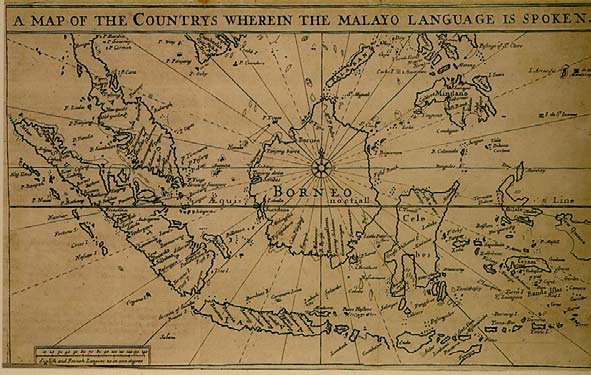Kamis sore, cuaca cukup cerah bikin gerah sembari membaca kabar dari negeri "dagelan" yang masuk pada episode "suap daging sapi", disinyalir juga terdapat gratifikasi seks.
Dari permasalahan kelakar calon hakim agung, berlanjut dengan gaya hidup bangsawan yang terungkap oleh kasus (mantan) Bupati Garut, meninggalnya bocah RI dan yang terbaru adalah gratifikasi seks dalam temuan kasus suap daging sapi. Tentunya masih ingat perilaku wakil rakyat yang pernah tertangkap sedang menonton video porno saat sidang, saya jadi berpikir: benarkah kita sedang serius mendirikan suatu negara?.
Atau memang kita ini adalah bangsa paling porno?~sedikit terbawa emosi sebab tiba-tiba saja saya meyakini bahwa Indonesia ini ada hanya karena iseng. Semoga hal itu tidak benar, semoga saja hanya karena kejengkelan saya saja.
Betapa tidak saya berpikirnya seperti itu melihat kenyataan dalam pergaulan masyarakat yang lebih mengesankan perilaku liberalisme-individualistik, serta polah kebangsawanan para politisi yang ternyata juga menjangkiti masyarakat. Gila hormat-gila kuasa, semuanya seputar masalah syahwat. Gila.
Tidak turut perilaku semacam ini dikatakan "tidak gaul" yang mengesankan tidak modern, dan tidak modern ini adalah dimana perilaku orang yang tidak "kebarat-baratan", barat, kalau bukan Amerika ya Eropa, Amerika isinya kebanyakan juga orang Eropa.
"Barat" dalam hal ini menunjuk pada gaya hidup dan segala pernak-pernik budaya orang-orang Amerika dan Eropa, sedangkan negara kita masih akrab dengan sebutan "negara dunia ketiga" atau sering pula disebut bangsa timur, bangsa timur yang memiliki stereotype tidak beradab dan harus mencontoh "barat".
Jadi teringat nasihat Pramoedya Ananta Toer "Jangan agungkan Eropa sebagai keseluruhan. Dimanapun ada yang mulia dan jahat... Kau sudah lupa kiranya. Nak, yang kolonial selalu iblis. Tak ada yang kolonial pernah mengindahkan kepentingan bangsamu." Demikian ia tulis dalam karyanya 'Anak Semua Bangsa' salah satu tetralogi yang belum rampung saya baca.
Bukan lantaran lewat tulisan ini saya turut mengampanyekan kebencian terhadap bangsa barat~dalam hal ini Eropa dan Amerika, bukan itu maksud saya sebab saya juga dalam kesadaran bahwa kebencian adalah musuh utama yang harus diperangi, karena kebencian dapat merubah seseorang menjadi mayat hidup, tanpa jiwa.
Hanya saja disini saya melihat masyarakat kita sudah keterlaluan dalam memposisikan dirinya, bukan berusaha untuk menyaingi kehebatan "orang barat" tadi, malah keasyikan mencontoh kegagalan "orang barat" membangun peradabannya, diperdaya dengan kebebasan individual yang pada dasarnya anti sosial. Lalu gagal pulalah kita merumuskan etika-estetika untuk mewujudkan bangsa yang beradab, secara tidak langsung kecenderungan yang ada adalah tingkah biadab.
Tentu saya pesimis, sebab bangsa ini tidak memiliki kemungkinan untuk memunculkan pemimpin. Hampir tidak terdapat lingkungan yang kondusif untuk melaksanakan pendidikan yang mampu melahirkan calon-calon pemimpin.
Bung Hatta pernah melontarkan kritik dengan mengutip ungkapan penyair Jerman, Schiller, pada tahun 60 an terhadap bangsa ini sebagai "suatu masa besar yang menemui manusia kerdil", meskipun yang diambil adalah kutipan dari seorang "bangsa barat" tapi sepertinya sangat relevan pada masa sekarang ini, betapa kita adalah sekumpulan manusia yang pongah, berpayah-payah menyatakan diri beragama tapi hati berkiblat pada kemegahan dunia yang serta merta selalu berupaya mencari kepuasan pribadi. Kita banyak melahirkan konsepsi yang kita sumbangkan kepada masyarakat dunia, tapi kini kita malah melupakannya.
Hari ini saya begitu pesimis, saya tidak mengerti dengan segala yang saya pikirkan saat ini. Indonesia, entah dimana.
Pramoedya Ananta Toer
Kamis, 31 Januari 2013
Rabu, 30 Januari 2013
"sepi ing pamrih, rame ing gawe" filosofi yang dipelintir
Rabu sore, hujan dan flu yang tak kunjung sembuh. Refleksi hari ini adalah filosofi "sepi ing pamrih, rame ing gawe" atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia "sepi dalam pamrih, ramai dalam bekerja" yang bukan berarti bekerja dengan cara acak-acakkan lalu teriak-teriak biar ramai, tapi ramai disini adalah "giat" atau dalam istilah jawanya "sregep".
Filosofi yang selalu menyertai setiap penataran P4 jaman SMP dulu disamping tenggang rasa, "tepo sliro", "mikul duwur mendem jero" dan segala hal yang sifatnya Jawa sentris. Pada waktu itu, meskipun sempat berpikir jika hal demikian dapat dimanfaatkan secara licik oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tapi baru beberapa tahun kemudian saya menyadari bahwa disatu sisi filosofi tersebut menyimpan kebaikan dan pada dasarnya adalah upaya penyeragaman setelah saya mengenal istilah "keterasingan" dan "ketergantungan" dari Karl Marx.
Saya selalu gagal menulis tentang ini, tentang filosofi "sepi ing pamrih, rame ing gawe" yang dipelintir sedemikian rupa untuk kepentingan perseorangan. Untuk mempermudah, saya akan ceritakan saja perjumpaan saya dengan salah seorang teman, guru pada salah satu sekolah swasta di Malang.
Saya kenali teman saya ini waktu masih kuliah di Universitas Negeri Malang, beda jurusan dengan saya, kenal akrab sebab sering nongkrong-ngopi diwarung. Sama gondrong.
Sepengetahuan saya, teman yang satu ini adalah mahasiwa "kupu" disebut seperti itu sebab tidak memiliki aktivitas lainnya selain kuliah-pulang, ngopi di kampus kalau ada kesempatan, tapi di sekolah tempat ia mengajar ia lebih dikenal sebagai mantan aktivis, demonstran dan seorang organisatoris, tidak tanggung ada yang bilang ia adalah seorang pendiri dari sebuah organisasi mahasiswa penggiat seni yang sebenarnya nama dari organisasi ini cukup "sangar" untuk didengar alias terkenal, dan sebenarnya sudah ada sebelum teman saya ini masuk.
Tidak begitu saya hiraukan, mungkin itu adalah sekedar tak-tik untuk mendapatkan pengakuan diri dari orang lain, yang saya pikir saat itu adalah karena ia lebih dulu masuk kedalam dunia pendidikan dalam hal mengajar, saya belakangan karena bertahun-tahun terjebak dalam dunia berita alias wartawan, saya berpikir saya harus dapat menggali pengalaman dari teman saya ini. Kami jadi akrab kembali.
Banyak hal yang ia ceritakan kepada saya, sudah pasti seputar lingkungan kerjanya yang katanya banyak berisi orang-orang munafik dan sistem yang ada disana adalah senioritas, sembari terus menghujat nama-nama seniornya, yang dikemudian hari dia katakan "saya tidak mempermasalahkan senioritas disini, saya adalah sedang menghormati mereka", padahal waktu itu saya sedang mengikuti alur pikirannya yang membenci senioritas. Toh pada akhirnya juga saya ketahui bahwa maksud teman saya ini ketika begitu menggebu-nggebu kebenciannya terhadap senioritas lantaran sakit hati yang berlebihan tentang pemberian tunjangan kepada para seniornya yang~katakanlah sedang pelit, sedangkan dia juga ikut mengajukan tapi gagal.
Pernah dengan berapi-api ia menceritakan hal ini hingga (mungkin) tanpa ia sadari bahwasannya saya adalah orang diluar lingkungannya dan tidak memiliki pengaruh apa-apa dengan ceramahnya itu. Tapi saat itu saya adalah juga seorang guru, jadi saya merasa harus mempelajarinya sebab saya juga merasa nantinya saya pasti akan bertemu dengan hal-hal seperti itu. Dan sekaligus pula saat itu saya sadari bahwa seorang guru pun juga sedang terjebak dalam keterasingan, entah setuju atau tidak atau bahkan nantinya saya akan dihujat saya katakan seperti itu dengan tidak bersepakat dengan apa yang dinamakan "sertifikasi" atau semacamnya.
Kembali pada teman saya, dimana sepanjang saya perhatikan ia adalah seorang pembuat onar dilingkungan kerjanya tapi dapat dikatakan posisinya "aman-aman saja" hingga saya ketahui teman saya ini memiliki kewenangan melebihi kewenangan seorang kepala sekolah, orang-orang yang dirasa cukup mengganggu atau mengancam kepentingannya bisa saja ia singkirkan tanpa harus diketahui oleh rekannya yang lain.
Saya cari tahu akan hal ini yang kemudian dia sendiri yang menjelaskan kepada saya "prinsip saya adalah membuat orang kecanduan kepada saya", sebenarnya sudah cukup jelas bagi saya, mengharapkan orang kecanduan sudah pasti adalah menciptakan keterasingan bagi orang lain, tentu seperti itu hingga atasannya saja harus tunduk pada dia. Tapi harus saya ketahui bagaimana teman saya ini mempraktekkan prinsipnya tersebut.
Mula-mula dan yang utama disini adalah keterampilan berperan, mengambil peran sebagai seorang korban atau pihak yang diasingkan, mungkin sudah keberuntungan bagi teman saya ini yang memiliki peran watak yang mumpuni sedemikian itu, lalu berusaha giat mengerjakan segala sesuatu dan membantu orang-orang disekitarnya, terus seperti itu hingga semua orang merasa ingin memanfaatkan tenaganya. Tidak lupa memanfaatkan perseteruan yang ada, menjual omongan sembari menghasut satu sama lain hingga semua orang merasa dia berada dipihaknya. Yang seperti ini tergolong cerdas atau licik?.
Dalam setiap yang ia kerjakan tentunya adalah pamrih, tapi semboyan yang selalu ia bicarakan adalah sebagaimana filosofi "sepi ing pamrih rame ing gawe" dan kali ini saya tidak dapat menahan diri, saya tidak bersepakat dengan prinsip teman saya ini.
Keterasingan adalah kondisi yang harus ditolak, meskipun memang pada dasarnya niat seseorang itu tidak dapat diketahui tapi disamping sebelumnya telah saya sadari prinsipnya, juga apapun yang berpeluang untuk menjebak orang terasing atas kemanusiaannya sedah semestinya diperangi, orang kehilangan jati dirinya adalah karena ia terasing atas kemanusiaanya.
Filosofi "sepi ing pamrih, rame ing gawe" pada akhirnya hanya dapat dipahami dan dilaksanakan oleh orang yang memiliki kesadaran tinggi, hidup hanyalah untuk mengabdi, bekerja dan berkarya tanpa terikat dengan hasilnya. Ikhlas tanpa batas. Tapi hal ini juga dapat menjadi propaganda yang efektif untuk memperdaya orang lain.
Filosofi yang selalu menyertai setiap penataran P4 jaman SMP dulu disamping tenggang rasa, "tepo sliro", "mikul duwur mendem jero" dan segala hal yang sifatnya Jawa sentris. Pada waktu itu, meskipun sempat berpikir jika hal demikian dapat dimanfaatkan secara licik oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tapi baru beberapa tahun kemudian saya menyadari bahwa disatu sisi filosofi tersebut menyimpan kebaikan dan pada dasarnya adalah upaya penyeragaman setelah saya mengenal istilah "keterasingan" dan "ketergantungan" dari Karl Marx.
Saya selalu gagal menulis tentang ini, tentang filosofi "sepi ing pamrih, rame ing gawe" yang dipelintir sedemikian rupa untuk kepentingan perseorangan. Untuk mempermudah, saya akan ceritakan saja perjumpaan saya dengan salah seorang teman, guru pada salah satu sekolah swasta di Malang.
Saya kenali teman saya ini waktu masih kuliah di Universitas Negeri Malang, beda jurusan dengan saya, kenal akrab sebab sering nongkrong-ngopi diwarung. Sama gondrong.
Sepengetahuan saya, teman yang satu ini adalah mahasiwa "kupu" disebut seperti itu sebab tidak memiliki aktivitas lainnya selain kuliah-pulang, ngopi di kampus kalau ada kesempatan, tapi di sekolah tempat ia mengajar ia lebih dikenal sebagai mantan aktivis, demonstran dan seorang organisatoris, tidak tanggung ada yang bilang ia adalah seorang pendiri dari sebuah organisasi mahasiswa penggiat seni yang sebenarnya nama dari organisasi ini cukup "sangar" untuk didengar alias terkenal, dan sebenarnya sudah ada sebelum teman saya ini masuk.
Tidak begitu saya hiraukan, mungkin itu adalah sekedar tak-tik untuk mendapatkan pengakuan diri dari orang lain, yang saya pikir saat itu adalah karena ia lebih dulu masuk kedalam dunia pendidikan dalam hal mengajar, saya belakangan karena bertahun-tahun terjebak dalam dunia berita alias wartawan, saya berpikir saya harus dapat menggali pengalaman dari teman saya ini. Kami jadi akrab kembali.
Banyak hal yang ia ceritakan kepada saya, sudah pasti seputar lingkungan kerjanya yang katanya banyak berisi orang-orang munafik dan sistem yang ada disana adalah senioritas, sembari terus menghujat nama-nama seniornya, yang dikemudian hari dia katakan "saya tidak mempermasalahkan senioritas disini, saya adalah sedang menghormati mereka", padahal waktu itu saya sedang mengikuti alur pikirannya yang membenci senioritas. Toh pada akhirnya juga saya ketahui bahwa maksud teman saya ini ketika begitu menggebu-nggebu kebenciannya terhadap senioritas lantaran sakit hati yang berlebihan tentang pemberian tunjangan kepada para seniornya yang~katakanlah sedang pelit, sedangkan dia juga ikut mengajukan tapi gagal.
Pernah dengan berapi-api ia menceritakan hal ini hingga (mungkin) tanpa ia sadari bahwasannya saya adalah orang diluar lingkungannya dan tidak memiliki pengaruh apa-apa dengan ceramahnya itu. Tapi saat itu saya adalah juga seorang guru, jadi saya merasa harus mempelajarinya sebab saya juga merasa nantinya saya pasti akan bertemu dengan hal-hal seperti itu. Dan sekaligus pula saat itu saya sadari bahwa seorang guru pun juga sedang terjebak dalam keterasingan, entah setuju atau tidak atau bahkan nantinya saya akan dihujat saya katakan seperti itu dengan tidak bersepakat dengan apa yang dinamakan "sertifikasi" atau semacamnya.
Kembali pada teman saya, dimana sepanjang saya perhatikan ia adalah seorang pembuat onar dilingkungan kerjanya tapi dapat dikatakan posisinya "aman-aman saja" hingga saya ketahui teman saya ini memiliki kewenangan melebihi kewenangan seorang kepala sekolah, orang-orang yang dirasa cukup mengganggu atau mengancam kepentingannya bisa saja ia singkirkan tanpa harus diketahui oleh rekannya yang lain.
Saya cari tahu akan hal ini yang kemudian dia sendiri yang menjelaskan kepada saya "prinsip saya adalah membuat orang kecanduan kepada saya", sebenarnya sudah cukup jelas bagi saya, mengharapkan orang kecanduan sudah pasti adalah menciptakan keterasingan bagi orang lain, tentu seperti itu hingga atasannya saja harus tunduk pada dia. Tapi harus saya ketahui bagaimana teman saya ini mempraktekkan prinsipnya tersebut.
Mula-mula dan yang utama disini adalah keterampilan berperan, mengambil peran sebagai seorang korban atau pihak yang diasingkan, mungkin sudah keberuntungan bagi teman saya ini yang memiliki peran watak yang mumpuni sedemikian itu, lalu berusaha giat mengerjakan segala sesuatu dan membantu orang-orang disekitarnya, terus seperti itu hingga semua orang merasa ingin memanfaatkan tenaganya. Tidak lupa memanfaatkan perseteruan yang ada, menjual omongan sembari menghasut satu sama lain hingga semua orang merasa dia berada dipihaknya. Yang seperti ini tergolong cerdas atau licik?.
Dalam setiap yang ia kerjakan tentunya adalah pamrih, tapi semboyan yang selalu ia bicarakan adalah sebagaimana filosofi "sepi ing pamrih rame ing gawe" dan kali ini saya tidak dapat menahan diri, saya tidak bersepakat dengan prinsip teman saya ini.
Keterasingan adalah kondisi yang harus ditolak, meskipun memang pada dasarnya niat seseorang itu tidak dapat diketahui tapi disamping sebelumnya telah saya sadari prinsipnya, juga apapun yang berpeluang untuk menjebak orang terasing atas kemanusiaannya sedah semestinya diperangi, orang kehilangan jati dirinya adalah karena ia terasing atas kemanusiaanya.
Filosofi "sepi ing pamrih, rame ing gawe" pada akhirnya hanya dapat dipahami dan dilaksanakan oleh orang yang memiliki kesadaran tinggi, hidup hanyalah untuk mengabdi, bekerja dan berkarya tanpa terikat dengan hasilnya. Ikhlas tanpa batas. Tapi hal ini juga dapat menjadi propaganda yang efektif untuk memperdaya orang lain.
Selasa, 29 Januari 2013
Tak-tik dan intrik politik
Tadi sempat berbincang-bincang dengan seorang teman, menganalisis setiap potensi dari fakta-fakta yang ada. Memang dalam suatu lingkungan yang tenang tapi menyimpan gemuruh adalah seperti melakukan meditasi diantara banyak ancaman yang senantiasa mengawasi. Walaupun hanya sebatas lingkungan kelompok pengajian.
Dari cerita teman saya ini saya dapati adalah sekumpulan orang yang sedang diombang-ambing keadaan akibat beberapa anggotanya berpolitik, jauh dari bayangan saya tentang perkumpulan pengajian yang berisi orang-orang yang haus akan ilmu, atau sekumpulan orang yang mencari tempat untuk menata hati ditengah kegaduhan rimba politik tanah air. Sempat saya maklumi tadi, bahwasannya dimanapun ada sekumpulan manusia disitu pula akan ada pertarungan untuk saling mendominasi satu sama lain, serta tipikal orang-orang kita hingga saat inipun masih mengupayakan kehormatan-kebangsawanan kalau boleh saya katakan demikian, tapi saya harus menemukan Indonesia, maka permakluman tadi harus saya singkirkan.
Ada beberapa nama disodorkan kepada saya dalam curhatnya, masing-masing punya andil. Kelompok pengajian ini tak ubahnya seperti sekolah, ada pencari ilmu~kalau disekolah ya murid dan penyampai ilmu yang kalau disekolah namanya guru; kalau dipengajian namanya ustad/ustadzah, ada seragam, iuran tidak lupa dengan bentuk arisan atau semacamnya (seperti halnya modifikasi koperasi sekolah), bedanya hanya pada persoalan ijazah.
Pengajian ini punya seorang ketua, ibaratnya kepala sekolah yang membawahi beberapa staff terpilih atas dasar senioritas, sebagaimana organisasi pada umumnya setiap anggota terpilih akan menjalankan fungsi yang telah dibebankan kepada mereka, dari sarana prasarana hingga hal-hal lain seperti perencanaan kegiatan kelompok. Mirip sekolah bukan? Kalau disekolah ada juga staff sarana prasarana, kesiswaan, humas, kurikulum dan sebagainya.
Entah karena hal apa kedudukan-kedudukan seperti itu menjadi maha penting bagi mereka hingga beberapa anggotanya melancarkan taktik dan intrik politik untuk mempertahankan dominasi atau sebut saja status quo.
Saya sebut status quo sebab mendengar penuturan teman saya yang menggambarkan sekelompok orang yang "anti perubahan", anti perubahan sekedar untuk melanggengkan keuntungan-keuntungan pribadi, hal yang sebenarnya telah disadari oleh seluruh anggota dan kemudian menimbulkan "gap" antara penghuni lingkungan.
Anggota muda dan beberapa senior menginginkan perubahan (perbaikan) dengan belajar dari segala kesalahan dan anggota senior lainnya malah bertanya "kenapa harus merubah sesuatu yang sudah ditata?"- menurut kisah teman saya, orang yang "berseloroh" demikian itu punya tipikal seorang oportunis yang juga gemar menyediakan jebakan bagi yang lain. Ketua yang sebagai pemimpin pun katanya tunduk pada orang ini meskipun bersusah payah menyatakan "netral".
Daripada saya berpanjang lebar menulis perwatakan dari orang yang diceritakan oleh teman saya ini, saya akan analogikan saja dengan tokoh wayang, dan sebenarnya juga tadi saya kisahkan kepada teman saya itu tentang tokoh Krisna. Watak terselubung dari orang yang diceritakan oleh teman saya ini saya gambarkan sebagaimana peran Krisna dalam bharatayuda.
Berawal dari pertanyaan yang saya selipkan ditengah gebalau kegalauannya "menurut anda, siapa yang paling baik antara Durna dan Krisna dalam lakon Bharatayudha?" Lalu teman saya menjawab "Krisna yang paling baik, sebab ia membela kebenaran dipihak Pandawa" dan Durno dia katakan sebagai pihak paling buruk.
Memang, Krisna ada dipihak Pandawa, tapi orang modern selalu salah menilai (mungkin hanya sekilas mendengar kisahnya), tapi posisi Krisna bukan sebagai petarung, dalam peperangan ia bertindak sebagai kusir kereta Arjuna, inilah peran utamanya dalam perang selain karena ia telah bersumpah untuk tidak membunuh siapapun dalam perang tersebut, juga karena sebelumnya ia telah banyak memakan korban akibat taktiknya.
Pertama, Krisna menyingkirkan saudara kembarnya sendiri, Baladewa dari aliansi Kurawa, berlanjut dengan siasatnya untuk menyirnakan kesaktian Antareja anak Bima. Krisna pun merupakan pengatur siasat dari kubu Pandawa meskipun ia sendiri menyatakan bahwa keberadaannya adalah netral, selain juga karena petunjuk para dewa untuk membuat peta pertarungan, siapa melawan siapa.
Sedangkan Durna atau biasa ditulis Druna dan biasa dilafal "Durno" adalah seorang guru baik dari Pandawa maupun dari Kurawa, sebagai seorang bagawan kesaktiannya cukup merisaukan hati Krisna, maka dalam pertempuran siasat Krisna pula yang telah membunuhnya. Durna sangat menyayangi anaknya, Aswatama, dan Krisna mengerti lebih dari hal itu, Durna hanya akan dapat dilukai ketika sedang bersedih. Namun permasalahannya adalah Aswatama lari sembunyi saat perang terjadi.
Setelah mengutus mata-mata yang telah mendapati seekor gajah dari pihak Kurawa yang kebetulan bernama Aswatama, maka Krisna mengatakan agar seluruh pasukan nantinya berteriak "Aswatama telah mati!" ketika berhasil membunuh gajah tersebut dalam pertempuran, dan jika Arjuna nanti ditanya oleh Durna tentang kebenaran hal itu maka Arjuna harus menjawab "benar, gajah Aswatama telah mati" dengan memperkecil suara saat mengatakan "gajah", hal ini terjadi karena Arjuna yang diketahui sebagai murid kesayangan Durna dan Arjuna adalah seorang kesatria yang tidak mau berbohong. Dan saat pertempuran terjadi, skenario ini berjalan dengan lancar sesuai rencana, Durna gugur akibat kesedihannya.
Nah demikian itu kurang-lebih sebagaimana yang digambarkan oleh teman saya lewat curhatnya, kisah inipun tadi juga sempat saya ceritakan kepada teman saya itu. Sekedar ingin menyampaikan kepada dia bahwa perlu menggunakan logika dalam menghadapi kondisi seperti itu, yaitu memakai sudut pandang politik dalam menanggapi tindakan-tindakan politis yang dirasa mengancam, toh kita juga harus terus mendidik masyarakat untuk sadar akan kedaulatannya, agar masyarakat terbebas dari mentalitas budak untuk menemukan Indonesia. Penguasaan manusia atas manusia harus didobrak hingga lingkup terkecil masyarakat negeri ini.
Kita harus mewujudkan tiap-tiap lingkungan yang kondusif yang mampu mendidik satu sama lain, intrik dan persengkongkolan hanya akan menimbulkan ketertutupan. Serta kepemimpinan seorang pemimpin, saya kata seperti itu sebab belum tentu seorang pemimpin memiliki kepemimpinan yang mumpuni sebagaimana cerita teman saya dan sebagaimana juga gambaran tokoh Krisna, tidak selayaknya pemimpin malah memihak ketika mendapati perpecahan, bharatayuda adalah kisah yang patut diteladani, mempelajarinya untuk menghindari kesalahan yang sama seperti dalam kisah tersebut. Bagi saya (hanya sekedar berandai-andai) Krisna mampu mencegah pertumpahan darah tersebut sebab dia adalah raja titisan dewa yang sakti dan cukup disegani, ini hanya berandai-andai. Sepatutnya pemimpin memfasilitasi perpecahan dengan keterbukaan untuk memecahkan persoalan yang ada, bukan malah mendukung status quo yang dirasa timpang.
Dari cerita teman saya ini saya dapati adalah sekumpulan orang yang sedang diombang-ambing keadaan akibat beberapa anggotanya berpolitik, jauh dari bayangan saya tentang perkumpulan pengajian yang berisi orang-orang yang haus akan ilmu, atau sekumpulan orang yang mencari tempat untuk menata hati ditengah kegaduhan rimba politik tanah air. Sempat saya maklumi tadi, bahwasannya dimanapun ada sekumpulan manusia disitu pula akan ada pertarungan untuk saling mendominasi satu sama lain, serta tipikal orang-orang kita hingga saat inipun masih mengupayakan kehormatan-kebangsawanan kalau boleh saya katakan demikian, tapi saya harus menemukan Indonesia, maka permakluman tadi harus saya singkirkan.
Ada beberapa nama disodorkan kepada saya dalam curhatnya, masing-masing punya andil. Kelompok pengajian ini tak ubahnya seperti sekolah, ada pencari ilmu~kalau disekolah ya murid dan penyampai ilmu yang kalau disekolah namanya guru; kalau dipengajian namanya ustad/ustadzah, ada seragam, iuran tidak lupa dengan bentuk arisan atau semacamnya (seperti halnya modifikasi koperasi sekolah), bedanya hanya pada persoalan ijazah.
Pengajian ini punya seorang ketua, ibaratnya kepala sekolah yang membawahi beberapa staff terpilih atas dasar senioritas, sebagaimana organisasi pada umumnya setiap anggota terpilih akan menjalankan fungsi yang telah dibebankan kepada mereka, dari sarana prasarana hingga hal-hal lain seperti perencanaan kegiatan kelompok. Mirip sekolah bukan? Kalau disekolah ada juga staff sarana prasarana, kesiswaan, humas, kurikulum dan sebagainya.
Entah karena hal apa kedudukan-kedudukan seperti itu menjadi maha penting bagi mereka hingga beberapa anggotanya melancarkan taktik dan intrik politik untuk mempertahankan dominasi atau sebut saja status quo.
Saya sebut status quo sebab mendengar penuturan teman saya yang menggambarkan sekelompok orang yang "anti perubahan", anti perubahan sekedar untuk melanggengkan keuntungan-keuntungan pribadi, hal yang sebenarnya telah disadari oleh seluruh anggota dan kemudian menimbulkan "gap" antara penghuni lingkungan.
Anggota muda dan beberapa senior menginginkan perubahan (perbaikan) dengan belajar dari segala kesalahan dan anggota senior lainnya malah bertanya "kenapa harus merubah sesuatu yang sudah ditata?"- menurut kisah teman saya, orang yang "berseloroh" demikian itu punya tipikal seorang oportunis yang juga gemar menyediakan jebakan bagi yang lain. Ketua yang sebagai pemimpin pun katanya tunduk pada orang ini meskipun bersusah payah menyatakan "netral".
Daripada saya berpanjang lebar menulis perwatakan dari orang yang diceritakan oleh teman saya ini, saya akan analogikan saja dengan tokoh wayang, dan sebenarnya juga tadi saya kisahkan kepada teman saya itu tentang tokoh Krisna. Watak terselubung dari orang yang diceritakan oleh teman saya ini saya gambarkan sebagaimana peran Krisna dalam bharatayuda.
Berawal dari pertanyaan yang saya selipkan ditengah gebalau kegalauannya "menurut anda, siapa yang paling baik antara Durna dan Krisna dalam lakon Bharatayudha?" Lalu teman saya menjawab "Krisna yang paling baik, sebab ia membela kebenaran dipihak Pandawa" dan Durno dia katakan sebagai pihak paling buruk.
Memang, Krisna ada dipihak Pandawa, tapi orang modern selalu salah menilai (mungkin hanya sekilas mendengar kisahnya), tapi posisi Krisna bukan sebagai petarung, dalam peperangan ia bertindak sebagai kusir kereta Arjuna, inilah peran utamanya dalam perang selain karena ia telah bersumpah untuk tidak membunuh siapapun dalam perang tersebut, juga karena sebelumnya ia telah banyak memakan korban akibat taktiknya.
Pertama, Krisna menyingkirkan saudara kembarnya sendiri, Baladewa dari aliansi Kurawa, berlanjut dengan siasatnya untuk menyirnakan kesaktian Antareja anak Bima. Krisna pun merupakan pengatur siasat dari kubu Pandawa meskipun ia sendiri menyatakan bahwa keberadaannya adalah netral, selain juga karena petunjuk para dewa untuk membuat peta pertarungan, siapa melawan siapa.
Sedangkan Durna atau biasa ditulis Druna dan biasa dilafal "Durno" adalah seorang guru baik dari Pandawa maupun dari Kurawa, sebagai seorang bagawan kesaktiannya cukup merisaukan hati Krisna, maka dalam pertempuran siasat Krisna pula yang telah membunuhnya. Durna sangat menyayangi anaknya, Aswatama, dan Krisna mengerti lebih dari hal itu, Durna hanya akan dapat dilukai ketika sedang bersedih. Namun permasalahannya adalah Aswatama lari sembunyi saat perang terjadi.
Setelah mengutus mata-mata yang telah mendapati seekor gajah dari pihak Kurawa yang kebetulan bernama Aswatama, maka Krisna mengatakan agar seluruh pasukan nantinya berteriak "Aswatama telah mati!" ketika berhasil membunuh gajah tersebut dalam pertempuran, dan jika Arjuna nanti ditanya oleh Durna tentang kebenaran hal itu maka Arjuna harus menjawab "benar, gajah Aswatama telah mati" dengan memperkecil suara saat mengatakan "gajah", hal ini terjadi karena Arjuna yang diketahui sebagai murid kesayangan Durna dan Arjuna adalah seorang kesatria yang tidak mau berbohong. Dan saat pertempuran terjadi, skenario ini berjalan dengan lancar sesuai rencana, Durna gugur akibat kesedihannya.
Nah demikian itu kurang-lebih sebagaimana yang digambarkan oleh teman saya lewat curhatnya, kisah inipun tadi juga sempat saya ceritakan kepada teman saya itu. Sekedar ingin menyampaikan kepada dia bahwa perlu menggunakan logika dalam menghadapi kondisi seperti itu, yaitu memakai sudut pandang politik dalam menanggapi tindakan-tindakan politis yang dirasa mengancam, toh kita juga harus terus mendidik masyarakat untuk sadar akan kedaulatannya, agar masyarakat terbebas dari mentalitas budak untuk menemukan Indonesia. Penguasaan manusia atas manusia harus didobrak hingga lingkup terkecil masyarakat negeri ini.
Kita harus mewujudkan tiap-tiap lingkungan yang kondusif yang mampu mendidik satu sama lain, intrik dan persengkongkolan hanya akan menimbulkan ketertutupan. Serta kepemimpinan seorang pemimpin, saya kata seperti itu sebab belum tentu seorang pemimpin memiliki kepemimpinan yang mumpuni sebagaimana cerita teman saya dan sebagaimana juga gambaran tokoh Krisna, tidak selayaknya pemimpin malah memihak ketika mendapati perpecahan, bharatayuda adalah kisah yang patut diteladani, mempelajarinya untuk menghindari kesalahan yang sama seperti dalam kisah tersebut. Bagi saya (hanya sekedar berandai-andai) Krisna mampu mencegah pertumpahan darah tersebut sebab dia adalah raja titisan dewa yang sakti dan cukup disegani, ini hanya berandai-andai. Sepatutnya pemimpin memfasilitasi perpecahan dengan keterbukaan untuk memecahkan persoalan yang ada, bukan malah mendukung status quo yang dirasa timpang.
Senin, 28 Januari 2013
Vasco Da Gama dan Syah Ismail lewat Novel "Suluk Malang Sungsang"
Dari kemarin saya mulai membaca novel Syaikh Siti Jenar tujuh jilid, sudah sejak ramadhan kemarin sebenarnya saya mulai membaca, kemarin melanjutkan jilid enam. Dari yang saya baca ini, saya sampai pada bagian yang menceritakan sepak terjang Vasco Da Gama, petualang yang berhasil menyusun rute perjalanan laut Portugal ke India. Pahlawan bagi bangsanya, rampok bagi bangsa timur, permulaan dari kekuatan kolonial pertama.
Saya juga suka penulisan Pak Agus Sunyoto yang menggambarkan perwatakan Da Gama dari tampilan fisiknya, terutama dari wajahnya.
Ia adalah perwira muda angkatan laut Portugis berpangkat kapten mayor yang dikenal orang di sekitarnya sebagai manusia kejam, telengas, tak kenal ampun, dingin, suka menghina orang, dan ahli dalam menyiksa tawanan. Gambaran tentang Vasco Da Gama sendiri bukanlah sesuatu yang berlebihan. Bagi mereka yang paham perwatakan manusia berdasar bentuk wajah, tentu akan mengamini gambaran itu. Matanya cekung dan tersembunyi di bawah alis tebal bentuk pedang melengkung mencerminkan kerakusan dan keganasan serigala yang memendam hasrat tak terpuaskan dan penuh diliputi kebencian. Hidungnya yang bengkok paruh rajawali menyembunyikan kelicikan dan jiwa pendendam seekor ular yang bercabang lidahnya, setiap ucapannya berbalut pamrih beracun. Tulang pipinya yang menonjol pada wajahnya yang tirus membiaskan keculasan dan kepura-puraan musang yang selalu mengintai kelengahan lawan. Bibirnya yang selalu terkatup sinis mengungkapkan kesombongan dan kekejaman buaya yang tak kenal ampun.
Demikian yang ditulis oleh Pak Agus pada halaman 207, ingin juga rasanya memiliki kemampuan menulis seperti itu. Saya sangat tertarik dan termotivasi karenanya. Lebih lanjut Pak Agus juga memberi perbandingan sosok dan perwatakan Vasco Da Gama yang terjebak dalam sempitnya kehidupan serba hitam-putih ini dengan sosok Syah Ismail, nama yang sebenarnya baru saja saya kenal, tentu lewat bukunya Pak Agus ini.
Syah Ismail, guru suci Tarekat Safawiyah yang menobatkan diri sebagai raja (syah) Persia. Dari kisah yang di tulis oleh Pak Agus ini, Syah Ismail memiliki bentuk wajah dan perwatakan yang mirip seperti Vasco Da Gama. Sama-sama ganas, sama-sama rakus dan tak kenal ampun. Perbedaannya~sebagaimana yang ditulis Pak Agus adalah jika Vasco Da Gama memandang hanya ada dua agama di dunia ini yaitu Islam dan Kristen dan dianggapnya saling bermusuhan satu sama lain, dan Syah Ismail memandang hanya dua agama juga yaitu sunni dan Syiah. Sama-sama berbalut kefanatikan hingga hanya terdapat dua jalan dalam mata mereka: sesat dan apa yang mereka sebut "jalan tuhan".
Jika Vasco Da Gama menganggap dirinya sebagai ksatria pilihan tuhan, Syah Ismail lebih pada kehadiran tuhan kepada dirinya, mungkin pengaruh Hindu atau mungkin juga dia memperoleh celah untuk ia manfaatkan, yaitu pola pikir masyarakatnya yang masih beranggapan bahwa raja adalah titisan tuhan.
Ada juga tulisan Pak Agus selanjutnya pada halaman 266 yang menceritakan kabar tentang kekejian dua orang tokoh tersebut, yaitu di Jawa, masyarakat Jawa kuno menggambarkan Syah Ismail dengan kebiasaan mereka akan perlambangan-perlambangan. Syah, sah yang berarti "menyingkir" dan "semal" yang berarti tupai. Siluman tupai.
Begitupun desas-desus tentang rencana Portugis untuk menyerang Nusa Jawa, Portugis mendapat julukannya pula disini, kata Portugis dilafal peranggi, menyerang secara membabi buta yang memberi kesan bahwa Portugis adalah kawanan siluman kerbau putih bermata kucing. Sedangkan pemimpinnya, Vasco Da Gama dianggap sebagai siluman bernama Kala Srenggi, siluman babi hutan bertaring besar yang berasal dari Nusa Pranggi (negara kacau). Demikian kurang-lebih yang ditulis oleh Pak Agus, selengkapnya baca sendiri.
Saya tertarik dari kisah ini adalah suatu usaha penaklukan atas dasar kerakusan yang bertopeng agama, baik oleh Vasco Da Gama maupun oleh Syah Ismail. Saya tertarik sebab akhir-akhir ini juga sering saya dengar tentang wacana negara khilafah yang mencuat diberbagai jejaring sosial dan selebaran-selebaran yang menolak pelaksanaan demokrasi dan mendukung terbentuknya khilafah, negara yang berdasarkan pada syariah.
Saya tidak begitu mengerti tentang ketatanegaraan, pun tentang keagamaan, hanya saja~sebagaimana imajinasi saya akan dua tokoh yang saya sebut diatas, apakah dalam khilafah nantinya manusia akan terhindar dari penguasaan manusia atas manusia? Atau jangan-jangan malah mengembalikan manusia pada permasalahan sebelumnya dimana manusia malah menuhankan manusia?.
Dan bukankah sangat mudah saat ini untuk kita temui kerakusan dan kepalsuan yang bertopeng keluhuran? Sungguhpun saya tidak mengerti. Begitu juga dengan demokrasi, yang pada dasarnya adalah sistem yang tidak pernah baku, tidak pernah ada "blue print" untuk melaksanakannya, kita menyesuaikan demokrasi dengan segala yang ada dan yang kita miliki. Tidak ada "cetak biru" untuk demokrasi meskipun Amerika Serikat ngotot dengan bentuk demokrasinya sebagai demokrasi yang terbaik, pun kita juga harus ngotot untuk menyempurnakan demokrasi kita yang tidak hanya sekedar permasalahan politik. Demokrasi adalah pancasila, demokrasi adalah bhineka tunggal ika, kita harus mulai untuk memanusiakan manusia meskipun berada dalam keragaman, dan jargon kita adalah "rahmatan lil'alamin".
Lewat tulisan ini saya juga sempatkan untuk menyampaikan (sebenarnya adalah kejengkelan saya) bahwa Indonesia adalah bukan kafir, sebab kita hanya mengenal dua kafir: Kafir dzimmi dan kafir harbi, tidak ada yang namanya kafir Indonesia atau semacamnya. Tidak ada.
Saya juga suka penulisan Pak Agus Sunyoto yang menggambarkan perwatakan Da Gama dari tampilan fisiknya, terutama dari wajahnya.
Ia adalah perwira muda angkatan laut Portugis berpangkat kapten mayor yang dikenal orang di sekitarnya sebagai manusia kejam, telengas, tak kenal ampun, dingin, suka menghina orang, dan ahli dalam menyiksa tawanan. Gambaran tentang Vasco Da Gama sendiri bukanlah sesuatu yang berlebihan. Bagi mereka yang paham perwatakan manusia berdasar bentuk wajah, tentu akan mengamini gambaran itu. Matanya cekung dan tersembunyi di bawah alis tebal bentuk pedang melengkung mencerminkan kerakusan dan keganasan serigala yang memendam hasrat tak terpuaskan dan penuh diliputi kebencian. Hidungnya yang bengkok paruh rajawali menyembunyikan kelicikan dan jiwa pendendam seekor ular yang bercabang lidahnya, setiap ucapannya berbalut pamrih beracun. Tulang pipinya yang menonjol pada wajahnya yang tirus membiaskan keculasan dan kepura-puraan musang yang selalu mengintai kelengahan lawan. Bibirnya yang selalu terkatup sinis mengungkapkan kesombongan dan kekejaman buaya yang tak kenal ampun.
Demikian yang ditulis oleh Pak Agus pada halaman 207, ingin juga rasanya memiliki kemampuan menulis seperti itu. Saya sangat tertarik dan termotivasi karenanya. Lebih lanjut Pak Agus juga memberi perbandingan sosok dan perwatakan Vasco Da Gama yang terjebak dalam sempitnya kehidupan serba hitam-putih ini dengan sosok Syah Ismail, nama yang sebenarnya baru saja saya kenal, tentu lewat bukunya Pak Agus ini.
Syah Ismail, guru suci Tarekat Safawiyah yang menobatkan diri sebagai raja (syah) Persia. Dari kisah yang di tulis oleh Pak Agus ini, Syah Ismail memiliki bentuk wajah dan perwatakan yang mirip seperti Vasco Da Gama. Sama-sama ganas, sama-sama rakus dan tak kenal ampun. Perbedaannya~sebagaimana yang ditulis Pak Agus adalah jika Vasco Da Gama memandang hanya ada dua agama di dunia ini yaitu Islam dan Kristen dan dianggapnya saling bermusuhan satu sama lain, dan Syah Ismail memandang hanya dua agama juga yaitu sunni dan Syiah. Sama-sama berbalut kefanatikan hingga hanya terdapat dua jalan dalam mata mereka: sesat dan apa yang mereka sebut "jalan tuhan".
Jika Vasco Da Gama menganggap dirinya sebagai ksatria pilihan tuhan, Syah Ismail lebih pada kehadiran tuhan kepada dirinya, mungkin pengaruh Hindu atau mungkin juga dia memperoleh celah untuk ia manfaatkan, yaitu pola pikir masyarakatnya yang masih beranggapan bahwa raja adalah titisan tuhan.
Ada juga tulisan Pak Agus selanjutnya pada halaman 266 yang menceritakan kabar tentang kekejian dua orang tokoh tersebut, yaitu di Jawa, masyarakat Jawa kuno menggambarkan Syah Ismail dengan kebiasaan mereka akan perlambangan-perlambangan. Syah, sah yang berarti "menyingkir" dan "semal" yang berarti tupai. Siluman tupai.
Begitupun desas-desus tentang rencana Portugis untuk menyerang Nusa Jawa, Portugis mendapat julukannya pula disini, kata Portugis dilafal peranggi, menyerang secara membabi buta yang memberi kesan bahwa Portugis adalah kawanan siluman kerbau putih bermata kucing. Sedangkan pemimpinnya, Vasco Da Gama dianggap sebagai siluman bernama Kala Srenggi, siluman babi hutan bertaring besar yang berasal dari Nusa Pranggi (negara kacau). Demikian kurang-lebih yang ditulis oleh Pak Agus, selengkapnya baca sendiri.
Saya tertarik dari kisah ini adalah suatu usaha penaklukan atas dasar kerakusan yang bertopeng agama, baik oleh Vasco Da Gama maupun oleh Syah Ismail. Saya tertarik sebab akhir-akhir ini juga sering saya dengar tentang wacana negara khilafah yang mencuat diberbagai jejaring sosial dan selebaran-selebaran yang menolak pelaksanaan demokrasi dan mendukung terbentuknya khilafah, negara yang berdasarkan pada syariah.
Saya tidak begitu mengerti tentang ketatanegaraan, pun tentang keagamaan, hanya saja~sebagaimana imajinasi saya akan dua tokoh yang saya sebut diatas, apakah dalam khilafah nantinya manusia akan terhindar dari penguasaan manusia atas manusia? Atau jangan-jangan malah mengembalikan manusia pada permasalahan sebelumnya dimana manusia malah menuhankan manusia?.
Dan bukankah sangat mudah saat ini untuk kita temui kerakusan dan kepalsuan yang bertopeng keluhuran? Sungguhpun saya tidak mengerti. Begitu juga dengan demokrasi, yang pada dasarnya adalah sistem yang tidak pernah baku, tidak pernah ada "blue print" untuk melaksanakannya, kita menyesuaikan demokrasi dengan segala yang ada dan yang kita miliki. Tidak ada "cetak biru" untuk demokrasi meskipun Amerika Serikat ngotot dengan bentuk demokrasinya sebagai demokrasi yang terbaik, pun kita juga harus ngotot untuk menyempurnakan demokrasi kita yang tidak hanya sekedar permasalahan politik. Demokrasi adalah pancasila, demokrasi adalah bhineka tunggal ika, kita harus mulai untuk memanusiakan manusia meskipun berada dalam keragaman, dan jargon kita adalah "rahmatan lil'alamin".
Lewat tulisan ini saya juga sempatkan untuk menyampaikan (sebenarnya adalah kejengkelan saya) bahwa Indonesia adalah bukan kafir, sebab kita hanya mengenal dua kafir: Kafir dzimmi dan kafir harbi, tidak ada yang namanya kafir Indonesia atau semacamnya. Tidak ada.
Minggu, 27 Januari 2013
Multi partai, nasib dan kepentingan rakyat
Orang kembar itu unik, dikatakan serupa tapi tak sama, bahkan yang identik seringnya hampir menipu mata. Saya tidak begitu mengerti tentang kejadian orang bisa jadi kembar, biarlah yang ahli yang menjelaskan hal tersebut. Keunikan ini juga ada digambarkan lewat tokoh wayang, Nakula-Sadewa, dua dari Pandawa lima.
Mungkin semua itu adalah fenomena, entah, mungkin juga sama seperti fenomena partai politik, hanya saja partai politik dengan jumlah yang begitu luar biasa bukan "serupa tapi tak sama", sebaliknya kebanyakan dari partai yang ada adalah "sama tapi tak serupa", tak sama nama, warna atau lambangnya saja, selebihnya mirip sama sekali. Bahkan ada tiga parpol yang menurut saya tipikalnya sama.
Jumlah yang ada dan sah menjadi peserta pemilu adalah sepuluh~saya rasa ini masih kebanyakan, seharusnya cukup lima parpol saja sudah cukup. Ini hanya penilaian saya saja, dari sudut pandang saya sebagai salah seorang rakyat yang seringnya dikhianati.
Menilik kembali fungsi partai politik untuk menampung aspirasi masyarakat yang berwarna-warni, melalui proses selektif suara rakyat yang bercampur-baur itu akan baku dalam partai politik, sesuai kepentingan. Jadi bingung kalau faktanya adalah suara rakyat yang beragam tersebut mendapati "sajian" parpol-parpol yang hanya beda nama, warna dan lambang tapi tipikal orangnya sama semua. Atau mungkin semua ini adalah pesebaran kader golongan tertentu yang berada di balik parpol-parpol tersebut? Entah, dan jika hal ini benar maka demokrasi di negeri ini adalah hal yang percuma, sebab mau diotak-atik seperti apapun pada dasarnya yang menang adalah golongan tersebut.
Saya jadi ingat waktu masih kuliah dulu, beberapa teman mahasiswa memang ada yang sengaja menjalankan politik praksis, sebagian yang lain tanpa sengaja yaitu tunduk akibat aksi "ideologis" kawan yang lain, dan bagian terbesarnya adalah cari selamat dengan bersikap netral tapi memihak, pragmatis.
Kekuasaan dan kedudukan adalah hal utama dan penting waktu itu, termasuk menduduki jabatan ketua "offring", demikian masing-masing pihak berupaya mendominasi, pada waktu itu kondisi politik nasional juga teramat gaduh. Dari angkatan saya di jurusan PPKn terbagi dalam empat faksi, saya sendiri lebih dekat dengan "faksi merah" (saya tidak akan menyebut organisasinya, khawatir nantinya akan bermasalah, sebab saya tidak masuk dalam organisasi-organisasi tersebut, hanya sekedar dekat saja) berhadapan langsung dengan organisasi paling dominan waktu itu. Tidak hanya perang wacana, pertarungan fisik pun juga terjadi. Kekerasan dalam segala hal dan dalam segala cara.
Yang menarik adalah intrik yang dilakukan oleh organisasi yang dominan waktu itu, selain melakukan "show of force" lewat demonstrasi-demonstrasi juga penyusupan dan pemecahan suara lewat wacana. Saya hanya "geleng-geleng" kepala.
Pernah dalam suatu pemilihan ketua HMJ yang dilaksanakan dengan tata cara debat terbuka setelah penyebaran brosur dan sebelum pemilihan berlangsung, teman-teman dari organisasi dominan ini mempraktekkan "trik" pemecahan suara. Ada sekitar lima orang anggotanya yang paling vokal waktu itu disebar, tidak bergerombol, tapi berpencar dalam satu ruang.
Giliran kandidat yang muncul dengan mengusung bendera seterunya langsung saja kelima orang ini mengepung dengan pertanyaan-pertanyaan. Padahal jumlah mereka sedikit, tapi seperti tersihir orang-orang dalam ruangan tersebut merasa pertanyaan-pertanyaan dari kelima orang tersebut adalah suara penentang yang dominan. Hal ini selain kandidat yang sedang dicerca pertanyaan dari awal sudah kalah kharismanya, pun hanya dua orang dari jurusan saya yang menjadi kader "faksi merah" ini, saya dekat dengan kelompok ini hanyalah karena merasa punya sudut pandang yang sama, dan sebenarnya saya malah sedang berada lebih "kiri" dari mereka.
Dan sebenarnya juga saya sudah mengetahui perilaku orang-orang ini diluar kegiatan politik praksisnya, minum kopi bersama tanpa diketahui oleh yang lain. Payah.
Tulisan ini hanya sekedar cerita dari ingatan dan sudut pandang saya tanpa ada upaya untuk menyerang salah satu pihak yang termuat dalam tulisan ini, toh sedari awal saya sudah sadar bahwa mereka pada waktu itu sedang dibingungkan oleh konsepsi ideologi yang datang dari luar diri mereka, meskipun sudah cukup jelas, pada waktu itu mereka ada di jurusan pancasila. Tapi mereka bingung.
Saya yakin, kini teman-teman saya itu yang berkesempatan jadi guru pasti sedang mati-matian membela jurusannya untuk juga membela kepentingan pribadi mereka sendiri. Apapun warna bendera mereka waktu itu, mereka adalah kaum liberal, kini (mungkin) sama-sama pragmatis.
Partai politik adalah sangat penting bagi berlangsungnya demokrasi, diluar demokrasi hanya sistem dengan partai tunggal, bahkan hampir tidak terdapat suatu negara tanpa partai, dan dalam penerapan demokrasi dengan multi partai semacam negeri ini hanya akan menjadi pemborosan, pemborosan dalam segala hal. Mungkin untuk menghindari terjadinya mayoritas suara, tapi apalah artinya jika malah terjebak dalam masyarakat kelas dengan dominannya kepentingan kelas dalam masyarakat?.
Memang demokrasi bukanlah konsep baku, kita harus menyempurnakan demokrasi ini, dan tidak salah rasanya untuk selalu belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Saya hanya sekedar khawatir kalau-kalau yang sedang berlangsung saat ini adalah sama halnya dengan pengalaman yang saya dapati ketika masih kuliah dulu. Jika benar, maka suara rakyat hanya sekedar objek perjudian, dan semoga saja tidak benar, semoga saja hanya sekedar kekhawatiran yang tidak mendasar dari kalangan jelata yang terlalu sering dikhianati ini. Semoga.
A tribute to Dion, Eko, Andik, Dian dan Anam, mungkin kita tidak akan pernah mampu untuk terlepas dari kemungkinan-kemungkinan seperti yang pernah kita saksikan bersama, mungkin kita akan sadar nantinya bahwa bodoh dan ketidak tahuan adalah nikmat bagi mereka yang hidup di negeri ini. Salam.
Mungkin semua itu adalah fenomena, entah, mungkin juga sama seperti fenomena partai politik, hanya saja partai politik dengan jumlah yang begitu luar biasa bukan "serupa tapi tak sama", sebaliknya kebanyakan dari partai yang ada adalah "sama tapi tak serupa", tak sama nama, warna atau lambangnya saja, selebihnya mirip sama sekali. Bahkan ada tiga parpol yang menurut saya tipikalnya sama.
Jumlah yang ada dan sah menjadi peserta pemilu adalah sepuluh~saya rasa ini masih kebanyakan, seharusnya cukup lima parpol saja sudah cukup. Ini hanya penilaian saya saja, dari sudut pandang saya sebagai salah seorang rakyat yang seringnya dikhianati.
Menilik kembali fungsi partai politik untuk menampung aspirasi masyarakat yang berwarna-warni, melalui proses selektif suara rakyat yang bercampur-baur itu akan baku dalam partai politik, sesuai kepentingan. Jadi bingung kalau faktanya adalah suara rakyat yang beragam tersebut mendapati "sajian" parpol-parpol yang hanya beda nama, warna dan lambang tapi tipikal orangnya sama semua. Atau mungkin semua ini adalah pesebaran kader golongan tertentu yang berada di balik parpol-parpol tersebut? Entah, dan jika hal ini benar maka demokrasi di negeri ini adalah hal yang percuma, sebab mau diotak-atik seperti apapun pada dasarnya yang menang adalah golongan tersebut.
Saya jadi ingat waktu masih kuliah dulu, beberapa teman mahasiswa memang ada yang sengaja menjalankan politik praksis, sebagian yang lain tanpa sengaja yaitu tunduk akibat aksi "ideologis" kawan yang lain, dan bagian terbesarnya adalah cari selamat dengan bersikap netral tapi memihak, pragmatis.
Kekuasaan dan kedudukan adalah hal utama dan penting waktu itu, termasuk menduduki jabatan ketua "offring", demikian masing-masing pihak berupaya mendominasi, pada waktu itu kondisi politik nasional juga teramat gaduh. Dari angkatan saya di jurusan PPKn terbagi dalam empat faksi, saya sendiri lebih dekat dengan "faksi merah" (saya tidak akan menyebut organisasinya, khawatir nantinya akan bermasalah, sebab saya tidak masuk dalam organisasi-organisasi tersebut, hanya sekedar dekat saja) berhadapan langsung dengan organisasi paling dominan waktu itu. Tidak hanya perang wacana, pertarungan fisik pun juga terjadi. Kekerasan dalam segala hal dan dalam segala cara.
Yang menarik adalah intrik yang dilakukan oleh organisasi yang dominan waktu itu, selain melakukan "show of force" lewat demonstrasi-demonstrasi juga penyusupan dan pemecahan suara lewat wacana. Saya hanya "geleng-geleng" kepala.
Pernah dalam suatu pemilihan ketua HMJ yang dilaksanakan dengan tata cara debat terbuka setelah penyebaran brosur dan sebelum pemilihan berlangsung, teman-teman dari organisasi dominan ini mempraktekkan "trik" pemecahan suara. Ada sekitar lima orang anggotanya yang paling vokal waktu itu disebar, tidak bergerombol, tapi berpencar dalam satu ruang.
Giliran kandidat yang muncul dengan mengusung bendera seterunya langsung saja kelima orang ini mengepung dengan pertanyaan-pertanyaan. Padahal jumlah mereka sedikit, tapi seperti tersihir orang-orang dalam ruangan tersebut merasa pertanyaan-pertanyaan dari kelima orang tersebut adalah suara penentang yang dominan. Hal ini selain kandidat yang sedang dicerca pertanyaan dari awal sudah kalah kharismanya, pun hanya dua orang dari jurusan saya yang menjadi kader "faksi merah" ini, saya dekat dengan kelompok ini hanyalah karena merasa punya sudut pandang yang sama, dan sebenarnya saya malah sedang berada lebih "kiri" dari mereka.
Dan sebenarnya juga saya sudah mengetahui perilaku orang-orang ini diluar kegiatan politik praksisnya, minum kopi bersama tanpa diketahui oleh yang lain. Payah.
Tulisan ini hanya sekedar cerita dari ingatan dan sudut pandang saya tanpa ada upaya untuk menyerang salah satu pihak yang termuat dalam tulisan ini, toh sedari awal saya sudah sadar bahwa mereka pada waktu itu sedang dibingungkan oleh konsepsi ideologi yang datang dari luar diri mereka, meskipun sudah cukup jelas, pada waktu itu mereka ada di jurusan pancasila. Tapi mereka bingung.
Saya yakin, kini teman-teman saya itu yang berkesempatan jadi guru pasti sedang mati-matian membela jurusannya untuk juga membela kepentingan pribadi mereka sendiri. Apapun warna bendera mereka waktu itu, mereka adalah kaum liberal, kini (mungkin) sama-sama pragmatis.
Partai politik adalah sangat penting bagi berlangsungnya demokrasi, diluar demokrasi hanya sistem dengan partai tunggal, bahkan hampir tidak terdapat suatu negara tanpa partai, dan dalam penerapan demokrasi dengan multi partai semacam negeri ini hanya akan menjadi pemborosan, pemborosan dalam segala hal. Mungkin untuk menghindari terjadinya mayoritas suara, tapi apalah artinya jika malah terjebak dalam masyarakat kelas dengan dominannya kepentingan kelas dalam masyarakat?.
Memang demokrasi bukanlah konsep baku, kita harus menyempurnakan demokrasi ini, dan tidak salah rasanya untuk selalu belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Saya hanya sekedar khawatir kalau-kalau yang sedang berlangsung saat ini adalah sama halnya dengan pengalaman yang saya dapati ketika masih kuliah dulu. Jika benar, maka suara rakyat hanya sekedar objek perjudian, dan semoga saja tidak benar, semoga saja hanya sekedar kekhawatiran yang tidak mendasar dari kalangan jelata yang terlalu sering dikhianati ini. Semoga.
A tribute to Dion, Eko, Andik, Dian dan Anam, mungkin kita tidak akan pernah mampu untuk terlepas dari kemungkinan-kemungkinan seperti yang pernah kita saksikan bersama, mungkin kita akan sadar nantinya bahwa bodoh dan ketidak tahuan adalah nikmat bagi mereka yang hidup di negeri ini. Salam.
Sabtu, 26 Januari 2013
Demokrasi dan teknologi, antara manfaat dan mudharat
Pulang lebih awal, di sekolah ada kegiatan Maulid Nabi, istilahnya "muludtan" untuk memperingati hari kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Anak-anak tadi dikumpulkan ditengah lapangan untuk mendengarkan ceramah. Kurang tahu nama ustadnya.
Banyak hal diungkap dengan sedikit menggelitik, bukan menghujat tapi menampar-nampar pendengarnya, hebat, dalam hati pun saya berdoa "semoga bermanfaat dan memberi banyak kesadaran, aamiin". Realitas memang harus selalu didobrak.
Saya tidak akan mengulas isi ceramah tersebut atau sekedar menceritakan suasananya, saya hanya akan mengambil sebagian kecil dari isi ceramah, yaitu tentang teknologi. Menurut pak ustad tadi teknologi itu tergantung pemakainya, jika digunakan oleh orang yang berilmu maka akan bernilai manfaat, dan jika ada ditangan yang keliru malah akan menjadi mudharat. Tadi beliau bikin contohnya juga, mengenai penggunaan telephon genggam, dengan bahasa khas pesantren yang tidak banyak saya ketahui, kurang lebih seperti penggunaan fasilitas SMS, jika dilakukan oleh orang yang berilmu maka bermanfaat untuk menjalin silaturahmi, sebaliknya, ketika dioperasionalkan oleh orang yang salah maka akan menjadi "Sarana-Modal Selingkuh".
Semacam pisau, dan pisau ini adalah hasil budaya yang sama halnya dengan telephon genggam. Pisau ditangan orang berilmu akan menjadi manfaat, misalnya untuk masak, tapi jadi masalah ketika digenggam oleh tangan yang salah, misalnya membunuh. Teknologi itu ibarat pisau disini, atau mungkin bisa saja diibaratkan sebagai pisau bermata dua.
Tergantung pemakainya, apakah dia berilmu atau tidak, baik atau buruk, teknologi hanya sekedar mengikuti. Beradab tidaknya pengguna adalah faktor penting dalam memberi nilai teknologi.
Begitupun dengan apa yang kita sebut "demokrasi", sistem yang memang dirumuskan untuk dapat bermanfaat bagi orang banyak. Demokrasi memang labil, dia bukan konsep baku dengan suatu "blue print" untuk melaksanakannya. Hanya menyertakan dua syarat, selebihnya diserahkan kepada para pelakunya, yang pertama adalah pengakuan HAM dan yang kedua adalah pengakuan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.
Demokrasi adalah hasil peradaban yang tinggi, sepanjang usianya pun juga telah mengalami banyak uji. Ia bisa dilaksanakan oleh semua manusia, baik yang beradab maupun yang biadab sekalipun, bagai pisau bermata dua, menyimpan manfaat sekaligus mudharat tergantung penggunaannya. Jika yang menggunakan adalah orang yang berilmu maka bermanfaat. Tapi jika pelakunya sendiri adalah masyarakat yang miskin akan etika-estetika yang berarti juga miskin ilmu, maka bukan manfaat yang dipetik malah mudharat yang dengan terpaksa kita nikmati.
Bisa dibayangkan ketika demokrasi dilaksanakan oleh masyarakat yang belum mampu keluar dari pola pikir feodalistiknya, demokrasi hanya akan sekedar menjadi sarana penguasaan manusia atas manusia. Ini kemungkinan terburuknya. Dan dominasi mayoritas sebagaimana dalam pelaksanaan demokrasi liberal adalah memunculkan ketidak adilan. Apalagi jika dilaksanakan oleh masyarakat yang masih cenderung menggunakan kekerasan, demokrasi hanya akan menjadi pintu gerbang pertikaian.
Semua pihak bisa hidup dalam demokrasi, termasuk pihak yang anti terhadap demokrasi itu sendiri.
Banyak hal diungkap dengan sedikit menggelitik, bukan menghujat tapi menampar-nampar pendengarnya, hebat, dalam hati pun saya berdoa "semoga bermanfaat dan memberi banyak kesadaran, aamiin". Realitas memang harus selalu didobrak.
Saya tidak akan mengulas isi ceramah tersebut atau sekedar menceritakan suasananya, saya hanya akan mengambil sebagian kecil dari isi ceramah, yaitu tentang teknologi. Menurut pak ustad tadi teknologi itu tergantung pemakainya, jika digunakan oleh orang yang berilmu maka akan bernilai manfaat, dan jika ada ditangan yang keliru malah akan menjadi mudharat. Tadi beliau bikin contohnya juga, mengenai penggunaan telephon genggam, dengan bahasa khas pesantren yang tidak banyak saya ketahui, kurang lebih seperti penggunaan fasilitas SMS, jika dilakukan oleh orang yang berilmu maka bermanfaat untuk menjalin silaturahmi, sebaliknya, ketika dioperasionalkan oleh orang yang salah maka akan menjadi "Sarana-Modal Selingkuh".
Semacam pisau, dan pisau ini adalah hasil budaya yang sama halnya dengan telephon genggam. Pisau ditangan orang berilmu akan menjadi manfaat, misalnya untuk masak, tapi jadi masalah ketika digenggam oleh tangan yang salah, misalnya membunuh. Teknologi itu ibarat pisau disini, atau mungkin bisa saja diibaratkan sebagai pisau bermata dua.
Tergantung pemakainya, apakah dia berilmu atau tidak, baik atau buruk, teknologi hanya sekedar mengikuti. Beradab tidaknya pengguna adalah faktor penting dalam memberi nilai teknologi.
Begitupun dengan apa yang kita sebut "demokrasi", sistem yang memang dirumuskan untuk dapat bermanfaat bagi orang banyak. Demokrasi memang labil, dia bukan konsep baku dengan suatu "blue print" untuk melaksanakannya. Hanya menyertakan dua syarat, selebihnya diserahkan kepada para pelakunya, yang pertama adalah pengakuan HAM dan yang kedua adalah pengakuan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.
Demokrasi adalah hasil peradaban yang tinggi, sepanjang usianya pun juga telah mengalami banyak uji. Ia bisa dilaksanakan oleh semua manusia, baik yang beradab maupun yang biadab sekalipun, bagai pisau bermata dua, menyimpan manfaat sekaligus mudharat tergantung penggunaannya. Jika yang menggunakan adalah orang yang berilmu maka bermanfaat. Tapi jika pelakunya sendiri adalah masyarakat yang miskin akan etika-estetika yang berarti juga miskin ilmu, maka bukan manfaat yang dipetik malah mudharat yang dengan terpaksa kita nikmati.
Bisa dibayangkan ketika demokrasi dilaksanakan oleh masyarakat yang belum mampu keluar dari pola pikir feodalistiknya, demokrasi hanya akan sekedar menjadi sarana penguasaan manusia atas manusia. Ini kemungkinan terburuknya. Dan dominasi mayoritas sebagaimana dalam pelaksanaan demokrasi liberal adalah memunculkan ketidak adilan. Apalagi jika dilaksanakan oleh masyarakat yang masih cenderung menggunakan kekerasan, demokrasi hanya akan menjadi pintu gerbang pertikaian.
Semua pihak bisa hidup dalam demokrasi, termasuk pihak yang anti terhadap demokrasi itu sendiri.
Jumat, 25 Januari 2013
Pembenahan, belajar dari sejarah jahiliyah dan serat darmaghandul
Jum'at sore, kegiatan teater sengaja saya hentikan, saya lagi tidak ingin kena angin. Sudah beberapa hari ini gigi geraham sebelah kiri melakukan pemberontakan, dan sedang benar-benar kena serangan flu, perih-kering rasanya tenggorokkan.
Tadi pas sholat Jum'at khotibnya membahas tentang istilah "jahiliyah" dan seperti biasanya kalau urusan pengetahuan keagamaan saya masih rendah pengetahuannya. Setahu saya istilah ini merupakan kondisi suatu bangsa, sebagaimana pernah terjadi di Eropa, jaman kegelapan, sedang "jahiliyah" menimpa bangsa Arab. Jahiliyah bermakna bodoh-kebodohan, dan menurut bapak khotib tadi yang dimaksud "jahiliyah" disini bukanlah jaman dimana bangsa Arab sedang bodoh-bodohnya, sebaliknya pada masa itu bangsa Arab sedang gencar-gencarnya mengembangkan kasusastran.
Berarti pada waktu itu merupakan puncak dari kebudayaan bangsa Arab, bangsa yang sedang mengembangkan kasusastran adalah bangsa yang telah menemukan jati diri dan sedang mengupayakan peradaban, peradaban suatu bangsa itu ada karena etika-estetikanya dan lewat kasusastranlah semua itu dapat diabadikan.
Tapi kenapa disebut dengan istilah "jahiliyah"? Nah dari sini bapak khotib tadi menjelaskan bahwa "jahiliyah" ini terdiri atas empat macam, maksudnya empat macam kebodohan. Pertama, bodoh hukumnya, dimana hukum hanya memihak pada kalangan berkuasa.
Tentunya memang hal bodoh, mengingat peranan hukum dalam masyarakat adalah untuk ketertiban dan mencapai keadilan demi kesejahteraan bersama, bagaimana mungkin ketertiban dan keadilan dapat diwujudkan jika hukumnya hanya berlaku bagi masyarakat bawah, sedangkan sangat toleran bagi masyarakat kelas atas, lebih-lebih penguasa.
Kedua, bodoh adatnya, dimana terjadi jual-beli manusia sebagai budak, bahkan ada kebiasaan untuk saling bertukar istri. Kalau seperti ini sebenarnya sudah kepalang bodohnya, bagaimanapun tindakan dan perilaku yang tidak memanusiakan manusia adalah kebodohan. Titik.
Ketiga adalah bodoh karena kesombongannya, sudah pasti orang sombong karena tidak memanusiakan manusia, penguasaan manusia atas manusia salah satu unsurnya adalah kesombongan, yang kuat yang menang, siapa cepat dia dapat. Individualistis, tanpa ada kesadaran sosial, serakah.
Juga diceritakan bahwa waktu itu cara berpakaian bangsa Arab cenderung vulgar, lebih mengutamakan tampilan sexual dengan serba ketat dan-katakanlah "tidak tersamar". Sulit juga mencari kata buat menggambarkannya.
Pikiran saya saat itu "bukankah memang sedang benar-benar bodoh-bodohnya bangsa Arab? Lalu, kira-kira isi muatan kasusastrannya apa?" Keheranan saya adalah pada tindakan tidak manusiawi yang tengah digambarkan, dan hampir juga saya teriak "itu bukan jahiliyah, itu masyarakat yang kini sedang menamai dirinya Indonesia!" Tapi hampir, untunglah saya sedang sadar sesadar-sadarnya bahwa Indonesia akan segera saya temukan, dan pada dasarnya tidak boleh ada perdebatan ataupun protes dalam mimbar Jum'at.
Kondisi tersebut dapat terhenti dengan kehadiran Rasulullah Shalallahu'alaihi Wassalam, Nabi besar yang hadir dijaman akhir yang berhasil melancarkan revolusi, tidak dengan senjata atau sekedar protes, dengan konsepsi sederhana yang menggugah kesadaran lewat keteladanan, menyampaikan kabar kemenangan bagi orang-orang beriman. Rahmatan lil'alamin.
Sebelumnya saya sempatkan baca darmagandhul, serat yang terbit beratus-ratus tahun yang lalu di tanah Jawa, bercerita tentang runtuhnya Majapahit akibat ajaran Islam yang dikatakannya "menggurita", kalau yang saya ketahui dari pelajaran sejarah, runtuhnya dinasti besar ini karena perang saudara.
Dari yang saya baca tadi, mengenai perjalanan Sunan Bonang di wilayah Kediri, dalam perjalanannya Sunan Bonang sempat berdebat dengan raja jin setempat karena Sunan Bonang telah memberi kutukan terhadap masyarakat sebuah desa di (mungkin) seputaran Nganjuk. Aliran sungai dia alihkan hingga menerpa desa, para jejaka dan perawannya dia kutuk akan menikah di usia tua. Kutukan tersebut terjadi akibat ulah seorang gadis desa yang salah sangka, ketika seorang murid dari Sunan yang diutus mencari air minum dan wudlu disangka hendak berbuat jahat, tidak mendapat air malah hinaan dan cacian dari sang gadis yang kemudian ia laporkan kepada Sunan. Marah dan mengutuk akhirnya.
Dari cerita perdebatan antara Sunan dan raja jin ini saya dapati suatu pemikiran, meskipun sangat jauh dari isi sampaian serat tersebut, yaitu ketika menyampaikan kabar gembira, syiar agama yang "rahmatan lil'alamin" ini adalah lebih baik dengan cara yang rahmatan lil'alamin juga. Tidak perlu merusak apalagi hingga menimbulkan permusuhan. Baik-buruknya kita kembalikan kepada Yang Maha Esa.
Membangun bangsa berakhlak mulia tidaklah dengan kekerasan, apalagi perang, penaklukkan hanya akan menyelipkan dendam. Dalam hal ini saya masih kabur, apakah Islam masuk ke nusantara dengan cara damai atau lewat penaklukkan tadi? Sejarahnya saya baca hanya sepotong-sepotong. Dan kenyataan berkisah lain, wajah garang pembela ajaran Rasulullah yang-sama sekali-jauh dari jargon rahmatan lil'alamin.
Sekali lagi, kedisiplinan tidak akan muncul dari ketakutan, masalah akhlak, masalah moral adalah pembenahan lewat keteladanan, tentunya dengan membuka ruang dialog.
Tadi pas sholat Jum'at khotibnya membahas tentang istilah "jahiliyah" dan seperti biasanya kalau urusan pengetahuan keagamaan saya masih rendah pengetahuannya. Setahu saya istilah ini merupakan kondisi suatu bangsa, sebagaimana pernah terjadi di Eropa, jaman kegelapan, sedang "jahiliyah" menimpa bangsa Arab. Jahiliyah bermakna bodoh-kebodohan, dan menurut bapak khotib tadi yang dimaksud "jahiliyah" disini bukanlah jaman dimana bangsa Arab sedang bodoh-bodohnya, sebaliknya pada masa itu bangsa Arab sedang gencar-gencarnya mengembangkan kasusastran.
Berarti pada waktu itu merupakan puncak dari kebudayaan bangsa Arab, bangsa yang sedang mengembangkan kasusastran adalah bangsa yang telah menemukan jati diri dan sedang mengupayakan peradaban, peradaban suatu bangsa itu ada karena etika-estetikanya dan lewat kasusastranlah semua itu dapat diabadikan.
Tapi kenapa disebut dengan istilah "jahiliyah"? Nah dari sini bapak khotib tadi menjelaskan bahwa "jahiliyah" ini terdiri atas empat macam, maksudnya empat macam kebodohan. Pertama, bodoh hukumnya, dimana hukum hanya memihak pada kalangan berkuasa.
Tentunya memang hal bodoh, mengingat peranan hukum dalam masyarakat adalah untuk ketertiban dan mencapai keadilan demi kesejahteraan bersama, bagaimana mungkin ketertiban dan keadilan dapat diwujudkan jika hukumnya hanya berlaku bagi masyarakat bawah, sedangkan sangat toleran bagi masyarakat kelas atas, lebih-lebih penguasa.
Kedua, bodoh adatnya, dimana terjadi jual-beli manusia sebagai budak, bahkan ada kebiasaan untuk saling bertukar istri. Kalau seperti ini sebenarnya sudah kepalang bodohnya, bagaimanapun tindakan dan perilaku yang tidak memanusiakan manusia adalah kebodohan. Titik.
Ketiga adalah bodoh karena kesombongannya, sudah pasti orang sombong karena tidak memanusiakan manusia, penguasaan manusia atas manusia salah satu unsurnya adalah kesombongan, yang kuat yang menang, siapa cepat dia dapat. Individualistis, tanpa ada kesadaran sosial, serakah.
Juga diceritakan bahwa waktu itu cara berpakaian bangsa Arab cenderung vulgar, lebih mengutamakan tampilan sexual dengan serba ketat dan-katakanlah "tidak tersamar". Sulit juga mencari kata buat menggambarkannya.
Pikiran saya saat itu "bukankah memang sedang benar-benar bodoh-bodohnya bangsa Arab? Lalu, kira-kira isi muatan kasusastrannya apa?" Keheranan saya adalah pada tindakan tidak manusiawi yang tengah digambarkan, dan hampir juga saya teriak "itu bukan jahiliyah, itu masyarakat yang kini sedang menamai dirinya Indonesia!" Tapi hampir, untunglah saya sedang sadar sesadar-sadarnya bahwa Indonesia akan segera saya temukan, dan pada dasarnya tidak boleh ada perdebatan ataupun protes dalam mimbar Jum'at.
Kondisi tersebut dapat terhenti dengan kehadiran Rasulullah Shalallahu'alaihi Wassalam, Nabi besar yang hadir dijaman akhir yang berhasil melancarkan revolusi, tidak dengan senjata atau sekedar protes, dengan konsepsi sederhana yang menggugah kesadaran lewat keteladanan, menyampaikan kabar kemenangan bagi orang-orang beriman. Rahmatan lil'alamin.
Sebelumnya saya sempatkan baca darmagandhul, serat yang terbit beratus-ratus tahun yang lalu di tanah Jawa, bercerita tentang runtuhnya Majapahit akibat ajaran Islam yang dikatakannya "menggurita", kalau yang saya ketahui dari pelajaran sejarah, runtuhnya dinasti besar ini karena perang saudara.
Dari yang saya baca tadi, mengenai perjalanan Sunan Bonang di wilayah Kediri, dalam perjalanannya Sunan Bonang sempat berdebat dengan raja jin setempat karena Sunan Bonang telah memberi kutukan terhadap masyarakat sebuah desa di (mungkin) seputaran Nganjuk. Aliran sungai dia alihkan hingga menerpa desa, para jejaka dan perawannya dia kutuk akan menikah di usia tua. Kutukan tersebut terjadi akibat ulah seorang gadis desa yang salah sangka, ketika seorang murid dari Sunan yang diutus mencari air minum dan wudlu disangka hendak berbuat jahat, tidak mendapat air malah hinaan dan cacian dari sang gadis yang kemudian ia laporkan kepada Sunan. Marah dan mengutuk akhirnya.
Dari cerita perdebatan antara Sunan dan raja jin ini saya dapati suatu pemikiran, meskipun sangat jauh dari isi sampaian serat tersebut, yaitu ketika menyampaikan kabar gembira, syiar agama yang "rahmatan lil'alamin" ini adalah lebih baik dengan cara yang rahmatan lil'alamin juga. Tidak perlu merusak apalagi hingga menimbulkan permusuhan. Baik-buruknya kita kembalikan kepada Yang Maha Esa.
Membangun bangsa berakhlak mulia tidaklah dengan kekerasan, apalagi perang, penaklukkan hanya akan menyelipkan dendam. Dalam hal ini saya masih kabur, apakah Islam masuk ke nusantara dengan cara damai atau lewat penaklukkan tadi? Sejarahnya saya baca hanya sepotong-sepotong. Dan kenyataan berkisah lain, wajah garang pembela ajaran Rasulullah yang-sama sekali-jauh dari jargon rahmatan lil'alamin.
Sekali lagi, kedisiplinan tidak akan muncul dari ketakutan, masalah akhlak, masalah moral adalah pembenahan lewat keteladanan, tentunya dengan membuka ruang dialog.
Kamis, 24 Januari 2013
disorientasi dan kualitas bangsa
Dapat istilah menarik pagi ini, disorientasi lingkungan, sebenarnya saya baca kemarin waktu membagi tulisan ke beranda face book, pada suatu artikel yang membahas tentang fenomena kesurupan, dibahas lewat jalur ilmiah bukan metafisika, disitulah saya baca istilah "disorientasi lingkungan" sebagai salah satu point temuan. Juga baru kemarin saya ketahui istilah "tourette" yang merupakan judul lagu dari Nirvana.
Kalau dipikir, akhir-akhir ini sering terlihat hal-hal dan kejadian yang menggambarkan perilaku disorientasi lingkungan, seperti kehadiran para pembalap di jalanan, jalanan, bukan sirkuit. Atau seperti halnya hilangnya jati diri sebagaimana umumnya terjadi, terkait pula dengan penempatan diri pada waktu dan tempat secara tidak lazim. Ataukah mungkin sama dan dapat disejajarkan dengan keadaan "anti sosial"? Entah, yang pasti negeriku semakin tambah lucu.
Bisa saja dengan mudah ditemui bagaimana suatu lebaga beralih fungsi dengan tidak semestinya sebab sudah pasti orang-orang didalamnya juga sedang mengalami disorientasi lingkungan, seperi lembaga pendidikan yang lebih memberi kesan seperti lembaga politik atau bahkan lebih mirip usaha dagang, atau seperti parpol yang malah jadi lebih identik dengan penyalur tenaga kerja dan sebagainya yang sangat mudah untuk dijumpai. Sebagaimana juga suporter sepak bola yang memang lebih mirip prajurit kerajaan.
Kita bicarakan Sekolahan saja, biar lebih mudah menggambarkannya, sekolah adalah lembaga pendidikan, tempatnya orang belajar. Orang belajar adalah orang yang berubah, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu, belajar dan berubah. Dan proses belajar tanpa diikuti oleh perubahan~khususnya tingkah laku, adalah kesia-siaan.
Dengan begitu perlu adanya usaha yang sungguh-sungguh dalam proses belajar, mendisiplinkan diri adalah jadi penting sebelum didisiplinkan. Disiplin, terkait menempatkan segala sesuatunya dengan tepat dan benar, termasuk menempatkan diri pada tempat dan waktu secara tepat dan benar. Tanpa semua itu, saya tidak yakin perubahan bisa terjadi.
Tapi akan jadi tambah kacau ketika sekolah sebagai wadah perubahan tersebut malah ikut kehilangan jati dirinya, jangankan bicara perubahan, untuk bertahan sebagai manusiapun sepertinya adalah ketidak mungkinan. Pohon yang menghasilkan buah yang berkualitas hanya akan tumbuh dari tanah yang berkualitas pula, dan tentunya dengan cara merawat yang "berkualitas". Belajar tanpa ada perubahan sikap itu ibarat pohon tiada berbuah, alias percuma.
Pemimpin dan pejuang yang berkualitas hanya akan tumbuh dari lingkungan masyarakat (sebagai tanahnya) yang berkualitas. Kecenderungan perilaku disorientasi lingkungan memang bersifat individu, hanya saja ketika lingkungan tidak segera membenahi dan malah turut mendukung perilaku tersebut maka dapat dianalogikan seperti sebidang tanah yang memang tidak layak untuk ditanami.
Cukup mengherankan memang jika tumbuh padi diatas pasir, tidaklah mungkin tumbuh pohon apel didasar laut.
Manipulasi lingkungan pun sepertinya tidak akan memberi apapun terhadap perubahan-perbaikan, yang ada malah mengarah pada penyesatan yang tidak terperi, salah satu dampaknya adalah keterasingan. Manusia-manusia yang berkualitas dan bermanfaat bagi manusia yang lain hanya akan muncul dari lingkungan yang berkualitas pula. Tapi bagaimana mengolahnya? Dan seperti apakah lingkungan yang berkualitas itu jika individu-individunya saja malah terjebak pada keterasingan dan jadi tambah parah mengalami disorientasi lingkungan?. Mari bertanya pada rumpun yang bergoyang.
Kalau dipikir, akhir-akhir ini sering terlihat hal-hal dan kejadian yang menggambarkan perilaku disorientasi lingkungan, seperti kehadiran para pembalap di jalanan, jalanan, bukan sirkuit. Atau seperti halnya hilangnya jati diri sebagaimana umumnya terjadi, terkait pula dengan penempatan diri pada waktu dan tempat secara tidak lazim. Ataukah mungkin sama dan dapat disejajarkan dengan keadaan "anti sosial"? Entah, yang pasti negeriku semakin tambah lucu.
Bisa saja dengan mudah ditemui bagaimana suatu lebaga beralih fungsi dengan tidak semestinya sebab sudah pasti orang-orang didalamnya juga sedang mengalami disorientasi lingkungan, seperi lembaga pendidikan yang lebih memberi kesan seperti lembaga politik atau bahkan lebih mirip usaha dagang, atau seperti parpol yang malah jadi lebih identik dengan penyalur tenaga kerja dan sebagainya yang sangat mudah untuk dijumpai. Sebagaimana juga suporter sepak bola yang memang lebih mirip prajurit kerajaan.
Kita bicarakan Sekolahan saja, biar lebih mudah menggambarkannya, sekolah adalah lembaga pendidikan, tempatnya orang belajar. Orang belajar adalah orang yang berubah, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu, belajar dan berubah. Dan proses belajar tanpa diikuti oleh perubahan~khususnya tingkah laku, adalah kesia-siaan.
Dengan begitu perlu adanya usaha yang sungguh-sungguh dalam proses belajar, mendisiplinkan diri adalah jadi penting sebelum didisiplinkan. Disiplin, terkait menempatkan segala sesuatunya dengan tepat dan benar, termasuk menempatkan diri pada tempat dan waktu secara tepat dan benar. Tanpa semua itu, saya tidak yakin perubahan bisa terjadi.
Tapi akan jadi tambah kacau ketika sekolah sebagai wadah perubahan tersebut malah ikut kehilangan jati dirinya, jangankan bicara perubahan, untuk bertahan sebagai manusiapun sepertinya adalah ketidak mungkinan. Pohon yang menghasilkan buah yang berkualitas hanya akan tumbuh dari tanah yang berkualitas pula, dan tentunya dengan cara merawat yang "berkualitas". Belajar tanpa ada perubahan sikap itu ibarat pohon tiada berbuah, alias percuma.
Pemimpin dan pejuang yang berkualitas hanya akan tumbuh dari lingkungan masyarakat (sebagai tanahnya) yang berkualitas. Kecenderungan perilaku disorientasi lingkungan memang bersifat individu, hanya saja ketika lingkungan tidak segera membenahi dan malah turut mendukung perilaku tersebut maka dapat dianalogikan seperti sebidang tanah yang memang tidak layak untuk ditanami.
Cukup mengherankan memang jika tumbuh padi diatas pasir, tidaklah mungkin tumbuh pohon apel didasar laut.
Manipulasi lingkungan pun sepertinya tidak akan memberi apapun terhadap perubahan-perbaikan, yang ada malah mengarah pada penyesatan yang tidak terperi, salah satu dampaknya adalah keterasingan. Manusia-manusia yang berkualitas dan bermanfaat bagi manusia yang lain hanya akan muncul dari lingkungan yang berkualitas pula. Tapi bagaimana mengolahnya? Dan seperti apakah lingkungan yang berkualitas itu jika individu-individunya saja malah terjebak pada keterasingan dan jadi tambah parah mengalami disorientasi lingkungan?. Mari bertanya pada rumpun yang bergoyang.
Rabu, 23 Januari 2013
Kedisiplinan tidak muncul dari ketakutan
Rabu sore yang seperti biasa, langit masih juga murung oleh kehadiran mendung, kondisi seperti ini diramalkan akan terjadi hingga sebulan kedepan. Dingin dan misterius. Kalau masih kecil dulu malah yang ditunggu yang seperti ini buat main bola, biar seperti yang ada di TV dan memang pada dasarnya main bola sambil hujan-hujan adalah sangat mengasyikkan. Tapi itu dulu, hingga tersiar kabar tentang kesebelasan yang tersambar petir saat bertanding. Kegembiraan jadi redup-hilang.
Itu ketika masih SMP, saya sekolahnya di SMPN 1 Singosari tapi rumah saya ada di Kelurahan Purwodadi Malang, jauh, kalau pas musim kemarau biasanya naik BMX, kalau musim hujan cukuplah dengan angkot. Betapa hebat saya waktu itu.
Mengingat jaman SMP sudah tentu ingat kalau pernah nakal, suka bikin komplotan sama adik kelas atau mengganggu temen cewek, dan untungnya saya sekolahnya terhitung berada diluar wilayah perkotaan, dulu Singosari terkenal dengan wilayah santri, temen-temen saya kebanyakan juga santri waktu itu disamping anak-anak tentara, yang pasti saya terhindar dari pergaulan menyimpang yang lagi trend waktu itu.
Tapi, sejujurnya itu hanya berlangsung dua tahun, pas kelas tiga dan kakak saya sudah tidak lagi jadi teman seperjalanan ke sekolah, toh pada akhirnya saya juga menyimpang. Patut jadi catatan, hal ini tidak melibatkan temen-temen sekolah saya, sebab di kelas tiga hubungan saya dengan mereka merenggang, pun saya harus berterima kasih kepada mereka yang sadar atau tidak mereka juga telah menuntun saya kembali dan sepertinya juga (kalau diingat-ingat) merekalah yang bersusah payah membantu-membela saya. Aku rindu kalian kawan.
Jadi sedih kalau sudah seperti ini, tapi bukan untuk bercerita tentang kenangan, saya masih harus mencari Indonesia. Kenakalan anak SMP, sering disuruh lari keliling lapangan gara-gara terlambat datang, sudah pasti bareng kakak lari-lari berputar di lapangan.
Atau kena "strap" berjemur di lapangan. Nakal. Tapi tidak anti sosial, jaman orba, P4 dan butir-butir pancasila adalah mekanisme gerak dan pikiran setiap orang untuk dapat dikatakan "benar" meskipun pada akhirnya saya sadari semua itu hanyalah tindakan ideologis, penafsiran tunggal terhadap pancasila. Mungkin bagi orang Jawa hal tersebut tidak ada masalah, tapi bagi masyarakat lainnya. Sungguh, hingga hari ini dapat kita rasa dan saksikan dampak hebatnya, perpecahan.
Pernah ada kejadian, kakak kelas 3 B kena skors tiga hari lantaran (entah sengaja atau tidak) menaruh seragam olah raganya menutupi lambang garuda pancasila, juga belum saya ketahui nasib Bapak gurunya waktu itu. Dan yang kena skors bukannya bersedih malah terlihat riang bercerita pada kawan-kawannya yang lain. Kalau imajinasi saya saat ini adalah mereka gembira karena telah berhasil melancarkan aksi pemberontakannya. Betapa agungnya pancasila waktu itu, hingga UUD'45 pun jadi semacam kitab suci.
Ah, pasca reformasi, waktu saya ada di kelas tiga SMU kebanyakan orang malah melecehkan pancasila tanpa harus mendapat skors, kini saya bersama teman-teman saya mengkampanyekan pancasila, bukan dengan penafsiran tunggal, tapi dengan dialog antar generasi untuk membangun karakter bangsa yang berdaulat, bukan bangsa budak.
Memang muncul kelucuan-kelucuan jika mengingat masa-masa SMP, bahkan yang paling menegangkan pun juga ikut teringat, seperti ketika ada kunjungan Presiden Soeharto ke Kota Malang, entah waktu itu saya kelas dua atau kelas satu, yang pasti saya masih bersama kakak saya berangkat ke sekolah. Jalan kaki dari rumah menuju tempat biasa angkot menunggu penumpang di depan rumah bersalin di Jalan Panji Suroso.
Tidak seperti biasanya, setiap hari ketika berangkat sekolah pasti jalanan sudah ramai oleh lalu-lalang kendaraan dan kehadiran penjual koran, sekaligus anak jalanannya juga. Dan waktu itu sepi, banyak bapak tentara berjaga disepanjang jalan, hanya sekali dua kali kendaraan melintas, rupanya waktu itu jalur dialihkan, yang padat adalah di Jalan A. Yani, sedangkan jalur-jalur yang akan dilalui oleh presiden di sterilkan, termasuk di Jalan Panji Suroso ini.
Di tengah perjalanan, saya mendapati seorang petani~waktu itu area persawahan cukup luas di kawasan ini, pak petani ini membawa sabit, rupanya sedang berencana membersihkan sawah dari rumput liar, sabit/arit itulah perlengkapan khas petani yang juga turut menjadi simbol terlarang waktu itu. Palu-arit (jangankan mengibarkannya, menggambarnya di tempat paling tersembunyi adalah "Haram!"). Dan bapak petani itu sedang bawa arit dipinggir jalan yang jadi jalur lintas kendaraan presiden.
Seorang tentara datang menghampiri, dengan sedikit membentak telunjuknya mengarah ke bapak petani, sedang bapak petaninya celingukan tidak mengerti sampai pada akhirnya beliau meringis kearah bapak tentara yang mencoba merampas aritnya. Tidak begitu saya pahami kejadian itu selain penjelasan kakak saya yang sedang sok tahu waktu itu, seputaran lambang dan kengerian G 30S/PKI.
Tidak beruntung bagi saya dan kakak, waktu itu kami harus menambah rute perjalanan kearah timur, lebih dekat dengan pintu terminal angkot untuk mendapatkan mobil hijau, setelah dapat pun masih harus nunggu jalan dibuka, dari dalam angkot saya dapat menyaksikan rombongan presiden melaju dengan kecepatan penuh, salah seorang bapak penumpang bilang mobil-mobil serba hitam itu anti peluru.
Pikiran saya waktu itu masih pada nasib bapak petani, apakah arit yang hanya sebuah mampu memberi ancaman yang berarti terhadap mobil-mobil itu? Ataukah kewibawaan yang serta merta kehormatan seorang presiden dapat runtuh karenanya? Kewibawaan dan kehormatan yang juga dilindungi oleh serangkaian pengamanan ideologis yang sebenarnya malah memberi ancaman bagi banyak orang.
Semoga semua itu hanyalah masa lalu yang dapat kita pelajari kekurangan dan kelebihannya, kita menuju penyempurnaan hidup, tentu hidup yang lebih manusiawi, menyingkirkan peraturan-peraturan yang tidak mendasar bahkan yang tidak manusiawi untuk digantikan dengan peraturan yang lebih baik, tentu demi membangun kepribadian yang dicita-citakan, kedisiplinan sebagai seorang manusia yang tidak muncul dari rasa takut dan segan. Semoga (sebagaimana yang saya dapati lewat surat kabar) tidak ada lagi tindakan pendisiplinan yang tidak mendasar, ancaman hanya akan menumbuhkan ketakutan, bukan kedisiplinan.
Semoga tidak ada tindakan pendisiplinan yang sewenang-wenang demi generasi yang sehat pikiran dan mentalnya. Tindakan kekerasan tidak hanya sekedar tindakan fisik, dengan berkata-kata dan mengintimidasi adalah tindakan kekerasan, dan tidak manusiawi. Kalaupun pernah kita baca di surat kabar tentang tindakan-tindakan pendisiplinan oleh seorang guru yang pada akhirnya malah menjerumuskannya dalam kasus hukum, semoga saja yang demikian itu menjadi bahan belajar bagi kita semua. Pernah memang saya baca yang demikian, seperti protes wali murid yang mendapati laporan anaknya tentanng hukuman seorang guru dengan menumpuk-numpuk muridnya di tengah lapangan basket (apa gunanya?). Atau tindakan-tindakan lainnya yang tidak mendidik, semoga saja dapat menjadi bahan belajar untuk memperbaiki, kita sedang membentuk Indonesia, masa depan anak-cucu kita.
Itu ketika masih SMP, saya sekolahnya di SMPN 1 Singosari tapi rumah saya ada di Kelurahan Purwodadi Malang, jauh, kalau pas musim kemarau biasanya naik BMX, kalau musim hujan cukuplah dengan angkot. Betapa hebat saya waktu itu.
Mengingat jaman SMP sudah tentu ingat kalau pernah nakal, suka bikin komplotan sama adik kelas atau mengganggu temen cewek, dan untungnya saya sekolahnya terhitung berada diluar wilayah perkotaan, dulu Singosari terkenal dengan wilayah santri, temen-temen saya kebanyakan juga santri waktu itu disamping anak-anak tentara, yang pasti saya terhindar dari pergaulan menyimpang yang lagi trend waktu itu.
Tapi, sejujurnya itu hanya berlangsung dua tahun, pas kelas tiga dan kakak saya sudah tidak lagi jadi teman seperjalanan ke sekolah, toh pada akhirnya saya juga menyimpang. Patut jadi catatan, hal ini tidak melibatkan temen-temen sekolah saya, sebab di kelas tiga hubungan saya dengan mereka merenggang, pun saya harus berterima kasih kepada mereka yang sadar atau tidak mereka juga telah menuntun saya kembali dan sepertinya juga (kalau diingat-ingat) merekalah yang bersusah payah membantu-membela saya. Aku rindu kalian kawan.
Jadi sedih kalau sudah seperti ini, tapi bukan untuk bercerita tentang kenangan, saya masih harus mencari Indonesia. Kenakalan anak SMP, sering disuruh lari keliling lapangan gara-gara terlambat datang, sudah pasti bareng kakak lari-lari berputar di lapangan.
Atau kena "strap" berjemur di lapangan. Nakal. Tapi tidak anti sosial, jaman orba, P4 dan butir-butir pancasila adalah mekanisme gerak dan pikiran setiap orang untuk dapat dikatakan "benar" meskipun pada akhirnya saya sadari semua itu hanyalah tindakan ideologis, penafsiran tunggal terhadap pancasila. Mungkin bagi orang Jawa hal tersebut tidak ada masalah, tapi bagi masyarakat lainnya. Sungguh, hingga hari ini dapat kita rasa dan saksikan dampak hebatnya, perpecahan.
Pernah ada kejadian, kakak kelas 3 B kena skors tiga hari lantaran (entah sengaja atau tidak) menaruh seragam olah raganya menutupi lambang garuda pancasila, juga belum saya ketahui nasib Bapak gurunya waktu itu. Dan yang kena skors bukannya bersedih malah terlihat riang bercerita pada kawan-kawannya yang lain. Kalau imajinasi saya saat ini adalah mereka gembira karena telah berhasil melancarkan aksi pemberontakannya. Betapa agungnya pancasila waktu itu, hingga UUD'45 pun jadi semacam kitab suci.
Ah, pasca reformasi, waktu saya ada di kelas tiga SMU kebanyakan orang malah melecehkan pancasila tanpa harus mendapat skors, kini saya bersama teman-teman saya mengkampanyekan pancasila, bukan dengan penafsiran tunggal, tapi dengan dialog antar generasi untuk membangun karakter bangsa yang berdaulat, bukan bangsa budak.
Memang muncul kelucuan-kelucuan jika mengingat masa-masa SMP, bahkan yang paling menegangkan pun juga ikut teringat, seperti ketika ada kunjungan Presiden Soeharto ke Kota Malang, entah waktu itu saya kelas dua atau kelas satu, yang pasti saya masih bersama kakak saya berangkat ke sekolah. Jalan kaki dari rumah menuju tempat biasa angkot menunggu penumpang di depan rumah bersalin di Jalan Panji Suroso.
Tidak seperti biasanya, setiap hari ketika berangkat sekolah pasti jalanan sudah ramai oleh lalu-lalang kendaraan dan kehadiran penjual koran, sekaligus anak jalanannya juga. Dan waktu itu sepi, banyak bapak tentara berjaga disepanjang jalan, hanya sekali dua kali kendaraan melintas, rupanya waktu itu jalur dialihkan, yang padat adalah di Jalan A. Yani, sedangkan jalur-jalur yang akan dilalui oleh presiden di sterilkan, termasuk di Jalan Panji Suroso ini.
Di tengah perjalanan, saya mendapati seorang petani~waktu itu area persawahan cukup luas di kawasan ini, pak petani ini membawa sabit, rupanya sedang berencana membersihkan sawah dari rumput liar, sabit/arit itulah perlengkapan khas petani yang juga turut menjadi simbol terlarang waktu itu. Palu-arit (jangankan mengibarkannya, menggambarnya di tempat paling tersembunyi adalah "Haram!"). Dan bapak petani itu sedang bawa arit dipinggir jalan yang jadi jalur lintas kendaraan presiden.
Seorang tentara datang menghampiri, dengan sedikit membentak telunjuknya mengarah ke bapak petani, sedang bapak petaninya celingukan tidak mengerti sampai pada akhirnya beliau meringis kearah bapak tentara yang mencoba merampas aritnya. Tidak begitu saya pahami kejadian itu selain penjelasan kakak saya yang sedang sok tahu waktu itu, seputaran lambang dan kengerian G 30S/PKI.
Tidak beruntung bagi saya dan kakak, waktu itu kami harus menambah rute perjalanan kearah timur, lebih dekat dengan pintu terminal angkot untuk mendapatkan mobil hijau, setelah dapat pun masih harus nunggu jalan dibuka, dari dalam angkot saya dapat menyaksikan rombongan presiden melaju dengan kecepatan penuh, salah seorang bapak penumpang bilang mobil-mobil serba hitam itu anti peluru.
Pikiran saya waktu itu masih pada nasib bapak petani, apakah arit yang hanya sebuah mampu memberi ancaman yang berarti terhadap mobil-mobil itu? Ataukah kewibawaan yang serta merta kehormatan seorang presiden dapat runtuh karenanya? Kewibawaan dan kehormatan yang juga dilindungi oleh serangkaian pengamanan ideologis yang sebenarnya malah memberi ancaman bagi banyak orang.
Semoga semua itu hanyalah masa lalu yang dapat kita pelajari kekurangan dan kelebihannya, kita menuju penyempurnaan hidup, tentu hidup yang lebih manusiawi, menyingkirkan peraturan-peraturan yang tidak mendasar bahkan yang tidak manusiawi untuk digantikan dengan peraturan yang lebih baik, tentu demi membangun kepribadian yang dicita-citakan, kedisiplinan sebagai seorang manusia yang tidak muncul dari rasa takut dan segan. Semoga (sebagaimana yang saya dapati lewat surat kabar) tidak ada lagi tindakan pendisiplinan yang tidak mendasar, ancaman hanya akan menumbuhkan ketakutan, bukan kedisiplinan.
Semoga tidak ada tindakan pendisiplinan yang sewenang-wenang demi generasi yang sehat pikiran dan mentalnya. Tindakan kekerasan tidak hanya sekedar tindakan fisik, dengan berkata-kata dan mengintimidasi adalah tindakan kekerasan, dan tidak manusiawi. Kalaupun pernah kita baca di surat kabar tentang tindakan-tindakan pendisiplinan oleh seorang guru yang pada akhirnya malah menjerumuskannya dalam kasus hukum, semoga saja yang demikian itu menjadi bahan belajar bagi kita semua. Pernah memang saya baca yang demikian, seperti protes wali murid yang mendapati laporan anaknya tentanng hukuman seorang guru dengan menumpuk-numpuk muridnya di tengah lapangan basket (apa gunanya?). Atau tindakan-tindakan lainnya yang tidak mendidik, semoga saja dapat menjadi bahan belajar untuk memperbaiki, kita sedang membentuk Indonesia, masa depan anak-cucu kita.
Selasa, 22 Januari 2013
Dari "Krisna gugah" sampai pada taktik "politik Poros"
Sore gerimis, sepinya mengiris-iris...
Saya pernah ndengerin rekaman wayang orang yang judulnya "krena gugah" dua seri, sebenarnya saya tidak begitu mengerti tentang wayang, jangankan ceritanya, tokoh-tokohnya hanya itu-itu saja yang saya hafal. Untuk mengerti jalan cerita rekaman wayang inipun saya harus memutarnya berulang-ulang. Waktu itu bukan hanya orang tua saya saja yang heran, mungkin setan dalam otak saya juga keheranan mendapati saya begitu tekun mendengar cerita wayang, sebab waktu itu saya lebih suka mendengar koleksi kaset metal saya. Kalau pas ada kegiatan panggung musik pun pilihannya pasti seputaran metal, punk, grunge atau sejenisnya, bukan wayang.
Tekun sekali waktu itu, hingga kini kalaupun ada yang minta saya ceritakan, tapi hanya kisah itu saja, Krisna gugah.
Berawal dari persiapan perang baratayudha, antara Kurawa dan Pandawa, kedua belah pihak menyusun strategi dan menggalang kekuatan termasuk berebut dukungan dari Krisna yang sudah tersohor bijaknya. Titisan dewa, sakti mandraguna.
Untuk mendapatkan dukungan dari Krisna ini, baik Kurawa maupun Pandawa harus mampu membangunkan Krisna dari tidurnya di dalam sebuah sumur, sumur jalathunda namanya dan dijaga oleh seorang anak Krisna. Dalam perjalanan menuju sumur, Pandawa mendapati rintangan bertemu raksasa dan Kurawa yang bersama Prabu Baladewa harus direpotkan dengan anak Krisna, dan yang mengalahkan anak Krisna ini adalah Baladewa, tapi yang masuk lebih dahulu ke dalam sumur adalah Pandawa.
Begitu masuk ke dalam sumur, Arjuna atas saran Punakawan menjemput roh Krisna ke kayangan. Di kayangan, Krisna sedang berbincang-bincang dengan para dewa tentang perang baratayudha yang memang harus terjadi agar kebaikan dapat mengalahkan kejahatan. Para dewa banyak memberi saran kepada Krisna agar perang baratayudha nantinya dapat menjadi suatu tontonan yang menarik bagi para dewa di kayangan.
Dari pertemuan ini juga terdapat rencana-rencana tentang siapa harus melawan siapa dalam perang tersebut, jadi skenarionya sudah ada.
Belum selesai pembicaraan tiba-tiba saja Arjuna muncul meminta Krisna untuk kembali ke raganya di sumur jalatunda. Berhasil membawa Krisna ke raganya, datanglah Kurawa dan Prabu Baladewa, dua pihak bertemu dan Krisna yang baru bangun tidur berada diantara mereka. Terjadi perebutan, masing-masing bikin alibi atau semacamnya untuk merebut dukungan Krisna.
Krisna yang sudah dari awal mendapat pesan dari para dewa harus memutar otak, belum juga selesai malah terjadi perkelahian antara Bima dengan Baladewa. Kekuatan dahsyat beradu, Baladewa mencabut keris pusakanya dan diterjangkan kearah Bima, meleset. Bima sigap melompat-menghindar, keris menghujam ke tanah. Blar!.
Terdengar suara kesakitan setelah ledakan akibat keris yang ledakkannya ini tadi (mungkin) mirip suara bom cluster milik Israel. Dewa Bumi muncul dengan lagak kesakitan bertanya-tanya siapa yang telah berani mengusik kedamaiannya. Buru-buru Baladewa meminta maaf, dan kemudian Dewa Bumi malah mengucap sumpah bahwa kematian Baladewa nantinya adalah dengan dicepit tujuh bumi.
Seketika pula Dewa Bumi pergi meninggalkan dua kelompok yang tengah berseteru ini, dan Baladewa jadi resah permohonan maafnya tidak diterima malah ia mendapat sumpah. Keresahan inipun dimanfaatkan oleh Krisna, ia sarankan kepada Baladewa untuk menebus kesalahannya dengan melakukan pertapaan di sebuah gunung. Sementara lupa dengan misi awal untuk merekrut Krisna.
Dalam perjalanan untuk bertapa, Baladewa mendapat godaan, ia bertemu seorang gadis desa yang rupawan, jatuh hatilah Baladewa dan berkeinginan untuk meminang gadis tersebut. Belum lagi terkabulkan, Krisna muncul dan gadis desa tersebut ternyata adalah Arjuna yang sedang menyamar. Gagal lah pertapaannya.
Oleh Krisna kemudian Baladewa disarankan untuk saling berbagi kepada rakyat jelata, bersama istri dan beberapa pengawal berangkatlah Baladewa mencari rakyat untuk disedekahi. Dalam perjalanannya ia bertemu seorang kakek yang sama-sama sedang ingin beristirahat pada sebuah pondok.
Baladewa diminta oleh Krisna untuk merendahkan hati dan melayani siapapun yang dijumpainya, kakek tua ini sangat ludu dan punya adat yang sedikit kurang ajar, beberapa kali Baladewa terpancing emosinya hingga pada saat tak tertahankan lagi. Hampir-hampir sang kakek menerima uper cut dari Baladewa, sekali lagi Krisna muncul, dan kake tadi ternyata adalah Petruk (salah satu dari Punakawan). Gagal lagi usaha Baladewa untuk menyucikan dirinya atas perbuatannya.
Terakhir kalinya, Baladewa disarankan untuk melakukan pengasingan, bertapa seorang diri di Grojokan sewu. Berangkatlah Baladewa tanpa diikuti oleh pengawal maupun istrinya. Dan hilang pula satu kekuatan dahsyat yang tadinya berpihak pada Kurawa yang ternyata pada akhirnya juga diketahui merupakan kehendak dari para dewa agar pada saat perang Baratayuda pertempuran dapat berjalan seimbang.
Sebenarnya bukan hanya pihak Kurawa yang mendapat perlakuan semacam itu oleh Krisna, tetapi juga pihak Pandawa dengan terbunuhnya Antareja-anak Bima, yang karena kemampuannya dikhawatirkan dapat menumpas pasukan Kurawa sebelum terjadi perang. Antareja diketahui memiliki kekuatan pada bibir dan lidahnya, siapapun yang terkena lidahnya akan musnah, juga dengan bekas dari lidah Antareja. Sakti.
Lebih lanjut, sebagaimana yang diketahui umum, pada akhirnya pihak Pandawalah yang menjadi pemenang, sedang pihak Kurawa musnah.
Kalau saya ingat lagi cerita ini hampir mirip dengan sejarah "poros-porosan" yang terjadi pasca reformasi 1998. Setelah Presiden Soeharto tumbang, pemerintahan dipegang oleh BJ Habibie sebagai pemerintahan transisi, presiden terpilih berikutnya adalah Gus Dur dengan taktik "poros" rancangan Amien Rais untuk menggagalkan Megawati sebagai presiden, tentunya untuk mengungguli kekuatan suara PDIP yang keluar sebagai pemenang pemilu. Pada waktu itu, presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat, tapi lewat sidang MPR. Dan taktik "poros" Amien Rais berhasil membendung kekuatan PDIP dengan menyatukan parpol-parpol Islam.
Lengsernya Gus Dur pun juga merupakan taktik "poros" Amien Rais yang menggalang kekuatan untuk mengungguli dominasi presiden-ini sebenarnya warisan orde lama yang hampir dilupakan oleh kalangan politik masa itu, dan Gus Dur memanfaatkannya: dekrit yang berisi (1) pembubaran MPR/DPR, (2) mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu satu tahun, dan (3) membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap Sidang Istimewa MPR. Namun dekrit tersebut tidak memperoleh dukungan dan pada 23 Juli, MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Sukarnoputri.
Memang ada berbagai intrik dibalik semua itu yang tidak mungkin bagi saya untuk menjelaskan, hanya sekedar tangkapan dan ingatan saya saja. Dan pada waktu itu, peran Amien Rais ini malah seperti peran Krisna dalam cerita Krisna gugah. Loncat sana, loncat sini, hadang sana-hadang sini, entah apa maunya, hanya dia sendiri yang bisa menjelaskan.
Bukan maksud saya membuka tabir cerita lama, mengungkit-ungkit masa lalu, tapi (sekali lagi) hanya sekedar mencari Indonesia yang bagi saya tidak ada salahnya dengan mereka-reka ulang kejadian demi kejadian yang berhasil saya tangkap-saya ingat.
Wayang adalah satu tradisi bangsa, meskipun ia datang dari tanah seberang-negeri Hindustan, tapi wayangnya adalah dari Jawa, dan telah mengalami beberapa kali revolusi, sering pula kisah-kisah wayang ini menginspirasi tokoh-tokoh politik negeri ini ataukah memang perwatakkan bangsa ini ada dalam tradisi wayang tersebut? Entah.
Saya pernah ndengerin rekaman wayang orang yang judulnya "krena gugah" dua seri, sebenarnya saya tidak begitu mengerti tentang wayang, jangankan ceritanya, tokoh-tokohnya hanya itu-itu saja yang saya hafal. Untuk mengerti jalan cerita rekaman wayang inipun saya harus memutarnya berulang-ulang. Waktu itu bukan hanya orang tua saya saja yang heran, mungkin setan dalam otak saya juga keheranan mendapati saya begitu tekun mendengar cerita wayang, sebab waktu itu saya lebih suka mendengar koleksi kaset metal saya. Kalau pas ada kegiatan panggung musik pun pilihannya pasti seputaran metal, punk, grunge atau sejenisnya, bukan wayang.
Tekun sekali waktu itu, hingga kini kalaupun ada yang minta saya ceritakan, tapi hanya kisah itu saja, Krisna gugah.
Berawal dari persiapan perang baratayudha, antara Kurawa dan Pandawa, kedua belah pihak menyusun strategi dan menggalang kekuatan termasuk berebut dukungan dari Krisna yang sudah tersohor bijaknya. Titisan dewa, sakti mandraguna.
Untuk mendapatkan dukungan dari Krisna ini, baik Kurawa maupun Pandawa harus mampu membangunkan Krisna dari tidurnya di dalam sebuah sumur, sumur jalathunda namanya dan dijaga oleh seorang anak Krisna. Dalam perjalanan menuju sumur, Pandawa mendapati rintangan bertemu raksasa dan Kurawa yang bersama Prabu Baladewa harus direpotkan dengan anak Krisna, dan yang mengalahkan anak Krisna ini adalah Baladewa, tapi yang masuk lebih dahulu ke dalam sumur adalah Pandawa.
Begitu masuk ke dalam sumur, Arjuna atas saran Punakawan menjemput roh Krisna ke kayangan. Di kayangan, Krisna sedang berbincang-bincang dengan para dewa tentang perang baratayudha yang memang harus terjadi agar kebaikan dapat mengalahkan kejahatan. Para dewa banyak memberi saran kepada Krisna agar perang baratayudha nantinya dapat menjadi suatu tontonan yang menarik bagi para dewa di kayangan.
Dari pertemuan ini juga terdapat rencana-rencana tentang siapa harus melawan siapa dalam perang tersebut, jadi skenarionya sudah ada.
Belum selesai pembicaraan tiba-tiba saja Arjuna muncul meminta Krisna untuk kembali ke raganya di sumur jalatunda. Berhasil membawa Krisna ke raganya, datanglah Kurawa dan Prabu Baladewa, dua pihak bertemu dan Krisna yang baru bangun tidur berada diantara mereka. Terjadi perebutan, masing-masing bikin alibi atau semacamnya untuk merebut dukungan Krisna.
Krisna yang sudah dari awal mendapat pesan dari para dewa harus memutar otak, belum juga selesai malah terjadi perkelahian antara Bima dengan Baladewa. Kekuatan dahsyat beradu, Baladewa mencabut keris pusakanya dan diterjangkan kearah Bima, meleset. Bima sigap melompat-menghindar, keris menghujam ke tanah. Blar!.
Terdengar suara kesakitan setelah ledakan akibat keris yang ledakkannya ini tadi (mungkin) mirip suara bom cluster milik Israel. Dewa Bumi muncul dengan lagak kesakitan bertanya-tanya siapa yang telah berani mengusik kedamaiannya. Buru-buru Baladewa meminta maaf, dan kemudian Dewa Bumi malah mengucap sumpah bahwa kematian Baladewa nantinya adalah dengan dicepit tujuh bumi.
Seketika pula Dewa Bumi pergi meninggalkan dua kelompok yang tengah berseteru ini, dan Baladewa jadi resah permohonan maafnya tidak diterima malah ia mendapat sumpah. Keresahan inipun dimanfaatkan oleh Krisna, ia sarankan kepada Baladewa untuk menebus kesalahannya dengan melakukan pertapaan di sebuah gunung. Sementara lupa dengan misi awal untuk merekrut Krisna.
Dalam perjalanan untuk bertapa, Baladewa mendapat godaan, ia bertemu seorang gadis desa yang rupawan, jatuh hatilah Baladewa dan berkeinginan untuk meminang gadis tersebut. Belum lagi terkabulkan, Krisna muncul dan gadis desa tersebut ternyata adalah Arjuna yang sedang menyamar. Gagal lah pertapaannya.
Oleh Krisna kemudian Baladewa disarankan untuk saling berbagi kepada rakyat jelata, bersama istri dan beberapa pengawal berangkatlah Baladewa mencari rakyat untuk disedekahi. Dalam perjalanannya ia bertemu seorang kakek yang sama-sama sedang ingin beristirahat pada sebuah pondok.
Baladewa diminta oleh Krisna untuk merendahkan hati dan melayani siapapun yang dijumpainya, kakek tua ini sangat ludu dan punya adat yang sedikit kurang ajar, beberapa kali Baladewa terpancing emosinya hingga pada saat tak tertahankan lagi. Hampir-hampir sang kakek menerima uper cut dari Baladewa, sekali lagi Krisna muncul, dan kake tadi ternyata adalah Petruk (salah satu dari Punakawan). Gagal lagi usaha Baladewa untuk menyucikan dirinya atas perbuatannya.
Terakhir kalinya, Baladewa disarankan untuk melakukan pengasingan, bertapa seorang diri di Grojokan sewu. Berangkatlah Baladewa tanpa diikuti oleh pengawal maupun istrinya. Dan hilang pula satu kekuatan dahsyat yang tadinya berpihak pada Kurawa yang ternyata pada akhirnya juga diketahui merupakan kehendak dari para dewa agar pada saat perang Baratayuda pertempuran dapat berjalan seimbang.
Sebenarnya bukan hanya pihak Kurawa yang mendapat perlakuan semacam itu oleh Krisna, tetapi juga pihak Pandawa dengan terbunuhnya Antareja-anak Bima, yang karena kemampuannya dikhawatirkan dapat menumpas pasukan Kurawa sebelum terjadi perang. Antareja diketahui memiliki kekuatan pada bibir dan lidahnya, siapapun yang terkena lidahnya akan musnah, juga dengan bekas dari lidah Antareja. Sakti.
Lebih lanjut, sebagaimana yang diketahui umum, pada akhirnya pihak Pandawalah yang menjadi pemenang, sedang pihak Kurawa musnah.
Kalau saya ingat lagi cerita ini hampir mirip dengan sejarah "poros-porosan" yang terjadi pasca reformasi 1998. Setelah Presiden Soeharto tumbang, pemerintahan dipegang oleh BJ Habibie sebagai pemerintahan transisi, presiden terpilih berikutnya adalah Gus Dur dengan taktik "poros" rancangan Amien Rais untuk menggagalkan Megawati sebagai presiden, tentunya untuk mengungguli kekuatan suara PDIP yang keluar sebagai pemenang pemilu. Pada waktu itu, presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat, tapi lewat sidang MPR. Dan taktik "poros" Amien Rais berhasil membendung kekuatan PDIP dengan menyatukan parpol-parpol Islam.
Lengsernya Gus Dur pun juga merupakan taktik "poros" Amien Rais yang menggalang kekuatan untuk mengungguli dominasi presiden-ini sebenarnya warisan orde lama yang hampir dilupakan oleh kalangan politik masa itu, dan Gus Dur memanfaatkannya: dekrit yang berisi (1) pembubaran MPR/DPR, (2) mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu satu tahun, dan (3) membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap Sidang Istimewa MPR. Namun dekrit tersebut tidak memperoleh dukungan dan pada 23 Juli, MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Sukarnoputri.
Memang ada berbagai intrik dibalik semua itu yang tidak mungkin bagi saya untuk menjelaskan, hanya sekedar tangkapan dan ingatan saya saja. Dan pada waktu itu, peran Amien Rais ini malah seperti peran Krisna dalam cerita Krisna gugah. Loncat sana, loncat sini, hadang sana-hadang sini, entah apa maunya, hanya dia sendiri yang bisa menjelaskan.
Bukan maksud saya membuka tabir cerita lama, mengungkit-ungkit masa lalu, tapi (sekali lagi) hanya sekedar mencari Indonesia yang bagi saya tidak ada salahnya dengan mereka-reka ulang kejadian demi kejadian yang berhasil saya tangkap-saya ingat.
Wayang adalah satu tradisi bangsa, meskipun ia datang dari tanah seberang-negeri Hindustan, tapi wayangnya adalah dari Jawa, dan telah mengalami beberapa kali revolusi, sering pula kisah-kisah wayang ini menginspirasi tokoh-tokoh politik negeri ini ataukah memang perwatakkan bangsa ini ada dalam tradisi wayang tersebut? Entah.
Senin, 21 Januari 2013
Pertarungan ideologis, refleksi dari situasi suatu komunitas
Senin sore, baru bisa ngetik disini, masih juga ngambang tanpa ada kejernihan, Indonesia semakin buram. Entah seperti apa dan bagaimana? Sama sekali hilang, membayang pun tidak. Mendung, sore yang murung.
Menyempatkan diri untuk berada dalam suatu komunitas-yang mungkin sama dengan komunitas yang lain, perkumpulan yang mungkin sama seperti perkumpulan yang lain di negeri ini, dimana perkumpulan-perkumpulan ini dibangun hanya untuk sarana penguasaan manusia atas manusia.
Orde baru telah membuktikan-sekali lagi, keunggulannya meski telah lama disingkirkan oleh reformasi, tapi itu hanya cerita, kenyataannya kekuatannya dan pengaruhnya masih ada terwarisi, mungkin hingga sepuluh generasi kedepan. Atau mungkin akan tambah menghebat.
Watak warisan regim developmentalisme, kalau boleh dikatakan seperti itu sebab menurut saya demikianlah gambaran yang pas realitas objektif haluan ekonomi negara-negara dunia ketiga, developmentalisme, suatu pemulihan ekonomi dengan motif utama membendung pengaruh komunisme dan bentuk-bentuk lain sosialisme. Sayang sekali "polisi demokrasi" waktu itu mendapati orde baru telah bergeser pada fasisme (terselubung) yaitu dengan paham "jawaisme" yang menggantikan slogan bhineka tunggal ika dengan pemusatan yang serta merta keharusan serba Jawa. Tepo sliro dan segala filosofi yang pada akhirnya terbukti hanyalah kedok bagi kemapanan dan kecurangan.
Mungkin pula masih teringat dengan baik, semua serba pusat... keputusan dari pusat, sekali lagi "pusat", birokrasi yang tidak sehat. Aman terpelihara disetiap gedung dan jalanan negeri ini.
Parahnya lagi, orde baru lebih mengedepankan istilah "demokrasi pancasila" yang hanya istilah tanpa pelaksanaan, dan pada akhirnya-kini-pancasila menjadi salah satu objek hujatan. Banyak yang berpendapat bahwa pancasila telah gagal sebab penguasa sendiri juga mendukung pendapat tersebut dengan kebijakan dan tingkah lakunya.
Dalam komunitas yang saya sempatkan untuk hadir hari ini pun tampaknya juga seperti itu, ada kelompok "tua" dan sudah pasti ada golongan "muda" dengan perwatakan dan kepentingan masing-masing yaitu menguasai satu sama lain.
Kepemimpinan menjadi terlihat tidak tegas dalam kondisi seperti ini, layaknya yang terjadi pada umumnya dan mungkin ini adalah salah satu penyakit menular yang menjangkiti bangsa ini. Seorang pemimpin akan terombang-ambing dan hanya cari selamat.
Kelompok tua lebih pada mempertahankan status quo dan bermain-main dibalik keluhuran, kemapanan dan gaya birokrasi serba "pusat", propaganda ideologis untuk sekedar mendominasi menjadi salah satu gambaran. Sedang golongan muda yang sedang mabuk kepayang terbagi-bagi dalam fraksi-fraksi sesuai kepentingan masing-masing, ada yang jadi kader kelompok tua ada yang berimajinasi tentang suatu gerakan revolusioner dan ada yang secara sadar mengharapkan suatu perubahan/perbaikan.
Dalam kondisi seperti ini sebenarnya peran seorang pemimpin yang tegas "tanpa kompromi" menjadi hal utama, dimana seorang pemimpin tidak saja hanya sebagai figur suatu kelompok atau komunitas, ia harus jadi teladan dan pemersatu anggotanya.
Seringnya pemimpin malah terjebak diantara perseteruan yang mengharuskan ia untuk berpihak, jadinya timpang, ada yang dilindungi, ada yang diserang tanpa ampun dan sudah pasti nantinya harus ada korban. Nah dalam komunitas yang saya sempatkan untuk hadir ini juga menyimpan keunikan, ceritanya dimana ketika kelompok tua mencari kader untuk kemapanannya ada salah satu dari mereka yang-katakanlah: blunder, sedang yang didekati~dari yang muda malah terlihat nyaman-nyaman saja. Terjadi skandal, dan rupanya sang pemimpin berpihak, tentunya agar aman maka ia berpihak pada kelompok tua. Saya tulis kelompok tua sebab mereka juga mengatakan seperti itu daripada memilih untuk menyebut "senior".
Keberpihakkan sang pemimpin ini dapat diketahui ketika ia mencoba menutup-nutupi hal tersebut, pun selanjutnya adalah upaya untuk mengaburkan pendapat umum tentang hal tersebut, jadi tambah rumit sebab upaya-upaya tersebut ternyata malah menumbuhkan kasus-kasus baru. Golongan muda semakin terpecah belah, saling curiga dengan menafsirkan situasi sesuai dengan sudut pandang masing-masing, keadaan jadi tak ubahnya seperti politik nasional, bahkan jadi terdengar lebih rumit. Kemana sang pemimpin?!.
Tidak hanya pemimpin yang sedang berpihak, lebih parah, aturan turut berpihak, tentunya berpihak pada kelompok yang dominan, warisan orde baru jadi terpampang nyata dimana kelompok tua bersusah payah menyembunyikan kepentingannya dengan mengatasnamakan "kedisiplinan" tanpa ada upaya peneladanan, jangankan peneladanan, lha wong yang dipikirkan hanya kemapanan.
Ada juga dari kadernya kelompok tua yang mengedepankan kerukunan tapi dengan menempatkan lawan-lawannya sebagai kelompok yang patut untuk disingkirkan (karena sepertinya sudah kehabisan akal untuk melakukan pembungkaman), penyingkiran-pembungkaman kok ya atas nama kerukunan? Benar-benar ideologis. Sungguh saya sangat menyadari bahwa saya sempat berada dalam situasi serba dramatis, kondisi yang lebih mirip sandiwara-mungkin karena pengaruh sinetron tanah merdeka ini. Dan untungnya saya hanya sekedar mampir jadi pengamat, tapi begitu saya memperlihatkan diri tadi, serentak semua pihak-pihak yang ada langsung berebut, padahal saya sama sekali tidak memiliki pengaruh apapun di dalamnya, jangankan pengaruh, wewenang sebagai anggota saja tidak.
Saya dapati pengetahuan dari sekilas pengalaman ini, yaitu kepemimpinan adalah suatu keterampilan berorganisasi yang tidak hanya sekedar mengorganisasikan orang-orang tapi juga lebih pada pengorganisasian kepentingan anggota-anggotanya. Apalah arti suatu organisasi ketika peraturan jadi timpang? Sama, apalah pentingnya sebuah negara ketika hukum berpihak pada satu golongan? Sedang kita pernah bersepakat untuk membangun suatu negara bangsa.
Atau memang? Semua ini berjalan hanya karena iseng? Toh seperti pengalaman saya tadi, yang pada akhirnya dapat saya ketahui (meskipun tanpa bertanya, salah satu "kader"menjelaskannya) bahwa skandal awalnya hanyalah suatu perbuatan iseng yang memanfaatkan kebodohan. Astaganaga...
Sebelum tiba waktu magrib tadi saya sudah cepat-cepat meninggalkan lokasi, hampir-hampir pikiran saya kacau dan hampir-hampir saya terhambat untuk mencari Indonesia, Indonesia, bangsa yang masih saja dalam angan-angan.
Seharusnya kita sudah belajar dari pengalaman, dimana penafsiran tunggal terhadap pancasila hanya akan menjerumuskan kita pada suatu keadaan yang serba kaku dan pura-pura, penafsiran tunggal hanya akan berujung pada tindakan ideologis yang pada dasarnya menyertakan ketidak adilan. Semoga saja "keisengan" yang ada dapat dihentikan dan dijelaskan agar dapat termaafkan, dan kita mampu kembali bangkit untuk membangun karakter bangsa untuk menemukan Indonesia. Aamiin.
Menyempatkan diri untuk berada dalam suatu komunitas-yang mungkin sama dengan komunitas yang lain, perkumpulan yang mungkin sama seperti perkumpulan yang lain di negeri ini, dimana perkumpulan-perkumpulan ini dibangun hanya untuk sarana penguasaan manusia atas manusia.
Orde baru telah membuktikan-sekali lagi, keunggulannya meski telah lama disingkirkan oleh reformasi, tapi itu hanya cerita, kenyataannya kekuatannya dan pengaruhnya masih ada terwarisi, mungkin hingga sepuluh generasi kedepan. Atau mungkin akan tambah menghebat.
Watak warisan regim developmentalisme, kalau boleh dikatakan seperti itu sebab menurut saya demikianlah gambaran yang pas realitas objektif haluan ekonomi negara-negara dunia ketiga, developmentalisme, suatu pemulihan ekonomi dengan motif utama membendung pengaruh komunisme dan bentuk-bentuk lain sosialisme. Sayang sekali "polisi demokrasi" waktu itu mendapati orde baru telah bergeser pada fasisme (terselubung) yaitu dengan paham "jawaisme" yang menggantikan slogan bhineka tunggal ika dengan pemusatan yang serta merta keharusan serba Jawa. Tepo sliro dan segala filosofi yang pada akhirnya terbukti hanyalah kedok bagi kemapanan dan kecurangan.
Mungkin pula masih teringat dengan baik, semua serba pusat... keputusan dari pusat, sekali lagi "pusat", birokrasi yang tidak sehat. Aman terpelihara disetiap gedung dan jalanan negeri ini.
Parahnya lagi, orde baru lebih mengedepankan istilah "demokrasi pancasila" yang hanya istilah tanpa pelaksanaan, dan pada akhirnya-kini-pancasila menjadi salah satu objek hujatan. Banyak yang berpendapat bahwa pancasila telah gagal sebab penguasa sendiri juga mendukung pendapat tersebut dengan kebijakan dan tingkah lakunya.
Dalam komunitas yang saya sempatkan untuk hadir hari ini pun tampaknya juga seperti itu, ada kelompok "tua" dan sudah pasti ada golongan "muda" dengan perwatakan dan kepentingan masing-masing yaitu menguasai satu sama lain.
Kepemimpinan menjadi terlihat tidak tegas dalam kondisi seperti ini, layaknya yang terjadi pada umumnya dan mungkin ini adalah salah satu penyakit menular yang menjangkiti bangsa ini. Seorang pemimpin akan terombang-ambing dan hanya cari selamat.
Kelompok tua lebih pada mempertahankan status quo dan bermain-main dibalik keluhuran, kemapanan dan gaya birokrasi serba "pusat", propaganda ideologis untuk sekedar mendominasi menjadi salah satu gambaran. Sedang golongan muda yang sedang mabuk kepayang terbagi-bagi dalam fraksi-fraksi sesuai kepentingan masing-masing, ada yang jadi kader kelompok tua ada yang berimajinasi tentang suatu gerakan revolusioner dan ada yang secara sadar mengharapkan suatu perubahan/perbaikan.
Dalam kondisi seperti ini sebenarnya peran seorang pemimpin yang tegas "tanpa kompromi" menjadi hal utama, dimana seorang pemimpin tidak saja hanya sebagai figur suatu kelompok atau komunitas, ia harus jadi teladan dan pemersatu anggotanya.
Seringnya pemimpin malah terjebak diantara perseteruan yang mengharuskan ia untuk berpihak, jadinya timpang, ada yang dilindungi, ada yang diserang tanpa ampun dan sudah pasti nantinya harus ada korban. Nah dalam komunitas yang saya sempatkan untuk hadir ini juga menyimpan keunikan, ceritanya dimana ketika kelompok tua mencari kader untuk kemapanannya ada salah satu dari mereka yang-katakanlah: blunder, sedang yang didekati~dari yang muda malah terlihat nyaman-nyaman saja. Terjadi skandal, dan rupanya sang pemimpin berpihak, tentunya agar aman maka ia berpihak pada kelompok tua. Saya tulis kelompok tua sebab mereka juga mengatakan seperti itu daripada memilih untuk menyebut "senior".
Keberpihakkan sang pemimpin ini dapat diketahui ketika ia mencoba menutup-nutupi hal tersebut, pun selanjutnya adalah upaya untuk mengaburkan pendapat umum tentang hal tersebut, jadi tambah rumit sebab upaya-upaya tersebut ternyata malah menumbuhkan kasus-kasus baru. Golongan muda semakin terpecah belah, saling curiga dengan menafsirkan situasi sesuai dengan sudut pandang masing-masing, keadaan jadi tak ubahnya seperti politik nasional, bahkan jadi terdengar lebih rumit. Kemana sang pemimpin?!.
Tidak hanya pemimpin yang sedang berpihak, lebih parah, aturan turut berpihak, tentunya berpihak pada kelompok yang dominan, warisan orde baru jadi terpampang nyata dimana kelompok tua bersusah payah menyembunyikan kepentingannya dengan mengatasnamakan "kedisiplinan" tanpa ada upaya peneladanan, jangankan peneladanan, lha wong yang dipikirkan hanya kemapanan.
Ada juga dari kadernya kelompok tua yang mengedepankan kerukunan tapi dengan menempatkan lawan-lawannya sebagai kelompok yang patut untuk disingkirkan (karena sepertinya sudah kehabisan akal untuk melakukan pembungkaman), penyingkiran-pembungkaman kok ya atas nama kerukunan? Benar-benar ideologis. Sungguh saya sangat menyadari bahwa saya sempat berada dalam situasi serba dramatis, kondisi yang lebih mirip sandiwara-mungkin karena pengaruh sinetron tanah merdeka ini. Dan untungnya saya hanya sekedar mampir jadi pengamat, tapi begitu saya memperlihatkan diri tadi, serentak semua pihak-pihak yang ada langsung berebut, padahal saya sama sekali tidak memiliki pengaruh apapun di dalamnya, jangankan pengaruh, wewenang sebagai anggota saja tidak.
Saya dapati pengetahuan dari sekilas pengalaman ini, yaitu kepemimpinan adalah suatu keterampilan berorganisasi yang tidak hanya sekedar mengorganisasikan orang-orang tapi juga lebih pada pengorganisasian kepentingan anggota-anggotanya. Apalah arti suatu organisasi ketika peraturan jadi timpang? Sama, apalah pentingnya sebuah negara ketika hukum berpihak pada satu golongan? Sedang kita pernah bersepakat untuk membangun suatu negara bangsa.
Atau memang? Semua ini berjalan hanya karena iseng? Toh seperti pengalaman saya tadi, yang pada akhirnya dapat saya ketahui (meskipun tanpa bertanya, salah satu "kader"menjelaskannya) bahwa skandal awalnya hanyalah suatu perbuatan iseng yang memanfaatkan kebodohan. Astaganaga...
Sebelum tiba waktu magrib tadi saya sudah cepat-cepat meninggalkan lokasi, hampir-hampir pikiran saya kacau dan hampir-hampir saya terhambat untuk mencari Indonesia, Indonesia, bangsa yang masih saja dalam angan-angan.
Seharusnya kita sudah belajar dari pengalaman, dimana penafsiran tunggal terhadap pancasila hanya akan menjerumuskan kita pada suatu keadaan yang serba kaku dan pura-pura, penafsiran tunggal hanya akan berujung pada tindakan ideologis yang pada dasarnya menyertakan ketidak adilan. Semoga saja "keisengan" yang ada dapat dihentikan dan dijelaskan agar dapat termaafkan, dan kita mampu kembali bangkit untuk membangun karakter bangsa untuk menemukan Indonesia. Aamiin.
Minggu, 20 Januari 2013
keseragaman opini, siapa diuntungkan dan siapa yang dirugikan?
Minggu pagi, dingin, mendung dan tidak terdapat sesuatu hal untuk menebak keadaan. Media massa terjebak keseragaman, begitupun pikiran orang-orang, seperti jalan searah, lurus, bisu dan kaku dengan pemandangan yang satu macam saja, pohonnya sama, kendaraannya sama, warnanya sama dan kita adalah pelaku didalamnya, entah sekedar penumpang atau sedang jadi pengendara. Membosankan.
Pernah dulu, sekilas saja membaca tentang politik media dan pendapat saya media massa adalah salah satu dari pihak pemenang, saya katakan pemenang sebab yang saya sadari kehidupan yang saya temui tidak lebih sekedar perjudian, menang-kalah adalah konsekuensinya, dikatakan menang-kalah karena yang ada hanyalah persaingan, terutama dan yang pertama sekali adalah memenangkan opini publik.
Tentunya masih ingat dengan ramainya demonstran ketika pemerintah berencana menghapus subsidi BBM tahun 2012 kemarin, lewat opini masyarakat dan para demonstran dapat dilihat bahwa tidak satupun yang memikirkan konsekuensi logis dari penghapusan subsidi BBM tersebut, serta merta mendukung kelanggengan praktek kapitalisme-liberalist di negeri ini. Semua pihak seakan menolak, buruh dengan mudah keluar dari lingkungan kerjanya untuk turun berdemonstrasi bersama mahasiswa di jalanan, hampir ditiap kota selama kurang lebih satu minggu seperti itu.
Berbanding terbalik ketika perayaan "mayday" (hari buruh), sepertinya buruh yang entah karena menemui kesulitan atau karena sudah bosan atau karena hal lain hampir-hampir tidak terlihat berdemonstrasi, hanya skala kecil mahasiswa dan organisasi. Pada awalnya saya menangkap situasi dimana pihak-pihak yang berkepentingan berhasil menguasai opini publik bahwa rencana pemerintah tersebut tidak berpihak kepada rakyat kecil, sekaligus saya tidak mengerti kenapa muncul opini semacam itu, bukankah yang terjadi sebenarnya adalah pengalihan subsidi?.
Biaya pendidikan dan kesehatan adalah beban tanggungan tersendiri bagi masyarakat yang telah nyata bergeser pada status sekedar konsumen, sedangkan ada atau tidaknya subsidi BBM pengaruhnya terhadap masyarakat masih kecil ketimbang bagi para pengusaha dan para pemilik modal yang curang memanfaatkan subsidi tersebut sebagai peluang untuk memperoleh keuntungan dengan menekan biaya operasional. Toh setelah berhasil menggagalkan rencana pemerintah tersebut dijalanan malah sering terlihat rombongan-rombongan kendaraan mewah. Dari touring motor gede hingga motor berandalan yang melenggang tanpa empati. Dan jalanan lebih sering macet dengan kehadiran kendaraan-kendaraan terbaru dengan cc besar. Aneh.
Bukankah akan lebih baik jika masyarakat memperoleh hak untuk pendidikan dan kesehatan dengan mudah tanpa harus terbebani oleh biaya? Bukankah akan lebih baik untuk membangun sektor pendidikan dan kesehatan dengan fasilitas yang memadai dan merata untuk menunjang perjuangan masyarakat dalam membenahi sektor yang lain? (dalam hati) Siapa sebenarnya yang ada dibalik opini miring seperti ini?.
Demikian yang ada dalam alam pikir saya untuk hal tersebut, yang kemudian muncul pula spekulasi bahwa ada kemungkinan pemerintah sendiri yang sengaja melempar wacana untuk mengalihkan perhatian massa dari perayaan "mayday", sebab tahun ini rencana tersebut sepertinya mulai dibicarakan lagi kalaupun media massa tidak direpotkan dengan kabar banjir yang sensasional di wilayah paling sensasional Republik ini.
Pertarungan politik selalu diwarnai dengan upaya memenangkan dan mendominasi opini publik, pembentukan opini dan citra adalah hal yang utama dalam demokrasi mayoritas, pun seperti itu yang terjadi dalam pergaulan sehari-hari masyarakat yang memiliki kecenderungan untuk saling berkuasa, pengaruh-mempengaruhi, hasut-menghasut menjadi pilihan utama dari sebuah kemunafikkan. Tentu hal ini akan menjadi satu peluang untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyadari bahwa masyarakat selalu menyimpan pretensi, membentuk opini dan citra demi kepentingan pribadi dan golongan.
Sungguhpun saya masih berteguh hati, bhineka tunggal ika, tan hanna dharma mangrwa, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, tiada kebenaran yang mendua. Dan Tuhan senantiasa membinasakan kebathilan, tapi-sebagaimana yang ditulis oleh Pramoedya dalam karyanya "sekali peristiwa di Banten Selatan":
"Dimana-mana aku selalu dengar. Yang benar juga akhirnya yang menang. Itu benar; Benar sekali. Tapi kapan? Kebenaran tidak datang dari langit, dia mesti diperjuangkan untuk menjadi benar"
Pernah dulu, sekilas saja membaca tentang politik media dan pendapat saya media massa adalah salah satu dari pihak pemenang, saya katakan pemenang sebab yang saya sadari kehidupan yang saya temui tidak lebih sekedar perjudian, menang-kalah adalah konsekuensinya, dikatakan menang-kalah karena yang ada hanyalah persaingan, terutama dan yang pertama sekali adalah memenangkan opini publik.
Tentunya masih ingat dengan ramainya demonstran ketika pemerintah berencana menghapus subsidi BBM tahun 2012 kemarin, lewat opini masyarakat dan para demonstran dapat dilihat bahwa tidak satupun yang memikirkan konsekuensi logis dari penghapusan subsidi BBM tersebut, serta merta mendukung kelanggengan praktek kapitalisme-liberalist di negeri ini. Semua pihak seakan menolak, buruh dengan mudah keluar dari lingkungan kerjanya untuk turun berdemonstrasi bersama mahasiswa di jalanan, hampir ditiap kota selama kurang lebih satu minggu seperti itu.
Berbanding terbalik ketika perayaan "mayday" (hari buruh), sepertinya buruh yang entah karena menemui kesulitan atau karena sudah bosan atau karena hal lain hampir-hampir tidak terlihat berdemonstrasi, hanya skala kecil mahasiswa dan organisasi. Pada awalnya saya menangkap situasi dimana pihak-pihak yang berkepentingan berhasil menguasai opini publik bahwa rencana pemerintah tersebut tidak berpihak kepada rakyat kecil, sekaligus saya tidak mengerti kenapa muncul opini semacam itu, bukankah yang terjadi sebenarnya adalah pengalihan subsidi?.
Biaya pendidikan dan kesehatan adalah beban tanggungan tersendiri bagi masyarakat yang telah nyata bergeser pada status sekedar konsumen, sedangkan ada atau tidaknya subsidi BBM pengaruhnya terhadap masyarakat masih kecil ketimbang bagi para pengusaha dan para pemilik modal yang curang memanfaatkan subsidi tersebut sebagai peluang untuk memperoleh keuntungan dengan menekan biaya operasional. Toh setelah berhasil menggagalkan rencana pemerintah tersebut dijalanan malah sering terlihat rombongan-rombongan kendaraan mewah. Dari touring motor gede hingga motor berandalan yang melenggang tanpa empati. Dan jalanan lebih sering macet dengan kehadiran kendaraan-kendaraan terbaru dengan cc besar. Aneh.
Bukankah akan lebih baik jika masyarakat memperoleh hak untuk pendidikan dan kesehatan dengan mudah tanpa harus terbebani oleh biaya? Bukankah akan lebih baik untuk membangun sektor pendidikan dan kesehatan dengan fasilitas yang memadai dan merata untuk menunjang perjuangan masyarakat dalam membenahi sektor yang lain? (dalam hati) Siapa sebenarnya yang ada dibalik opini miring seperti ini?.
Demikian yang ada dalam alam pikir saya untuk hal tersebut, yang kemudian muncul pula spekulasi bahwa ada kemungkinan pemerintah sendiri yang sengaja melempar wacana untuk mengalihkan perhatian massa dari perayaan "mayday", sebab tahun ini rencana tersebut sepertinya mulai dibicarakan lagi kalaupun media massa tidak direpotkan dengan kabar banjir yang sensasional di wilayah paling sensasional Republik ini.
Pertarungan politik selalu diwarnai dengan upaya memenangkan dan mendominasi opini publik, pembentukan opini dan citra adalah hal yang utama dalam demokrasi mayoritas, pun seperti itu yang terjadi dalam pergaulan sehari-hari masyarakat yang memiliki kecenderungan untuk saling berkuasa, pengaruh-mempengaruhi, hasut-menghasut menjadi pilihan utama dari sebuah kemunafikkan. Tentu hal ini akan menjadi satu peluang untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyadari bahwa masyarakat selalu menyimpan pretensi, membentuk opini dan citra demi kepentingan pribadi dan golongan.
Sungguhpun saya masih berteguh hati, bhineka tunggal ika, tan hanna dharma mangrwa, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, tiada kebenaran yang mendua. Dan Tuhan senantiasa membinasakan kebathilan, tapi-sebagaimana yang ditulis oleh Pramoedya dalam karyanya "sekali peristiwa di Banten Selatan":
"Dimana-mana aku selalu dengar. Yang benar juga akhirnya yang menang. Itu benar; Benar sekali. Tapi kapan? Kebenaran tidak datang dari langit, dia mesti diperjuangkan untuk menjadi benar"
Sabtu, 19 Januari 2013
Eschapisme dan minyak wangi
Baru bisa menulis selepas ishak, sebenarnya dari tadi siang sudah menulis hanya tidak saya publikasikan, sengaja memang, menunggu waktu yang tepat. Kalaupun waktu tersebut tidak juga datang dan saya keburu tewas, maka ada kemungkinan yang menerbitkan adalah orang lain, sudah saya tinggali alamat dan passwordnya di dalam buku harian. Hanya sekedar catatan tentang segala yang pernah dan sedang saya hadapi.
Tidak perlu membahas hal tersebut saat ini, saya mau membahas tentang minyak wangi atau istilahnya parfum, dan bukan yang dicampuri alcohol tapi yang istilahnya "bibit", entah kenapa disebut seperti itu saya juga belum paham.
Awal saya mengenal hal ini juga terhitung barusan, mungkin baru setahun kemarin dan itupun karena ketidak sengajaan. Ketika saya mulai penasaran dengan hal-hal yang berbau mistik, inipun pada awalnya saya tidak merencanakan, saya hanya menelusuri etika kejawen waktu itu, dan pada saat itu saya juga sedang ingin belajar ilmu tajwid.
Setiap kali menemui orang-orang yang saya anggap sebagai narasumber (kejawen) selain membicarakan seputaran filosofi dalam kejawen selalu juga disertakan dengan keampuhan benda-benda pusaka dan ajimat milik orang-orang tersebut, selalu saja berbau wangi.
Pada suatu hari, seorang murid saya yang sering menginap di rumah saya menawari saya untuk mencoba menggunakan sebuah tasbeeh yang terbuat dari kayu yang ia dapatkan dari kakaknya. Ya saya gunakan, karena pikiran saya waktu itu jauh dari hal-hal mistik, baunya juga wangi. Jadilah saya tertarik dengan bau-bau tersebut~selain juga jadi penasaran akan hal-hal mistik. Dan ketertarikan saya bukanlah ketertarikan yang menganggap hal tersebut sebagai solusi dalam suatu permasalahan, mungkin sekedar penasaran kalau orang bilang.
Mencoba cari tahu tentang ragam jenis minyak wangi yang sering digunakan sebagai keperluan dibidang mistik dan ritual, bertanya pada murid saya yang lain yang saya ketahui dia adalah salah satu penggiat seni kuda lumping. Dapat empat nama minyak wangi: cendana, misik dan javaron.
Belum puas, saya bicarakan dengan ayah saya, saya ceritakan tentang tasbeeh milik murid saya itu, alasan saya membicarakan hal ini dengan ayah saya adalah meskipun ayah saya ini mengaku sebagai seorang sosialis-realis tapi pada kenyataannya saya ketahui beliau juga menyimpan beberapa pusaka. Mungkin sama halnya dengan Ir. Soekarno, atau mungkin tokoh-tokoh politik negeri ini memang demikian? Saya tidak tahu.
Tidak perlu dibahas, kita bahas minyak wanginya saja yang belakangan saya ketahui bahwa menggunakan wangi-wangian adalah termasuk sunnah, saya tidak dapat menyebutkan dalil-dalil dan hadis riwayatnya, terlalu panjang dan cukup saya tahu bahwa hal tersebut sunnah. Pun saya sekarang menyukainya selain sebagai hal baru bagi saya. Tak tanggung kinipun banyak yang menganggap saya adalah orang yang memiliki kemampuan mistik.
Pikir saya orang-orang tersebut terlanjur dalam untuk mengapresiasi kegemaran baru ini, selain memang pada dasarnya orang Indonesia, khususnya masyarakat Jawa masih juga cenderung memilih jalan pintas untuk menyelesaikan masalah, mungkin dengan mistiklah mereka dapat menyelesaikan masalah dengan cepat dan tanpa resiko. Dan ini salah.
Masalah ada adalah sebagai sarana agar orang bisa jadi lebih kuat, dan masalah tidak akan pernah selesai hanya dengan minyak wangi. Aneh-aneh saja.
Minyak wangi pada beberapa orang akan menumbuhkan perasaan nyaman ketika menggunakannya, saya pun demikian, sering saya merasa aman ketika mencium keharuman dan terkadang pula jadi nyaman dan malah jadi ingin tidur. Waktu sholat pun seperti itu, saya merasa nyaman dengan kebiasaan baru saya saat ini.
Bagi beberapa orang malah menggunakan minyak wangi untuk membantu kenyamanan saat melakukan meditasi, memanglah kenyamanan jadi syarat utama untuk mencapai konsentrasi, meski sering pula ditemui hal ini malah digunakan sebagai salah satu sarana "eschapism", salah satu karena banyak sarana termasuk menggunakan obat-obatan dan minuman keras. Mabuk.
Dengan seperti itu, mabuk (entah karena minuman, obat atau bahkan minyak wangi) maka pada dasarnya seseorang secara tidak langsung telah melarikan diri dari keterasingan menuju keterasingan yang lain yang tidak ia sadari juga berpotensi untuk menghancurkan dirinya sendiri.
Masyarakat di negeri ini pada umumnya menolak pemikiran Karl Marx karena ia pernah berpendapat bahwa agama adalah candu, tapi kebanyakan masyarakat negeri ini malah mencari pelarian dengan sarana-sarana yang tidak perlu dan tidak bermanfaat. Saya menulis ini dalam semerbak aroma kesturi hingga mengantuk dan kurang sanggup berpikir. Jadi cukuplah jurnal ini mengambang sampai disini, saya mau tidur.
Tidak perlu membahas hal tersebut saat ini, saya mau membahas tentang minyak wangi atau istilahnya parfum, dan bukan yang dicampuri alcohol tapi yang istilahnya "bibit", entah kenapa disebut seperti itu saya juga belum paham.
Awal saya mengenal hal ini juga terhitung barusan, mungkin baru setahun kemarin dan itupun karena ketidak sengajaan. Ketika saya mulai penasaran dengan hal-hal yang berbau mistik, inipun pada awalnya saya tidak merencanakan, saya hanya menelusuri etika kejawen waktu itu, dan pada saat itu saya juga sedang ingin belajar ilmu tajwid.
Setiap kali menemui orang-orang yang saya anggap sebagai narasumber (kejawen) selain membicarakan seputaran filosofi dalam kejawen selalu juga disertakan dengan keampuhan benda-benda pusaka dan ajimat milik orang-orang tersebut, selalu saja berbau wangi.
Pada suatu hari, seorang murid saya yang sering menginap di rumah saya menawari saya untuk mencoba menggunakan sebuah tasbeeh yang terbuat dari kayu yang ia dapatkan dari kakaknya. Ya saya gunakan, karena pikiran saya waktu itu jauh dari hal-hal mistik, baunya juga wangi. Jadilah saya tertarik dengan bau-bau tersebut~selain juga jadi penasaran akan hal-hal mistik. Dan ketertarikan saya bukanlah ketertarikan yang menganggap hal tersebut sebagai solusi dalam suatu permasalahan, mungkin sekedar penasaran kalau orang bilang.
Mencoba cari tahu tentang ragam jenis minyak wangi yang sering digunakan sebagai keperluan dibidang mistik dan ritual, bertanya pada murid saya yang lain yang saya ketahui dia adalah salah satu penggiat seni kuda lumping. Dapat empat nama minyak wangi: cendana, misik dan javaron.
Belum puas, saya bicarakan dengan ayah saya, saya ceritakan tentang tasbeeh milik murid saya itu, alasan saya membicarakan hal ini dengan ayah saya adalah meskipun ayah saya ini mengaku sebagai seorang sosialis-realis tapi pada kenyataannya saya ketahui beliau juga menyimpan beberapa pusaka. Mungkin sama halnya dengan Ir. Soekarno, atau mungkin tokoh-tokoh politik negeri ini memang demikian? Saya tidak tahu.
Tidak perlu dibahas, kita bahas minyak wanginya saja yang belakangan saya ketahui bahwa menggunakan wangi-wangian adalah termasuk sunnah, saya tidak dapat menyebutkan dalil-dalil dan hadis riwayatnya, terlalu panjang dan cukup saya tahu bahwa hal tersebut sunnah. Pun saya sekarang menyukainya selain sebagai hal baru bagi saya. Tak tanggung kinipun banyak yang menganggap saya adalah orang yang memiliki kemampuan mistik.
Pikir saya orang-orang tersebut terlanjur dalam untuk mengapresiasi kegemaran baru ini, selain memang pada dasarnya orang Indonesia, khususnya masyarakat Jawa masih juga cenderung memilih jalan pintas untuk menyelesaikan masalah, mungkin dengan mistiklah mereka dapat menyelesaikan masalah dengan cepat dan tanpa resiko. Dan ini salah.
Masalah ada adalah sebagai sarana agar orang bisa jadi lebih kuat, dan masalah tidak akan pernah selesai hanya dengan minyak wangi. Aneh-aneh saja.
Minyak wangi pada beberapa orang akan menumbuhkan perasaan nyaman ketika menggunakannya, saya pun demikian, sering saya merasa aman ketika mencium keharuman dan terkadang pula jadi nyaman dan malah jadi ingin tidur. Waktu sholat pun seperti itu, saya merasa nyaman dengan kebiasaan baru saya saat ini.
Bagi beberapa orang malah menggunakan minyak wangi untuk membantu kenyamanan saat melakukan meditasi, memanglah kenyamanan jadi syarat utama untuk mencapai konsentrasi, meski sering pula ditemui hal ini malah digunakan sebagai salah satu sarana "eschapism", salah satu karena banyak sarana termasuk menggunakan obat-obatan dan minuman keras. Mabuk.
Dengan seperti itu, mabuk (entah karena minuman, obat atau bahkan minyak wangi) maka pada dasarnya seseorang secara tidak langsung telah melarikan diri dari keterasingan menuju keterasingan yang lain yang tidak ia sadari juga berpotensi untuk menghancurkan dirinya sendiri.
Masyarakat di negeri ini pada umumnya menolak pemikiran Karl Marx karena ia pernah berpendapat bahwa agama adalah candu, tapi kebanyakan masyarakat negeri ini malah mencari pelarian dengan sarana-sarana yang tidak perlu dan tidak bermanfaat. Saya menulis ini dalam semerbak aroma kesturi hingga mengantuk dan kurang sanggup berpikir. Jadi cukuplah jurnal ini mengambang sampai disini, saya mau tidur.
Jumat, 18 Januari 2013
Etika dan kondisi jalan raya
Baru pulang dari latihan teater sama komplotan Karter langsung ngetik jurnal, masih juga dalam pencarian Indonesia, sebenarnya tadi siang juga sempet nulis tapi bukan jurnal, cerita dan belum juga selesai. Berat juga ternyata untuk bercerita.
Tadi pas di jalan sempat juga mengawasi seorang pejalan kaki yang menyeberang, depan gerbang sekolah ada zebra cross, aturannya adalah tempat orang menyeberang, sekarang dilengkapi pula dengan cat merah school area, untuk aturan jalan saja kita masih harus menggunakan bahasa Inggris. Sangat klasik.
Ada juga perlengkapan trafic light, denger-denger katanya akan disiapkan semacam trafic light di Surabaya sana yang pakai tombol untuk mengatur nyala lampu. Masalah ini saya masih awam, dan belum ada kabar lanjutan.
Biarlah, kata orang sekitar akan lebih aman dengan cara seperti itu, tapi masih mungkin, mungkin saja aman dan mungkin saja kondisinya tetap. Mengingat belum juga terbentuk etika dalam masyarakat, khususnya dalam hal ini adalah etika pengguna jalan.
Aturannya sudah cukup jelas dengan perangkat rambu-rambu yang bertebaran disetiap ruas jalan, termasuk juga dengan kehadiran Pak polisi yang siap menertibkan jalanan, sebagaimana yang diketahui anak-anak SD. Yang jadi masalah adalah etikanya, baik pengendara maupun pejalan kakinya, termasuk juga kendaraan-kendaraannya. Kendaraan memang hanya benda, bukan makhluk dan memang terlepas dari masalah etika, dan itu tidak berlaku di Indonesia yang mana kendaraan ternyata juga sering dan banyak melanggar etika dan estetika. Nah lho, bagaimana bisa?.
Coba lihat saja trend kendaraan masa kini, ukuran dan fasilitasnya yang termasuk kapasitas CC nya-yang terakhir ini saya sedikit ngawur tentang cc yang sebenarnya tidak begitu saya mengerti selain kata orang kebanyakan-kalau ccnya besar maka kecepatan akan tinggi dan bensinnya boros. Dan kendaraan dengan CC yang besar sangat banyak bertebaran di negara dengan hutang yang besar ini, saya pikir kendaraan-kendaraan tersebut melanggar kepantasan untuk berada di jalanan Indonesia raya. Pun juga dengan ukurannya, yang lagi trend adalah kendaraan dengan body lebar, benar-benar tidak pantas bergaya melenggang di jalanan sempit kota-kota nusantara.
Sering pula didapati sindiran yang bisu (bisu sebab tidak ada yang mendengar dan memperhatikan) mengenai kehadiran anak jalanan yang kumal diantara mobil-mobil mewah yang berlintasan. Ironis.
Kembali pada penyebrang jalan tadi, sementara trafic light belum dapat difungsikan, sementara yang nyala hanya warna kuning yang berkedip genit, jalan dari arah utara ke selatan kondisinya padat merayap, dan dari arah sebaliknya cukup beringas dengan kecepatan yang "terburu-buru". Maklum, sudah mulai masuk jam lima sore, tiap-tiap pekerja sedang ingin segera mencapai rumah, ada juga pelajar dan mungkin beberapa pekerja yang baru berangkat, semua diburu waktu. Pun dengan supir angkot yang sekaligus diburu setoran.
Setelah berhasil menerobos kemacetan si penyeberang berada di tengah jalan, sejajar dengan marka jalan menunggu lintasan yang beringas tadi sedikit tenang. Saya awasi dari kejauhan sepertinya ada kesempatan itu, sepi memang dan si penyeberang buru-buru melangkah. Mungkin tebakan saya dengan si penyeberang sedang mirip, yaitu kondisi jalan untuk menyeberang adalah aman, tapi diluar dugaan ada tiga sepeda motor terlihat sedang adu kecepatan. Awalnya saya hanya lihat dua, pun seperti itu yang dilihat oleh si penyeberang yang ternyata diantara dua tersebut ada satu yang terselip dan sedang asyik bermanufer.
Lolos dari dua kendaraan, hampir saja dengan satunya yang bermanufer hingga dekat dengan tepi jalan, si penyeberang sebenarnya sudah berada dalam batas aman tapi posisinya sejajar dengan kendaraan tadi, berlanjut dengan suara khas rem mendadak dan umpatan khas anak negeri. Keduanya hampir saja bertengkar kalau saja si pengendara motor tidak cepat sadar untuk selekasnya pulang.
Saya juga sudah terlalu sering mengalami hal tersebut hingga dalam pikiran saya sudah terkonsep suatu kesimpulan. Sering saya merasa jika hendak menyeberang bahwa pengendara-pengendara pada umumnya malah akan menambah kecepatan begitu tahu akan ada yang menyeberang. Entah, apa karena merasa dirugikan hingga merasa harus mengambil hak para penyeberang? Dan kesimpulan saya adalah yang kuat yang menang, siapa cepat dia dapat. Edan.
Etikanya adalah mendahulukan pejalan kaki, lebih-lebih adalah menjaga keselamatan bersama para pengguna jalan. Dan sepertinya tidak berlaku seiring dengan menguatnya hukum rimba disetiap sudut negeri ini, didalam gedung maupun di jalanan adalah sama saja, hukum rimba.
Mungkin tidak perlulah membahas hal yang demikian rumit, dimanapun dan kapanpun selama masih di negeri ini, ruas trotoar sering dimanfaatkan untuk berjualan, entah hanya dengan tenda ataupun dengan memakir kendaraan yang pasti mengurangi hak para pengguna jalan terutama keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki.
Jukir, tukang becak dan sopir angkot pun turut hadir merayakan keadaan, semuanya serba ingin menang, serba ingin berkuasa tanpa ada sedikitpun kesadaran untuk saling memanusiakan manusia.
Tadi pas di jalan sempat juga mengawasi seorang pejalan kaki yang menyeberang, depan gerbang sekolah ada zebra cross, aturannya adalah tempat orang menyeberang, sekarang dilengkapi pula dengan cat merah school area, untuk aturan jalan saja kita masih harus menggunakan bahasa Inggris. Sangat klasik.
Ada juga perlengkapan trafic light, denger-denger katanya akan disiapkan semacam trafic light di Surabaya sana yang pakai tombol untuk mengatur nyala lampu. Masalah ini saya masih awam, dan belum ada kabar lanjutan.
Biarlah, kata orang sekitar akan lebih aman dengan cara seperti itu, tapi masih mungkin, mungkin saja aman dan mungkin saja kondisinya tetap. Mengingat belum juga terbentuk etika dalam masyarakat, khususnya dalam hal ini adalah etika pengguna jalan.
Aturannya sudah cukup jelas dengan perangkat rambu-rambu yang bertebaran disetiap ruas jalan, termasuk juga dengan kehadiran Pak polisi yang siap menertibkan jalanan, sebagaimana yang diketahui anak-anak SD. Yang jadi masalah adalah etikanya, baik pengendara maupun pejalan kakinya, termasuk juga kendaraan-kendaraannya. Kendaraan memang hanya benda, bukan makhluk dan memang terlepas dari masalah etika, dan itu tidak berlaku di Indonesia yang mana kendaraan ternyata juga sering dan banyak melanggar etika dan estetika. Nah lho, bagaimana bisa?.
Coba lihat saja trend kendaraan masa kini, ukuran dan fasilitasnya yang termasuk kapasitas CC nya-yang terakhir ini saya sedikit ngawur tentang cc yang sebenarnya tidak begitu saya mengerti selain kata orang kebanyakan-kalau ccnya besar maka kecepatan akan tinggi dan bensinnya boros. Dan kendaraan dengan CC yang besar sangat banyak bertebaran di negara dengan hutang yang besar ini, saya pikir kendaraan-kendaraan tersebut melanggar kepantasan untuk berada di jalanan Indonesia raya. Pun juga dengan ukurannya, yang lagi trend adalah kendaraan dengan body lebar, benar-benar tidak pantas bergaya melenggang di jalanan sempit kota-kota nusantara.
Sering pula didapati sindiran yang bisu (bisu sebab tidak ada yang mendengar dan memperhatikan) mengenai kehadiran anak jalanan yang kumal diantara mobil-mobil mewah yang berlintasan. Ironis.
Kembali pada penyebrang jalan tadi, sementara trafic light belum dapat difungsikan, sementara yang nyala hanya warna kuning yang berkedip genit, jalan dari arah utara ke selatan kondisinya padat merayap, dan dari arah sebaliknya cukup beringas dengan kecepatan yang "terburu-buru". Maklum, sudah mulai masuk jam lima sore, tiap-tiap pekerja sedang ingin segera mencapai rumah, ada juga pelajar dan mungkin beberapa pekerja yang baru berangkat, semua diburu waktu. Pun dengan supir angkot yang sekaligus diburu setoran.
Setelah berhasil menerobos kemacetan si penyeberang berada di tengah jalan, sejajar dengan marka jalan menunggu lintasan yang beringas tadi sedikit tenang. Saya awasi dari kejauhan sepertinya ada kesempatan itu, sepi memang dan si penyeberang buru-buru melangkah. Mungkin tebakan saya dengan si penyeberang sedang mirip, yaitu kondisi jalan untuk menyeberang adalah aman, tapi diluar dugaan ada tiga sepeda motor terlihat sedang adu kecepatan. Awalnya saya hanya lihat dua, pun seperti itu yang dilihat oleh si penyeberang yang ternyata diantara dua tersebut ada satu yang terselip dan sedang asyik bermanufer.
Lolos dari dua kendaraan, hampir saja dengan satunya yang bermanufer hingga dekat dengan tepi jalan, si penyeberang sebenarnya sudah berada dalam batas aman tapi posisinya sejajar dengan kendaraan tadi, berlanjut dengan suara khas rem mendadak dan umpatan khas anak negeri. Keduanya hampir saja bertengkar kalau saja si pengendara motor tidak cepat sadar untuk selekasnya pulang.
Saya juga sudah terlalu sering mengalami hal tersebut hingga dalam pikiran saya sudah terkonsep suatu kesimpulan. Sering saya merasa jika hendak menyeberang bahwa pengendara-pengendara pada umumnya malah akan menambah kecepatan begitu tahu akan ada yang menyeberang. Entah, apa karena merasa dirugikan hingga merasa harus mengambil hak para penyeberang? Dan kesimpulan saya adalah yang kuat yang menang, siapa cepat dia dapat. Edan.
Etikanya adalah mendahulukan pejalan kaki, lebih-lebih adalah menjaga keselamatan bersama para pengguna jalan. Dan sepertinya tidak berlaku seiring dengan menguatnya hukum rimba disetiap sudut negeri ini, didalam gedung maupun di jalanan adalah sama saja, hukum rimba.
Mungkin tidak perlulah membahas hal yang demikian rumit, dimanapun dan kapanpun selama masih di negeri ini, ruas trotoar sering dimanfaatkan untuk berjualan, entah hanya dengan tenda ataupun dengan memakir kendaraan yang pasti mengurangi hak para pengguna jalan terutama keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki.
Jukir, tukang becak dan sopir angkot pun turut hadir merayakan keadaan, semuanya serba ingin menang, serba ingin berkuasa tanpa ada sedikitpun kesadaran untuk saling memanusiakan manusia.
Kamis, 17 Januari 2013
Hormat, kehormatan atau kemanusiaan?
Ini tadi. Hari yang aneh, mendapati hal-hal yang diluar dugaan dan ternyata kalau dipikir ada juga saling keterkaitan satu sama lain. Tidak mungkin saya tulis di blog ini, nanti malah jadi masalah pencemaran nama baik yang pada dasarnya nama-nama yang ada tidak pernah terlihat baik oleh umum. Saya tulis pokoknya saja, yaitu tentang kehormatan, selebihnya bisa dibaca dibuku harian tapi nanti saja kalau saya sudah mati.
Tiap-tiap manusia punya keinginan dan wewenang, seperti selalu ingin dihormati oleh orang lain bahkan terkadang kita bisa menjumpai apa yang disebut-sebut dengan "gila hormat". Katanya Kyai Anwar Zahid "kalau ingin dihormati orang itu sangat mudah, bawa saja bendera kemanapun anda pergi, pasti setiap orang yang jumpa akan hormat".
Istilah hormat sepertinya lebih tepat digunakan untuk membela kemanusiaan, atau hak serta wewenang tiap orang yang merasa ditindas, dan penindasan bisa terjadi dengan berbagai sebab, pun dengan berbagai bentuk. Yang pasti adalah akan ada pembelaan atas penindasan.
Mengapa kita selalu ingin dihormati? Mengapa kita harus menghormati orang lain? Bukankah sebenarnya cukup hanya mengakui kemanusiaan atau istilahnya "memanusiakan manusia" kita bisa menciptakan kenyamanan bagi diri kita dan orang lain?.
Tentu tidak cukup bagi kita ketika kita mengupayakan ketertundukkan dan penaklukkan, dan memang sudah tabiatnya manusia untuk berkuasa atas manusia yang lain, dengan cara apapun bertahan agar senantiasa dihormati oleh orang lain meskipun dengan cara-cara yang tidak terhormat. Dengan kata lain, dalam kita mengupayakan dan memperjuangkan posisi kita untuk selalu terhormat senantiasa terdapat juga kesempatan yang pada dasarnya membuat kita menjadi tidak terhormat.
Cukuplah kita membatasi diri pada kemanusiaan, penghargaan atas kemanusiaan pada dasarnya akan menempatkan orang pada posisi terhormat sebagai manusia, tidak perlu ada keinginan untuk disegani apalagi ditakuti oleh yang lain, sebab hal demikian malah menempatkan kita pada posisi yang tidak terhormat. Bayangkan ketika tiap-tiap orang yang kita temui takut pada kita, apa dengan demikian kita masih termasuk manusia? Bukan, sama sekali bukan.
Hal tersebut juga telah dipesankan dalam pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Awalnya dan yang terutama adalah menyadari kemanusiaan, mengenal manusia, siapa manusia? Tentunya makhluk Tuhan yang paling sempurna. Kesempurnaan manusia tidak hanya mengenai kehebatannya, tapi juga tentang kelemahannya. Manusia itu hebat karena manusia bisa berfikir, jadi tidak sekedar mengikuti insting tapi lebih didasarkan pada pertimbangan, etika dan estetikanya. Baik- buruk dan juga benar-salahnya yang sekaligus juga efek dari setiap tindakan. Dipikir.
Sedang kelemahan manusia itu pada dasarnya lebih banyak sama seperti kelemahan yang dimiliki oleh makhluk yang lain, yaitu hewan, saya bikin perbandingan antara manusia dengan hewan sebab makhluk lain diluar dua makhluk tersebut tidak saya kenali alias "nggak paham".
Kelemahan tersebut misalnya saja manusia itu masih bisa lapar, sakit ataupun mengantuk, maka upaya yang dapat dilakukan adalah mengatasi kelemahan tersebut. Kalau lapar ya makan, kalau mengantuk ya tidur. Dan tidak cukup seperti itu, tidak mungkin seorang manusia ketika merasa mengantuk langsung tidur sebagaimana seekor kucing, ngantuk dan terus tidur habis perkara, tidak. Kucingpun pada dasarnya masih memilih-milih lokasi tidur yang aman dan nyaman. Manusia masih harus berfikir untuk hal tersebut, sebab sangat aneh jika kita tertidur didepan pintu sebagaimana seekor kucing.
Demikianlah kita sebagai manusia sedapat mungkin untuk mampu mengenal kemanusiaan, setelah mengenal segala kesempurnaan manusia yang ada pada kita sebagai manusia, maka ada baiknya untuk memahami manusia yang lain, memanusiakan manusia. Jika kita merasa sakit ketika dipukul ya jangan memukul, jika kita merasa sakit "hati" ketika dihina yang jangan menghina. Adil untuk mencapai manusia yang beradab.
Kemanusiaan itu tidak berlebihan dan berkekurangan, sebagaimana pandangan Friedrich Nietzsche dalam Zarathustra, "jikasatu tujuan bagi kemanusiaan masih kurang, tidaklah yang kurang itu-kemanusiaan itu sendiri?"
Lewat tulisan ini saya tidak hanya merefleksikan tiap-tiap kejadian, tapi saya gunakan juga kesempatan ini untuk berpesan, tentang posisi saya dan kesadaran saya saat ini.
nb.
aku
sedang dalam merendahkan diri
seperti sebelumnya
tak lagi merendahkan hati
sekedar untuk mendidik kesombongan
dan berdialog tentang kemanusiaan
kerendah hatian
kini, hanya akan tumbuhkan kecongkakan
maka
kuasailah dan perlakukanlah sesuka hati
aku
sedang dalam merendahkan diri
itupun juga untuk kehormatanmu
kesadaran-kemanusiaanmu
maka
suatu saat nanti
aku berharap:
kau mampu memanusiakan aku
Tiap-tiap manusia punya keinginan dan wewenang, seperti selalu ingin dihormati oleh orang lain bahkan terkadang kita bisa menjumpai apa yang disebut-sebut dengan "gila hormat". Katanya Kyai Anwar Zahid "kalau ingin dihormati orang itu sangat mudah, bawa saja bendera kemanapun anda pergi, pasti setiap orang yang jumpa akan hormat".
Istilah hormat sepertinya lebih tepat digunakan untuk membela kemanusiaan, atau hak serta wewenang tiap orang yang merasa ditindas, dan penindasan bisa terjadi dengan berbagai sebab, pun dengan berbagai bentuk. Yang pasti adalah akan ada pembelaan atas penindasan.
Mengapa kita selalu ingin dihormati? Mengapa kita harus menghormati orang lain? Bukankah sebenarnya cukup hanya mengakui kemanusiaan atau istilahnya "memanusiakan manusia" kita bisa menciptakan kenyamanan bagi diri kita dan orang lain?.
Tentu tidak cukup bagi kita ketika kita mengupayakan ketertundukkan dan penaklukkan, dan memang sudah tabiatnya manusia untuk berkuasa atas manusia yang lain, dengan cara apapun bertahan agar senantiasa dihormati oleh orang lain meskipun dengan cara-cara yang tidak terhormat. Dengan kata lain, dalam kita mengupayakan dan memperjuangkan posisi kita untuk selalu terhormat senantiasa terdapat juga kesempatan yang pada dasarnya membuat kita menjadi tidak terhormat.
Cukuplah kita membatasi diri pada kemanusiaan, penghargaan atas kemanusiaan pada dasarnya akan menempatkan orang pada posisi terhormat sebagai manusia, tidak perlu ada keinginan untuk disegani apalagi ditakuti oleh yang lain, sebab hal demikian malah menempatkan kita pada posisi yang tidak terhormat. Bayangkan ketika tiap-tiap orang yang kita temui takut pada kita, apa dengan demikian kita masih termasuk manusia? Bukan, sama sekali bukan.
Hal tersebut juga telah dipesankan dalam pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Awalnya dan yang terutama adalah menyadari kemanusiaan, mengenal manusia, siapa manusia? Tentunya makhluk Tuhan yang paling sempurna. Kesempurnaan manusia tidak hanya mengenai kehebatannya, tapi juga tentang kelemahannya. Manusia itu hebat karena manusia bisa berfikir, jadi tidak sekedar mengikuti insting tapi lebih didasarkan pada pertimbangan, etika dan estetikanya. Baik- buruk dan juga benar-salahnya yang sekaligus juga efek dari setiap tindakan. Dipikir.
Sedang kelemahan manusia itu pada dasarnya lebih banyak sama seperti kelemahan yang dimiliki oleh makhluk yang lain, yaitu hewan, saya bikin perbandingan antara manusia dengan hewan sebab makhluk lain diluar dua makhluk tersebut tidak saya kenali alias "nggak paham".
Kelemahan tersebut misalnya saja manusia itu masih bisa lapar, sakit ataupun mengantuk, maka upaya yang dapat dilakukan adalah mengatasi kelemahan tersebut. Kalau lapar ya makan, kalau mengantuk ya tidur. Dan tidak cukup seperti itu, tidak mungkin seorang manusia ketika merasa mengantuk langsung tidur sebagaimana seekor kucing, ngantuk dan terus tidur habis perkara, tidak. Kucingpun pada dasarnya masih memilih-milih lokasi tidur yang aman dan nyaman. Manusia masih harus berfikir untuk hal tersebut, sebab sangat aneh jika kita tertidur didepan pintu sebagaimana seekor kucing.
Demikianlah kita sebagai manusia sedapat mungkin untuk mampu mengenal kemanusiaan, setelah mengenal segala kesempurnaan manusia yang ada pada kita sebagai manusia, maka ada baiknya untuk memahami manusia yang lain, memanusiakan manusia. Jika kita merasa sakit ketika dipukul ya jangan memukul, jika kita merasa sakit "hati" ketika dihina yang jangan menghina. Adil untuk mencapai manusia yang beradab.
Kemanusiaan itu tidak berlebihan dan berkekurangan, sebagaimana pandangan Friedrich Nietzsche dalam Zarathustra, "jikasatu tujuan bagi kemanusiaan masih kurang, tidaklah yang kurang itu-kemanusiaan itu sendiri?"
Lewat tulisan ini saya tidak hanya merefleksikan tiap-tiap kejadian, tapi saya gunakan juga kesempatan ini untuk berpesan, tentang posisi saya dan kesadaran saya saat ini.
nb.
aku
sedang dalam merendahkan diri
seperti sebelumnya
tak lagi merendahkan hati
sekedar untuk mendidik kesombongan
dan berdialog tentang kemanusiaan
kerendah hatian
kini, hanya akan tumbuhkan kecongkakan
maka
kuasailah dan perlakukanlah sesuka hati
aku
sedang dalam merendahkan diri
itupun juga untuk kehormatanmu
kesadaran-kemanusiaanmu
maka
suatu saat nanti
aku berharap:
kau mampu memanusiakan aku
Rabu, 16 Januari 2013
Dari pentas drama ke panggung politik
Tadi pas piket pagi sempat baca artikel Jawa Pos hari ini, judulnya "negeri dagelan" saya lupa baca penulisnya sebab terlanjur asik dengan paparan penulis yang menurut saya-kalau boleh dianalogikan adalah seperti seperti seorang pemain sepak bola yang akrobatik.
Dalam bayang-bayang pengaruh tulisan tersebut saya pun mau nulis tentang ragam drama yang sepertinya jadi inspirasi bagi tokoh-tokoh politik masa kini. Saya tidak begitu mengenal tentang tradisi seni peran, ada pengkategorian "tradisional" dan modern, sedang yang katanya modern ini hanyalah bentuk tradisional di negeri asalnya, dan yang dikatakan tradisional adalah seni peran yang berasal dari negeri sendiri. Seni peran yang modern pun juga terpilah-pilah dinegeri asalnya, ada yang dikatakan klasik dan ada yang dikatakan neoklasik, ada pula yang modern dan post modern. Nah lho, bingung kan?.
Maka cukuplah saya mengikuti pendapat umum, bahwa yang tradisional saya kata klasik dalam negeri dan yang modern adalah yang kotemporer. Dan tidak perlu rasanya mengulas ini, sebab sasaran saya dalam jurnal kali ini bukan bidang ini.
Seni peran klasik dalam negeri memiliki ciri khas pementasan tanpa naskah, dialog dalam pementasan biasanya merupakan hasil dari tradisi lisan, mungkin terdapat banyak sekali improvisasi tapi selama yang saya lihat dan saya temui sepertinya tidak ada sama sekali improvisasi. Salut.
Dengan seni peran kotemporer yang akrab dengan lembaran-lembaran naskah penuh dialog yang harus dihafal dan mempersilahkan improvisasi serta dukungan teknologi juga pada dasarnya memiliki rambu-rambu untuk tetap dalam skenario sang sutradara. Kalau sutradara maunya humor ya harus lucu, sebaliknya kalau yang diinginkan adalah tampilan serius ya harus serius.
Dari WS Rendra kita kenal istilah "kritik sastra" yang dikatakan masih lemah tradisinya di negeri ini, istilah apa lagi ini? Sepanjang saya ketahui adalah semacam konsep seni untuk rakyat, yaitu karya seni yang bersuara atas penderitaan rakyat, terlahir atas dasar penderitaan rakyat. Mungkin mirip dengan konsep yang digagas oleh LEKRA, tapi siapa yang tahu kebenarannya tentu orang-orang sastra dan para ahlinya.
Dan dari seni klasik tradisional, khususnya Jawa, kita kenal istilah "pasemon" saya dapati istilah ini dari seorang seniman reog, seorang saja tidak lebih dan namanya patut disebut dalam tulisan ini, Pak Pi'i-dulu salah satu tukang kebun di SMP.
"Pasemon" sebagaimana penjelasan Pak Pi'i ini asalnya dari kata "nyemoni"/"semon" atau sindiran atau menyindir. Memang sudah kebiasaan masyarakat tradisional Jawa untuk tidak melawan penguasa secara "frontal" karena feodalisme juga menanamkan budaya-kalau tidak ingin disebut doktrin "ewuh pakewuh" perasaan hormat, segan, kepada seseorang, karena kedudukan, kharisma, senioritas, kebaikan, sehingga kemudian menimbulkan semacam “kebergantungan” yang begitu besar pada orang tersebut. Terdapat kecenderungan nepotisme dalam hal ini, mungkin juga kolusi. Ujung-ujungnya ya korupsi.
Ini malah ngelantur ngg'jelas...
kembali pada permasalahan awal, yaitu tentang aksi politik yang menggelitik diatas pentas drama "singgahsana Indonesia raya", dimana rakyat tetap sebagai penonton yang dipersilahkan menangkap pesan pementasan sesuai sudut pandang masing-masing tanpa harus didengar. Ya seperti ketika nonton pertandingan sepak bola di depan televisi, dimana kesebelasan kesayangan sedang bermain buruk dan mengalami kekalahan, sudah pasti yang muncul adalah umpatan-umpatan yang tidak terdengar oleh pemain, lha wong yang hadir di stadion yang menyaksikan secara langsung dan juga sedang mengumpat sama sekali tidak didengarkan. Edan.
Demikianlah, para aktor politik bermain penuh dengan improvisasi tanpa harus risau dengan protes-protes dari penonton, sedangkan telah disepakati bersama bahwasannya negara ini menganut kedaulatan rakyat, yang mana seharusnya rakyat bukan terbatas hanya sebagai penonton.
Sekedar catatan bingung dari seorang rakyat yang ling-lung. Mumpung kopi masih hangat coba kita saksikan pementasan drama di depan layar kaca... cheers...
Dalam bayang-bayang pengaruh tulisan tersebut saya pun mau nulis tentang ragam drama yang sepertinya jadi inspirasi bagi tokoh-tokoh politik masa kini. Saya tidak begitu mengenal tentang tradisi seni peran, ada pengkategorian "tradisional" dan modern, sedang yang katanya modern ini hanyalah bentuk tradisional di negeri asalnya, dan yang dikatakan tradisional adalah seni peran yang berasal dari negeri sendiri. Seni peran yang modern pun juga terpilah-pilah dinegeri asalnya, ada yang dikatakan klasik dan ada yang dikatakan neoklasik, ada pula yang modern dan post modern. Nah lho, bingung kan?.
Maka cukuplah saya mengikuti pendapat umum, bahwa yang tradisional saya kata klasik dalam negeri dan yang modern adalah yang kotemporer. Dan tidak perlu rasanya mengulas ini, sebab sasaran saya dalam jurnal kali ini bukan bidang ini.
Seni peran klasik dalam negeri memiliki ciri khas pementasan tanpa naskah, dialog dalam pementasan biasanya merupakan hasil dari tradisi lisan, mungkin terdapat banyak sekali improvisasi tapi selama yang saya lihat dan saya temui sepertinya tidak ada sama sekali improvisasi. Salut.
Dengan seni peran kotemporer yang akrab dengan lembaran-lembaran naskah penuh dialog yang harus dihafal dan mempersilahkan improvisasi serta dukungan teknologi juga pada dasarnya memiliki rambu-rambu untuk tetap dalam skenario sang sutradara. Kalau sutradara maunya humor ya harus lucu, sebaliknya kalau yang diinginkan adalah tampilan serius ya harus serius.
Dari WS Rendra kita kenal istilah "kritik sastra" yang dikatakan masih lemah tradisinya di negeri ini, istilah apa lagi ini? Sepanjang saya ketahui adalah semacam konsep seni untuk rakyat, yaitu karya seni yang bersuara atas penderitaan rakyat, terlahir atas dasar penderitaan rakyat. Mungkin mirip dengan konsep yang digagas oleh LEKRA, tapi siapa yang tahu kebenarannya tentu orang-orang sastra dan para ahlinya.
Dan dari seni klasik tradisional, khususnya Jawa, kita kenal istilah "pasemon" saya dapati istilah ini dari seorang seniman reog, seorang saja tidak lebih dan namanya patut disebut dalam tulisan ini, Pak Pi'i-dulu salah satu tukang kebun di SMP.
"Pasemon" sebagaimana penjelasan Pak Pi'i ini asalnya dari kata "nyemoni"/"semon" atau sindiran atau menyindir. Memang sudah kebiasaan masyarakat tradisional Jawa untuk tidak melawan penguasa secara "frontal" karena feodalisme juga menanamkan budaya-kalau tidak ingin disebut doktrin "ewuh pakewuh" perasaan hormat, segan, kepada seseorang, karena kedudukan, kharisma, senioritas, kebaikan, sehingga kemudian menimbulkan semacam “kebergantungan” yang begitu besar pada orang tersebut. Terdapat kecenderungan nepotisme dalam hal ini, mungkin juga kolusi. Ujung-ujungnya ya korupsi.
Ini malah ngelantur ngg'jelas...
kembali pada permasalahan awal, yaitu tentang aksi politik yang menggelitik diatas pentas drama "singgahsana Indonesia raya", dimana rakyat tetap sebagai penonton yang dipersilahkan menangkap pesan pementasan sesuai sudut pandang masing-masing tanpa harus didengar. Ya seperti ketika nonton pertandingan sepak bola di depan televisi, dimana kesebelasan kesayangan sedang bermain buruk dan mengalami kekalahan, sudah pasti yang muncul adalah umpatan-umpatan yang tidak terdengar oleh pemain, lha wong yang hadir di stadion yang menyaksikan secara langsung dan juga sedang mengumpat sama sekali tidak didengarkan. Edan.
Demikianlah, para aktor politik bermain penuh dengan improvisasi tanpa harus risau dengan protes-protes dari penonton, sedangkan telah disepakati bersama bahwasannya negara ini menganut kedaulatan rakyat, yang mana seharusnya rakyat bukan terbatas hanya sebagai penonton.
Sekedar catatan bingung dari seorang rakyat yang ling-lung. Mumpung kopi masih hangat coba kita saksikan pementasan drama di depan layar kaca... cheers...
Selasa, 15 Januari 2013
Kekerasan dan hilangnya suatu bangsa
Ada yang tanya "mengapa judul blognya jadi Mencari Indonesia? Bukankah Indonesia itu ada dan tidak sedang hilang?" Demikian tadi pas ngobrol lewat fesbuk. Saya jelaskan tadi bahwa bukannya Indonesia menghilang dari muka bumi ditelan luapan air laut atau dicoret sama PBB karena masalah persepakbolaan yang rumit dan seperti tidak memiliki penyelesaian.
Wilayah kepulauan Indonesia memang masih ada-mungkin hampir mirip dengan wilayah kepulauan jaman Majapahit dahulu, sebagaimana juga dengan penghuninya, pulau-pulau ini masih dihuni oleh masyarakat yang juga (mungkin) hampir sama karakteristiknya dengan jaman feodal tersebut. Tapi Indonesianya yang patut dipertanyakan, Indonesia yang disepakati sebagai nama suatu bangsa sejak tahun 1928 dan memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, suatu bangsa yang dibangun atas dasar keragaman hingga dalam lambang negaranya turut mengusung semboyan "Bhineka tunggal ika".
Patut dipertanyakan karena hingga hari ini belum juga terlihat yang dinamakan orang Indonesia yaitu masyarakat pancasila. Meskipun sipenanya protes saya tetap saja pada pendirian saya untuk mencari Indonesia, petanya adalah sejarah, kompasnya pancasila. Tetap akan saya cari.
Kalaupun boleh jujur, dalam otak saya sekarang mengenai kehancuran suatu bangsa yang katanya "berbhineka" ini adalah sejak 1965, terlihat jelas bahwa bangsa itu enggan untuk "berbhineka". Perbedaan harus dihilangkan meskipun harus dengan cara kekerasan.
Dan kekerasan bisa jadi merupakan salah satu solusi untuk menganulir masalah, menganulir bukan menyelesaikan. Dan kekerasan beragam macamnya, yang cukup populer adalah tindakan fisik yang pada dasarnya muncul dengan didahului kekerasan verbal. Bagi saya semua tindak kekerasan awalnya dari kekerasan verbal.
Bukan hanya semisal bentrok antar suporter yang berawal dari saling ejek, tapi juga seperti tindakan yang jadi kegemaran Amrik, name calling.Upaya mendiskreditkan pihak lain tentunya tidak akan lepas dari tindakan verbal untuk menjatuhkan kewibawaan sasaran selain untuk juga memperoleh dukungan dari banyak pihak.
Dan ini adalah kebiasaan dalam proses pengaruh-mempengaruhi dalam masyarakat sekalipun. Istilahnya "rasan-rasan" atau "ngomongin orang" atau kalau sedang keterlaluan "hasut-menghasut" dan kalaupun biar keren sebut saja "provokasi". Yang terakhir perlu ada pendalaman lebih lanjut, sekarang tidak perlu dibahas, cukup membahas kekerasan dan hilangnya Indonesia yang didamba, Indonesia yang berpancasila, Indonesia yang berbhineka tunggal ika.
Apa hubungannya runtuhnya sebuah bangsa yang menghuni kepulauan Indonesia dengan kekerasan? Tentu ada, sebab peradaban suatu bangsa itu ada karena etika dan estetikanya, bangsa hilang karena kecenderungan biadab yang tidak mengindahkan etika-estetika. Etika akan selalu dicari dan disepakati sebagai temuan suatu bangsa yang mencoba untuk eksis. Nah, sebuah bangsa hilang karena tidak mencapai kesepakatan tersebut, jangankan mempermasalahkan estetika, yang terjadi adalah upaya untuk saling mendominasi satu sama lain dan sudah pasti berujung pada kekerasan yang merupakan-secara tidak langsung pemusnahan satu sama lain.
Kita menolak kekerasan, kekerasan dalam bentuk apapun sebab kita juga menolak tindakan tidak manusiawi. Peradaban adalah hasil, produk dari budaya, dan kita akan selalu menggunakan produk budaya yang nyaman bagi kemanusiaan.
Sedikit sobekan dari Pramoedya Ananta Toer:
"Betapa bedanya bangsa-bangsa Hindia ini dari bangsa Eropa. Disana setiap orang yang memberikan sesuatu yang baru pada umat manusia dengan sendirinya mendapatkan tempat yang selayaknya di dunia dan di dalam sejarahnya. Di Hindia, pada bangsa-bangsa Hindia, nampaknya setiap orang takut tak mendapat tempat dan berebutan untuk menguasainya."
Wilayah kepulauan Indonesia memang masih ada-mungkin hampir mirip dengan wilayah kepulauan jaman Majapahit dahulu, sebagaimana juga dengan penghuninya, pulau-pulau ini masih dihuni oleh masyarakat yang juga (mungkin) hampir sama karakteristiknya dengan jaman feodal tersebut. Tapi Indonesianya yang patut dipertanyakan, Indonesia yang disepakati sebagai nama suatu bangsa sejak tahun 1928 dan memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, suatu bangsa yang dibangun atas dasar keragaman hingga dalam lambang negaranya turut mengusung semboyan "Bhineka tunggal ika".
Patut dipertanyakan karena hingga hari ini belum juga terlihat yang dinamakan orang Indonesia yaitu masyarakat pancasila. Meskipun sipenanya protes saya tetap saja pada pendirian saya untuk mencari Indonesia, petanya adalah sejarah, kompasnya pancasila. Tetap akan saya cari.
Kalaupun boleh jujur, dalam otak saya sekarang mengenai kehancuran suatu bangsa yang katanya "berbhineka" ini adalah sejak 1965, terlihat jelas bahwa bangsa itu enggan untuk "berbhineka". Perbedaan harus dihilangkan meskipun harus dengan cara kekerasan.
Dan kekerasan bisa jadi merupakan salah satu solusi untuk menganulir masalah, menganulir bukan menyelesaikan. Dan kekerasan beragam macamnya, yang cukup populer adalah tindakan fisik yang pada dasarnya muncul dengan didahului kekerasan verbal. Bagi saya semua tindak kekerasan awalnya dari kekerasan verbal.
Bukan hanya semisal bentrok antar suporter yang berawal dari saling ejek, tapi juga seperti tindakan yang jadi kegemaran Amrik, name calling.Upaya mendiskreditkan pihak lain tentunya tidak akan lepas dari tindakan verbal untuk menjatuhkan kewibawaan sasaran selain untuk juga memperoleh dukungan dari banyak pihak.
Dan ini adalah kebiasaan dalam proses pengaruh-mempengaruhi dalam masyarakat sekalipun. Istilahnya "rasan-rasan" atau "ngomongin orang" atau kalau sedang keterlaluan "hasut-menghasut" dan kalaupun biar keren sebut saja "provokasi". Yang terakhir perlu ada pendalaman lebih lanjut, sekarang tidak perlu dibahas, cukup membahas kekerasan dan hilangnya Indonesia yang didamba, Indonesia yang berpancasila, Indonesia yang berbhineka tunggal ika.
Apa hubungannya runtuhnya sebuah bangsa yang menghuni kepulauan Indonesia dengan kekerasan? Tentu ada, sebab peradaban suatu bangsa itu ada karena etika dan estetikanya, bangsa hilang karena kecenderungan biadab yang tidak mengindahkan etika-estetika. Etika akan selalu dicari dan disepakati sebagai temuan suatu bangsa yang mencoba untuk eksis. Nah, sebuah bangsa hilang karena tidak mencapai kesepakatan tersebut, jangankan mempermasalahkan estetika, yang terjadi adalah upaya untuk saling mendominasi satu sama lain dan sudah pasti berujung pada kekerasan yang merupakan-secara tidak langsung pemusnahan satu sama lain.
Kita menolak kekerasan, kekerasan dalam bentuk apapun sebab kita juga menolak tindakan tidak manusiawi. Peradaban adalah hasil, produk dari budaya, dan kita akan selalu menggunakan produk budaya yang nyaman bagi kemanusiaan.
Sedikit sobekan dari Pramoedya Ananta Toer:
"Betapa bedanya bangsa-bangsa Hindia ini dari bangsa Eropa. Disana setiap orang yang memberikan sesuatu yang baru pada umat manusia dengan sendirinya mendapatkan tempat yang selayaknya di dunia dan di dalam sejarahnya. Di Hindia, pada bangsa-bangsa Hindia, nampaknya setiap orang takut tak mendapat tempat dan berebutan untuk menguasainya."
Senin, 14 Januari 2013
Dari Pramoedya Ananta Toer (sebuah harapan tentang Indonesia yang lebih mengenal kemanusiaan)
Senin sore yang murung, langit mendung. Sempat meriang tadi, pulang dari tempat ngajar langsung terkapar, seharian kena angin. Kini sedikit mendingan. Judul dan alamat blog sengaja saya ganti jadi "Mencari Indonesia" terinspirasi kemarin saat share satu judul ke fesbuk, saya tulis "minggu pagi yang cerah, kita cari Indonesia".
Jika dihitung harinya, selama pencarian saat ini sudah masuk hari ke 17 pencarian bangsa yang hilang, Indonesia. Tapi mungkin lebih baik dihitung dari hari kemarin, jadi ini adalah hari ke dua pendarian Indonesia. Bukannya hilang, tapi saya rasa memang belum pernah ditemukan, bukan wilayahnya, tapi jati dirinya. Indonesia.
Tadi, disela-sela waktu saya sempatkan baca "Jalan raya pos, Jalan Daendels" karya Pramodya Ananta Toer. Sudah kali ketiga saya baca buku ini. Sangat menarik bagi saya untuk selalu membaca karya-karya Pramoedya, saya banyak terinspirasi oleh tulisan-tulisan semacamnya.
"... Instituut Boedi Oetomo, disingkat IBO. Di bawah pimpinan ayahku sendiri sekolah ini sudah banting setir jadi sekolah nasional pada tahun 30-an. Apa pula sekolah nasional itu?! Pendeknya secara tidak langsung-karenatidak mungkin secara langsung-diajar membenci penjajahan Barat, Eropa, Belanda. Sebaliknya mengagungkan bangsa sendiri, tak peduli ilmiah atau tidak, asal memerosotkan wibawa kolonial. Teks pelajaran dibikin sendiri tentu. Yang bisa jadi bukti hukum diberikan secara lisan.
Dalam gerakan nasional sekolah nasional punya sahamnya sendiri. Kekuasaan kolonial menamakannya sekolah liar, wilde scholen. Untuk melawannya kekuasaan kolonial mengeluarkan Wilde Scholen Ordonantie, dan memerintahkan menutup semua. Perlawanan terhadapnya telah memaksa kekuasaan kolonial mencabutnya. Sementara itu, antara lain ayahku, masuk tahanan, biarpun tidak lama, hanya tiga harmal (hari-malam)."
Dari sobekan cerita diatas-saya ambil-dari karyanya Pramoedya "Jalan raya pos, jalan Daendels"- saya menangkap pada masa kekuasaan kolonial kesadaran berbangsa itu lahir dari bangku sekolah, dan waktu itu ada dua macam sekolah, yaitu sekolah liar-sebagaimana diceritakan-dan sekolah kolonial.
Saya pikir yang namanya sekolah liar itu adalah semacam tandingan untuk menghantam kemapanan kolonial yang serta merta mencari kemanusiaan. Dan juga dengan keberadaan pesantren yang menurut saya pada masa itu mengusung ciri khas yang berangkat dari adat-kebiasaan masyarakat. Pondok pesantren, pondok berarti rumah menginap, dan pesantren ini adalah dari istilah santri atau orang yang menuntut ilmu. Inipun kalau pikiran saya benar, sementara saya sedang gemar menebak-nebak.
Perkembangannya, keberadaan sekolah nasional menggantikan sekolah kolonial dengan hengkangnya kekuasaan kolonial dari Indonesia, bukan sebagai pihak yang menang tapi (sangat nyata sekali) sebagai pemeran pengganti, tradisi kolonial masih terjaga dan rapi terwarisi, begitupun dengan pesantren yang ternyata malah kehilangan andil dalam membangun masyarakat. Yang terakhir ini, semoga saya benar-benar salah menebak.
Baik sekolah maupun pesantren kita kenal sebagai lembaga pendidikan, namanya seperti itu berarti adalah tempatnya orang berubah, saya pribadi tidak suka dan tidak akan mungkin bersepakat dengan model kolonial yang dalam sistem pendidikannya hanya mempertahankan kemapanan kelas sosial. Pendidikan, sekolah adalah tempat orang berubah, dari tidak tahu menjadi tahu dan dari tidak mengerti menjadi mengerti, terutama sekali mengenai kemanusiaan, sekolah adalah agen perubahan, kalaupun boleh bisa juga dikatakan sebagai agen perbaikan, mengenal manusia terutama. Memperbaiki kemanusiaan.
Sobekan lain dari karya yang sama:
"Dengan semakin panjangnya Jalan Raya Pos, Daendels memperluas tanampaksa kopi di daerah-daerah yang cocok untuk tanaman itu. Tanampaksa ini kemudian dihidupkan kembali semasa Orba. Hanya yang ditanampaksakan adalah tebu. Barangkali juga sama seperti semasa Orba, semasa kompeni harga diturunkan atau dimanipulasi semasa panen.Boleh jadi, karena selama rakyat kecil pribumi tidak berdaya, maka jadi sumber datangnya kekayaan bagi pihak yang sebelum berhasil membuat mereka tidak berdaya. Memang menarik memperhatikan bagaimana kompeni mampu meninggalkan warisan sistim dalam alam kemerdekaan".
Tentunya penguasa sebelumnya tidak akan begitu saja merelakan wilayah kekuasaan dan kekayaan rampasan dirampok begitu saja, dan pastinya sejak dari datangnya kolonial ke tanah air, mereka sudah memanfaatkan watak feodalisme yang ada, dan toh hingga kini watak tersebut seperti benar-benar terpelihara.
Akhir kata mengutip pula karya Pramoedya "Indonesia adalah negeri budak. Budak di antara bangsa dan budak bagi bangsa-bangsa lain".
Jika dihitung harinya, selama pencarian saat ini sudah masuk hari ke 17 pencarian bangsa yang hilang, Indonesia. Tapi mungkin lebih baik dihitung dari hari kemarin, jadi ini adalah hari ke dua pendarian Indonesia. Bukannya hilang, tapi saya rasa memang belum pernah ditemukan, bukan wilayahnya, tapi jati dirinya. Indonesia.
Tadi, disela-sela waktu saya sempatkan baca "Jalan raya pos, Jalan Daendels" karya Pramodya Ananta Toer. Sudah kali ketiga saya baca buku ini. Sangat menarik bagi saya untuk selalu membaca karya-karya Pramoedya, saya banyak terinspirasi oleh tulisan-tulisan semacamnya.
"... Instituut Boedi Oetomo, disingkat IBO. Di bawah pimpinan ayahku sendiri sekolah ini sudah banting setir jadi sekolah nasional pada tahun 30-an. Apa pula sekolah nasional itu?! Pendeknya secara tidak langsung-karenatidak mungkin secara langsung-diajar membenci penjajahan Barat, Eropa, Belanda. Sebaliknya mengagungkan bangsa sendiri, tak peduli ilmiah atau tidak, asal memerosotkan wibawa kolonial. Teks pelajaran dibikin sendiri tentu. Yang bisa jadi bukti hukum diberikan secara lisan.
Dalam gerakan nasional sekolah nasional punya sahamnya sendiri. Kekuasaan kolonial menamakannya sekolah liar, wilde scholen. Untuk melawannya kekuasaan kolonial mengeluarkan Wilde Scholen Ordonantie, dan memerintahkan menutup semua. Perlawanan terhadapnya telah memaksa kekuasaan kolonial mencabutnya. Sementara itu, antara lain ayahku, masuk tahanan, biarpun tidak lama, hanya tiga harmal (hari-malam)."
Dari sobekan cerita diatas-saya ambil-dari karyanya Pramoedya "Jalan raya pos, jalan Daendels"- saya menangkap pada masa kekuasaan kolonial kesadaran berbangsa itu lahir dari bangku sekolah, dan waktu itu ada dua macam sekolah, yaitu sekolah liar-sebagaimana diceritakan-dan sekolah kolonial.
Saya pikir yang namanya sekolah liar itu adalah semacam tandingan untuk menghantam kemapanan kolonial yang serta merta mencari kemanusiaan. Dan juga dengan keberadaan pesantren yang menurut saya pada masa itu mengusung ciri khas yang berangkat dari adat-kebiasaan masyarakat. Pondok pesantren, pondok berarti rumah menginap, dan pesantren ini adalah dari istilah santri atau orang yang menuntut ilmu. Inipun kalau pikiran saya benar, sementara saya sedang gemar menebak-nebak.
Perkembangannya, keberadaan sekolah nasional menggantikan sekolah kolonial dengan hengkangnya kekuasaan kolonial dari Indonesia, bukan sebagai pihak yang menang tapi (sangat nyata sekali) sebagai pemeran pengganti, tradisi kolonial masih terjaga dan rapi terwarisi, begitupun dengan pesantren yang ternyata malah kehilangan andil dalam membangun masyarakat. Yang terakhir ini, semoga saya benar-benar salah menebak.
Baik sekolah maupun pesantren kita kenal sebagai lembaga pendidikan, namanya seperti itu berarti adalah tempatnya orang berubah, saya pribadi tidak suka dan tidak akan mungkin bersepakat dengan model kolonial yang dalam sistem pendidikannya hanya mempertahankan kemapanan kelas sosial. Pendidikan, sekolah adalah tempat orang berubah, dari tidak tahu menjadi tahu dan dari tidak mengerti menjadi mengerti, terutama sekali mengenai kemanusiaan, sekolah adalah agen perubahan, kalaupun boleh bisa juga dikatakan sebagai agen perbaikan, mengenal manusia terutama. Memperbaiki kemanusiaan.
Sobekan lain dari karya yang sama:
"Dengan semakin panjangnya Jalan Raya Pos, Daendels memperluas tanampaksa kopi di daerah-daerah yang cocok untuk tanaman itu. Tanampaksa ini kemudian dihidupkan kembali semasa Orba. Hanya yang ditanampaksakan adalah tebu. Barangkali juga sama seperti semasa Orba, semasa kompeni harga diturunkan atau dimanipulasi semasa panen.Boleh jadi, karena selama rakyat kecil pribumi tidak berdaya, maka jadi sumber datangnya kekayaan bagi pihak yang sebelum berhasil membuat mereka tidak berdaya. Memang menarik memperhatikan bagaimana kompeni mampu meninggalkan warisan sistim dalam alam kemerdekaan".
Tentunya penguasa sebelumnya tidak akan begitu saja merelakan wilayah kekuasaan dan kekayaan rampasan dirampok begitu saja, dan pastinya sejak dari datangnya kolonial ke tanah air, mereka sudah memanfaatkan watak feodalisme yang ada, dan toh hingga kini watak tersebut seperti benar-benar terpelihara.
Akhir kata mengutip pula karya Pramoedya "Indonesia adalah negeri budak. Budak di antara bangsa dan budak bagi bangsa-bangsa lain".
Minggu, 13 Januari 2013
Kesadaran berbangsa
Dua hari kemarin tidak nulis disini, soalnya lagi mengisi opini di Warung Kopi Demokrasi salah satu blog yang saya kelola, dan kemarin saya sempatkan untuk nulis satu naskah pendek "Suara-suara" sebenarnya bukan naskah drama tapi sajak, dan sudah lama saya tulis sebelumnya. Dua judul sajak saya campur jadi satu lalu saya pecah-pecah lagi dalam dialog.
Cuaca ekstrim bermunculan dimedia massa berpadu dengan kabar dari Pak Roy Suryo yang baru saja diangkat sebagai Menpora. Mengintip facebook dan Google "plus" kondisinya juga serupa, di jalur FB kemarin ada pemberitaan tentang Roma Irama yang menyatakan dirinya selain seorang seniman juga adalah seorang negarawan dan diikuti komentar serta-merta hujatan. Dari G+ lewat postingan seorang teman yang "entah"-karena saya juga tidak begitu mengenal beliaunya, ada diskusi tentang pancasila dan kebangsaan.
Mending bahas yang terakhir itu, diskusi tentang pancasila dan kebangsaan, kalau saya simak dalam diskusi tersebut adalah permasalahan kesadaran berbangsa dan ini akan jadi hal utama disini, sebab pada kenyataannya kesadaran berbangsa hampir-hampir tidak ada di negeri ini selain gebyar kebanggaan kosong yang seringnya malah mengedepankan sentimen dan kebencian.
Muncul satu pertanyaan "sejak kapan bangsa Indonesia itu ada?". Sejak kapan, sebab sebelumnya tidak ada, nama Indonesia sendiri tidak muncul begitu saja dari masyarakat yang menghuni pulau-pulau nusantara, nama itu muncul dari buku yang ditulis orang Eropa, A. Bastian. Dan barulah bangsa Indonesia menyatakan diri menjadi satu bangsa lewat sumpah pemuda. Mungkin pendeknya demikian.
Tapi sampai hari ini kita belum mampu membentuk identitas kebangsaan kita meskipun pancasila pernah kita sepakati sebagai ideologi yang sekaligus falsafah negara, salah satu fungsi ideologi adalah membentuk identitas suatu bangsa untuk membedakannya dengan bangsa yang lain, tapi dengan kita itu belum terjadi. Kita belum mampu membangun identitas kita sebagai satu bangsa dalam diri kita meski rumusannya telah ada: pancasila.
Pernah saya nulis di Buletin Garis tentang kandungan pancasila- tentunya dari sudut pandang saya yang mencoba menafsirkan pancasila dari karakter tokoh wayang "Pandawa-pancasila" yang saya hadirkan dan tanpa komentar, mungkin terlalu njelimet dan terkesan mengada-ada. Mungkin. Di kolom Warung Kopi Demokrasi juga saya tinggali catatan "Pancasila sebagai wajah nasionalisme Indonesia" yang semuanya itu sekedar untuk menafsirkan pancasila dalam usaha saya mencari bangsa yang hilang, Indonesia.
Rupanya kita terlalu sibuk berpolitik hingga melupakan identitas kita yang pernah dicita-citakan sebagai bangsa yang ramah-tamah, berbudi luhur dan mengedepankan kegotong-royongan ditengah perbedaan, bhineka tunggal ika. Rumus sederhananya seperti ini, tiap-tiap kebudayaan sudah pasti membawa normanya sendiri-sendiri meskipun yang namanya moralitas memiliki dasar kemanusiaan dan kemanusiaan adalah sama dimanapun dan kapanpun tapi setiap budaya/kebudayaan memiliki normanya sendiri, misalnya terkait tentang kesopanan dan adat istiadat. Nah dengan begitu dapat kita ambil kesimpulan bahwa moral yang memiliki dasar kemanusiaan dan bersifat universal itu adalah hasil dari hubungan dialogis antar budaya yang ada, berdialog menuju universalisme moral.
Dan kita sebagai suatu bangsa yang dibangun dari keragaman budaya ini sudah memiliki rumusan tersebut, universalisme moral, hanya saja belum juga tertanam dalam diri kita tentang kesadaran berbangsa yang memiliki identitas kebangsaan. Namun hal ini tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan penafsiran tunggal terhadap pancasila sebagaimana yang pernah dilakukan baik oleh kekuasaan orde lama maupun orde baru. Penafsiran tunggal terhadap pancasila hanya akan memunculkan apatisme dan dendam. Sedang kita harus selalu berdialog mencari identitas kita sebagai suatu bangsa. Indonesia.
Cukup berat memang, belum lagi pola pikir warisan kolonial yang belum lagi terhapus dibenak kita masing-masing, yaitu tentang suatu bangunan masyarakat atas dasar kelas sosial. Kita bisa saksikan sendiri faktanya, dimana hukum yang diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat ternyata masih juga berpihak pada kelas tertentu dalam masyarakat. Dan inilah yang maha penting untuk segera dibenahi, sebab kesadaran berbangsa tidak akan terwujud jika hukum memihak.
Minggu pagi yang cerah, hampir siang belum juga mandi... ngopi-ngopi, cheers...
Cuaca ekstrim bermunculan dimedia massa berpadu dengan kabar dari Pak Roy Suryo yang baru saja diangkat sebagai Menpora. Mengintip facebook dan Google "plus" kondisinya juga serupa, di jalur FB kemarin ada pemberitaan tentang Roma Irama yang menyatakan dirinya selain seorang seniman juga adalah seorang negarawan dan diikuti komentar serta-merta hujatan. Dari G+ lewat postingan seorang teman yang "entah"-karena saya juga tidak begitu mengenal beliaunya, ada diskusi tentang pancasila dan kebangsaan.
Mending bahas yang terakhir itu, diskusi tentang pancasila dan kebangsaan, kalau saya simak dalam diskusi tersebut adalah permasalahan kesadaran berbangsa dan ini akan jadi hal utama disini, sebab pada kenyataannya kesadaran berbangsa hampir-hampir tidak ada di negeri ini selain gebyar kebanggaan kosong yang seringnya malah mengedepankan sentimen dan kebencian.
Muncul satu pertanyaan "sejak kapan bangsa Indonesia itu ada?". Sejak kapan, sebab sebelumnya tidak ada, nama Indonesia sendiri tidak muncul begitu saja dari masyarakat yang menghuni pulau-pulau nusantara, nama itu muncul dari buku yang ditulis orang Eropa, A. Bastian. Dan barulah bangsa Indonesia menyatakan diri menjadi satu bangsa lewat sumpah pemuda. Mungkin pendeknya demikian.
Tapi sampai hari ini kita belum mampu membentuk identitas kebangsaan kita meskipun pancasila pernah kita sepakati sebagai ideologi yang sekaligus falsafah negara, salah satu fungsi ideologi adalah membentuk identitas suatu bangsa untuk membedakannya dengan bangsa yang lain, tapi dengan kita itu belum terjadi. Kita belum mampu membangun identitas kita sebagai satu bangsa dalam diri kita meski rumusannya telah ada: pancasila.
Pernah saya nulis di Buletin Garis tentang kandungan pancasila- tentunya dari sudut pandang saya yang mencoba menafsirkan pancasila dari karakter tokoh wayang "Pandawa-pancasila" yang saya hadirkan dan tanpa komentar, mungkin terlalu njelimet dan terkesan mengada-ada. Mungkin. Di kolom Warung Kopi Demokrasi juga saya tinggali catatan "Pancasila sebagai wajah nasionalisme Indonesia" yang semuanya itu sekedar untuk menafsirkan pancasila dalam usaha saya mencari bangsa yang hilang, Indonesia.
Rupanya kita terlalu sibuk berpolitik hingga melupakan identitas kita yang pernah dicita-citakan sebagai bangsa yang ramah-tamah, berbudi luhur dan mengedepankan kegotong-royongan ditengah perbedaan, bhineka tunggal ika. Rumus sederhananya seperti ini, tiap-tiap kebudayaan sudah pasti membawa normanya sendiri-sendiri meskipun yang namanya moralitas memiliki dasar kemanusiaan dan kemanusiaan adalah sama dimanapun dan kapanpun tapi setiap budaya/kebudayaan memiliki normanya sendiri, misalnya terkait tentang kesopanan dan adat istiadat. Nah dengan begitu dapat kita ambil kesimpulan bahwa moral yang memiliki dasar kemanusiaan dan bersifat universal itu adalah hasil dari hubungan dialogis antar budaya yang ada, berdialog menuju universalisme moral.
Dan kita sebagai suatu bangsa yang dibangun dari keragaman budaya ini sudah memiliki rumusan tersebut, universalisme moral, hanya saja belum juga tertanam dalam diri kita tentang kesadaran berbangsa yang memiliki identitas kebangsaan. Namun hal ini tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan penafsiran tunggal terhadap pancasila sebagaimana yang pernah dilakukan baik oleh kekuasaan orde lama maupun orde baru. Penafsiran tunggal terhadap pancasila hanya akan memunculkan apatisme dan dendam. Sedang kita harus selalu berdialog mencari identitas kita sebagai suatu bangsa. Indonesia.
Cukup berat memang, belum lagi pola pikir warisan kolonial yang belum lagi terhapus dibenak kita masing-masing, yaitu tentang suatu bangunan masyarakat atas dasar kelas sosial. Kita bisa saksikan sendiri faktanya, dimana hukum yang diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat ternyata masih juga berpihak pada kelas tertentu dalam masyarakat. Dan inilah yang maha penting untuk segera dibenahi, sebab kesadaran berbangsa tidak akan terwujud jika hukum memihak.
Minggu pagi yang cerah, hampir siang belum juga mandi... ngopi-ngopi, cheers...
Langganan:
Postingan (Atom)